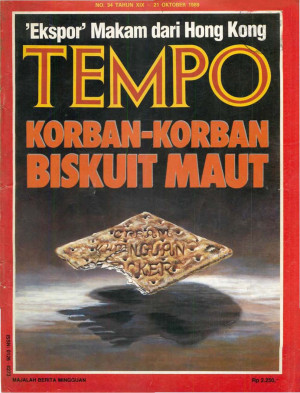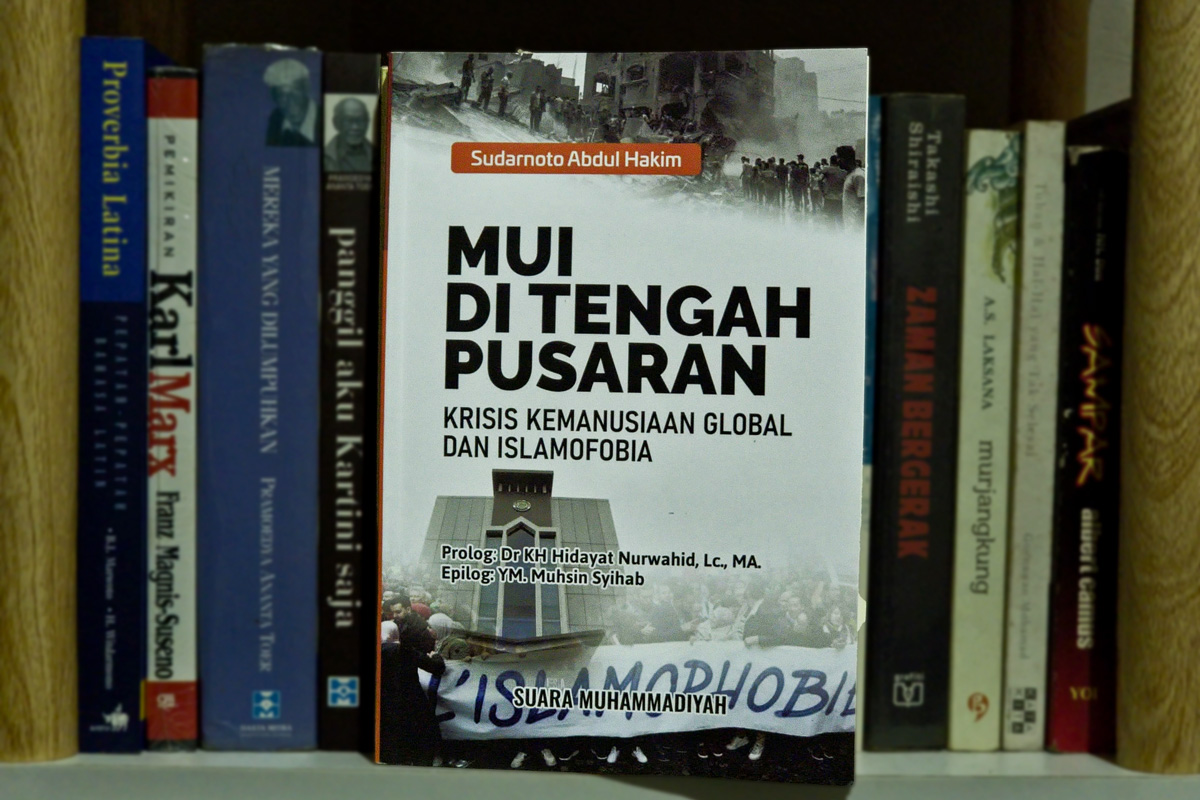MENUNGGU GODOT Karya: Samuel Beckett (terjemahan W.S. Rendra) Pemain: Didi Petet, Yoseph Ginting, Sena Utoyo, Edie Riwanto, Yogi Yose Sutradara: Wahyu Sihombing Produksi: Teater Lembaga, 13 s/d 17 Oktober 1989 di Gedung Kesenian Jakarta SAMUEL Beckett adalah sebuah tonggak besar dalam dunia teater. Dengan Waiting for Godot (1952) membuahkan hadiah Nobel tahun 1969 ia memulai sebuah tradisi baru yang oleh kritikus Martin Esselin kemudian disebut teater absurd. Kecenderungan ini melanda juga sampai ke Indonesia. Istilah absurd kini menjadi populer di kalanan kaum muda (teater) kita. Bukan karena kegandrungan orang terhadap absurditas, tetapi karena kerancuan pemakaiannya. Istilah itu sering menjadi amat dangkal dipraktekkan. Ia sering disamakan dengan segala sesuatu yang "asal aneh" atau "asal tak bisa dimengerti". Lebih lanjut lagi, "ketidakmengertian" itu sering bukan disebabkan karena obyek yang harus dimengerti itu tidak masuk akal, tetapi karena ia yang mencoba mengertinya ternyata tidak atau belum berpikir logis. Kendati Esselin menyatakan absurd (secara harfiah berarti mustahil, tak masuk akal), jenis teater itu adalah usaha yang penuh "akal" untuk memaparkan inti kenyataan. Sering teater absurd dilawankan dengan teater realis. Untuk pengikut realisme, teater absurd itu tidak real, karena di dalamnya tidak ada karakter, tidak ada plot cerita, bahkan bahasa tidak lagi terasa menyambung. Sementara itu, buat pengikut teater absurd, realisme di panggung justru tidak realistis karena ia telah melakukan penyederhanaan, pengarahan pada kenyataan yang sebenarnya agar bisa dipaketkan di panggung. Teater absurd mengenalkan dirinya sebagai usaha menyampaikan inti dari kenyataan, bukan wadak dari kenyataan. Segala ketidakmustahilan yang ada adalah bayangan dari kenyataan. Di Barat teater absurd adalah reaksi dari para pencari kebenaran terhadap teater yang menjadi mapan dan macet. Absurditas adalah hasil puncak kebuntuan manusia yang sudah mencapai puncaknya dalam mengisolasi dirinya. Tetapi di Timur apa yang oleh Barat dianggap sebagai absurditas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang merupakan terobosan-terobosan -- kearifan Timur untuk membangun harmoni. Tiba-tiba dengan agak mengejutkan Wahyu Sihombing, lulusan -- dan kemudian. pengajar -- ATNI yang dikenal sebagai pemuka realisme di dalam teater, memilih naskah Menunggu Godot. Didukung oleh para mahasiswa IKJ, pada tahun 1982, ia mementaskan naskah itu dengan mendapat pujian dari kritikus teater. Dan di Gedung Kesenian Jakarta, 13 s/d 17 Oktober, ia mencoba mengulangi suksesnya itu. Tiga jam lebih, Wahyu Sihombing, dengan dukungan pemain yang sama, menghadirkan tontonan tanpa musik. Hombing mempercayakan seluruhnya pada kemampuan bekas-bekas mahasiswanya, yang kini sudah menjadi bagian dari staf pengajar IKJ. Panggung hanya dihuni sebuah pohon kering yang berbentuk mirip salib. Di bawahnya jatuhan daun. Tak jauh dari sana nampak gundukan tanah. Menunggu Godot adalah kisah penantian Godot oleh Vladimir alias Didi (Yoseph Ginting) dengan Estragon alias Gogo (Didi Petet). Tidak seorang pun tahu siapa Godot dan apakah dia akan datang. Yang muncul adalah Pozzo (Sena Utoyo) dengan budaknya Lucky (Edie Riwanto). Kemudian seorang anak kecil (Yogi Yose) yang mengabarkan pesan Godot bahwa ia tak akan datang hari itu. Di babak kedua suasana penantian berulang. Pozzo dan Lucky muncul lagi, tetapi keduanya sudah berubah. Pozzo jadi buta, sedangkan Lucky gagu. Tetapi nasib Gogo dan Didi tak berubah. Mereka tetap menanti. Sang anak kecil juga kembali datang dan menyampaikan pesan yang sama bahwa Godot tak bisa datang hari itu. Suasana tak bergerak. Dalam memainkan naskah Beckett ini biasanya ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama, memainkannya utuh dan menghormati setiap penggal dialog yang akan nampak sarat. gelap, dan belepotan falsafah. Yang kedua adalah melakukan editing dan menyampaikannya secara santai, sehingga akan muncul nuansa-nuansa komik. Baik Bengkel Teater W.S. Rendra (1969) maupun Teater Lembaga cenderung menempuh cara yang kedua. Hanya bedanya, karena Rendra adalah seorang penyair, Godot di tangannya jadi teateral dan puitik. Sementara itu, di tangan Hombing, Godot jadi realistik. Dengan pemain-pemain yang memiliki stamina yang bagus serta keterampilan teknis yang baik, Teater Lembaga hadir memikat. Panggung tidak hanya menjadi arena diskusi tok, tetapi menyuguhkan peristiwa. Yoseph dan Didi Petet nampak kompak, mereka mengenal betul perannya dan hubungan antara keduanya. Sering muncul kelucuan-kelucuan yang segar karena Didi Petet melontarkan dialog dengan pas. Pozzo yang dimainkan Sena dengan karikatural kadang kurang selektif. Sementara Didi dan Yoseph yang bermain secara realistik, Sena jadi aneh tetapi toh tetap lucu. Sementara itu, Edie Riwanto sebagai Lucky bagus. Munculnya tokoh anak yang dimainkan oleh seorang anak-anak (Yogi Yose) pas dengan konsep realisme Hombing. Sebagai sebuah "tontonan", pertunjukan Teater Lembaa ini berhasil. Sebagai sebuah interpretasi ia sah. Baik sutradara maupun para pemainnya telah menunjukkan kerja keras. Hanya saya masih kehilangan sesuatu. Nuansa paling penting dari karya ini, "nasib manusia", belum muncul. Menunggu Godot Teater Lembaga baru menontonkan kita tentang "dua orang yang menunggu", bukan nasib manusia untuk "menunggu". Saya kira itu adalah risiko yang sulit dihindari kalau kita mencoba menangkap teater absurd dengan realisme. Karena ia berbicara tentang permasalahan abstrak tetapi kongkret dalam kehidupan diperlukan pendekatan yang lebih spiritual. Konsep "tontonan"-nya pun agak berbeda. Karikatur atau surealisme, misalnya, akan lebih memancing intinya keluar. Putu wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini