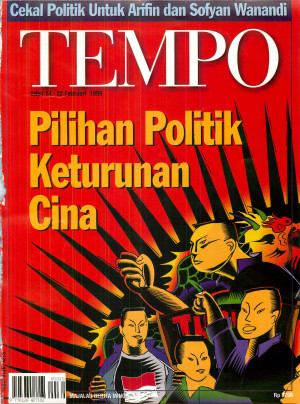Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peresmian Bienal Yogya VI di selasar ruang pameran Taman Budaya Yogyakarta, 8 Februari lalu, berlangsung sama saja dengan peresmian-peresmian bienal sebelumnya. Namun, di balik upacara yang terkesan rutin itu, sedang terjadi metamorfosis yang progresif.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo