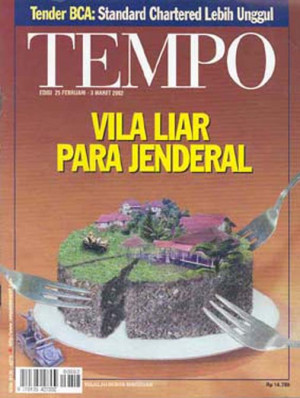Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meminta saya (mementaskan). Pertimbangan mereka, ekspresi dalam opera ini berkesan Islam dalam pluralitas. Saya sendiri malah tidak tahu hal itu. Mereka mendapat kesan begitu karena membicarakan Diponegoro yang memiliki simbol Islam. Dalam pementasan itu ada musik Mozart, gamelan Jawa, musik Islam, dan toh juga berbicara tentang Nyi Roro Kidul, yang memang ada dalam realitas sosial orang Jawa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo