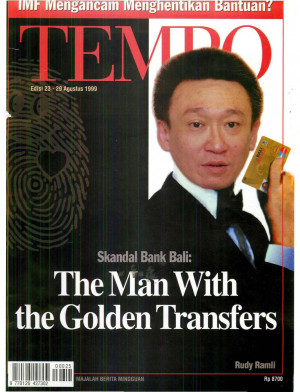Sejarah, menurut Voltaire, adalah serangkaian dongeng yang telah disepakati. Lalu, siapakah yang ikut dalam kesepakatan itu?
Untuk 32 tahun lamanya, kita mengenal sebuah versi besar—yang ditanamkan ke generasi demi generasi—tentang apa yang terjadi pada 30 September 1965. Hingga sekarang, kita tak pernah mengetahui secara jelas, apa yang sesungguhnya terjadi saat itu. "Sejarah"—versi Orde Baru—telah berupaya menuliskan dalam kurikulum pelajaran sejarah dari SD hingga universitas dengan menggunakan medium film, sinetron, komik, novel, dan berbagai perangkat lainnya untuk sebuah "kesepakatan" tentang apa yang terjadi saat itu. Orde Baru menamakannya "G30S-PKI", tetapi para sejarawan yang memiliki integritas, macam Asvi Warman Adam, dengan konsisten menyebutnya "G30S" karena, "PKI itu hanya salah satu versi saja," tuturnya.
Begitu banyak yang terbunuh, yang tertangkap, yang tersiksa, yang mendekam di penjara untuk puluhan tahun lamanya, tetapi kita tak tahu kriteria apa yang digunakan untuk penangkapan dan pembunuhan itu. Sejarah, untuk 32 tahun, adalah sebuah dongeng yang hanya disepakati oleh mereka yang berkuasa. Akibatnya, untuk generasi yang lahir pada 1960-an, sejarah menjadi bagian dari semacam press release sebuah rezim, tanpa tantangan untuk mengadu interpretasi atau menggali sebuah alternatif.
"Komunisme" akhirnya bukan suatu pemikiran yang patut diperdebatkan dalam sebuah wacana yang kritis, tetapi, seperti diutarakan Melani Budianta dalam novel Merajut Harkat karya Putu Oka Sukanta, komunisme menjadi "simbol kejagatan yang boleh dimusnahkan seperti hama". Generasi pasca-1960-an akhirnya tak memiliki kesempatan untuk mempelajari pemikiran-pemikiran para political thinker, seperti Marx dan Hegel, dalam sebuah diskusi sehat yang kritis—sehingga mampu mandiri untuk menyatakan kelemahan pemikiran tersebut—tanpa digiring dengan gaya patriarkis oleh kurikulum dan strategi politik pemerintah.
Karena itu, sejak jatuhnya Soeharto, 21 Mei setahun silam, berbagai buku yang ditulis oleh "suara dari seberang sana" mulai bermunculan untuk sebuah keseimbangan informasi.
Ada terjemahan buku karya Carmel Budiardjo, seorang aktivis hak asasi manusia warga Inggris—yang selama ini dikenal sebagai musuh Orde Baru—berjudul Bertahan Hidup di Gulag Indonesia; biografi Ketua Baperki Siauw Giok Tjhan yang ditulis oleh putranya, Siauw Tiong Djin; pengalaman di penjara Sulami, seorang pejabat Gerwani, yang diungkapkan melalui Perempuan-Kebenaran dan Penjara; dan dua buah novel yang meluncur bersamaan awal bulan ini, yakni Layang-Layang itu Tak Lagi Mengepak Tinggi-Tinggi karya Martin Aleida, yang pada masa lalu bekerja sebagai wartawan Harian Rakyat; dan novel Merajut Harkat karya Putu Oka Sukanta, seorang penyair Lekra.
Tidak semua pelaku ini dekat dengan "pusat kekuasaan". Carmel Budiardjo, seorang pengajar ekonomi—yang belakangan menjadi aktivis hak asasi manusia—memang mengenal Aidit; Latief mengenal Bung Karno dan Soeharto; Siauw pernah menjadi menteri pada masa Bung Karno, sementara Martin Aleida, wartawan Harian Rakyat, dan Putu Oka, penyair, adalah dua korban yang sama sekali jauh dari lingkaran kekuasaan.
Yang mempersamakan para penulis buku ini adalah mereka ikut disapu bersih, dicampakkan ke dalam tahanan, "kamp", atau penjara—dengan atau tanpa pengadilan—untuk kesalahan yang tak pernah diketahui, kecuali asosiasinya pada apa yang dikenal sebagai "kelompok kiri".
Tentu saja buku-buku itu bukanlah buku sejarah dalam arti akademis, dan mereka semua memang tidak berpretensi menjadi sejarawan. Tetapi, "suara dari sebelah sana" memang sesuatu yang belum didengarkan, yang belum pernah diberi kesempatan hidup dan memberi kesaksian sejujur-jujurnya. Mereka berkisah tentang apa yang dialami pada saat penangkapan, penyiksaan macam apa yang harus mereka derita, dan apa yang mereka ketahui atau tak mereka ketahui seputar peristiwa 30 September 1965.
Kesaksian itu ditulis dalam berbagai bentuk. Kesaksian Carmel Budiardjo, Siauw Giok Tjhan, dan Sulami ditulis dalam bentuk yang biografis, sementara Martin Aleida dan Putu Oka Sukanta menulis fiksi yang, tentu saja, tak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Karena buku-buku ini bukan sekumpulan buku sejarah yang akademis, tentu saja kita tak akan menemukan berbagai lubang-lubang dalam kisah G30S versi buku putih keluaran pemerintah Orde Baru. Padahal, memang masih banyak sisi kontroversial yang perlu diungkap, misalnya seperti yang diutarakan sejarawan Asvi Warman: bagaimana sebetulnya peran Sukarno dalam peristiwa ini? Siapakah sosok Syam Kamaruzaman, Ketua CC PKI yang menerjemahkan perintah Letkol Untung untuk menangkap para jenderal hidup atau mati itu? Apakah tokoh yang dianggap misterius ini adalah seorang militer yang menyusup ke PKI, atau sebaliknya dia seorang PKI yang menyusup ke militer? Kenapa tokoh kunci semacam Aidit ditembak? Lalu, pertanyaan yang paling sering dilontarkan dan tak pernah dijawab dengan seragam adalah: berapa sesungguhnya jumlah korban peristiwa 30 September itu?
Menurut pendiri Yayasan Tapol, Koesalah Soebagyo Toer, terdapat berbagai versi tentang jumlah korban peristiwa itu. Soemarno, pemimpin tim pencari fakta pada masa itu, menyebut resmi bahwa jumlah korban adalah 78.000. "Padahal, secara tidak resmi dia mengatakan jumlahnya 10 kali lipat angka itu," ujar adik sastrawan Pramoedya Ananta Toer itu. Ada versi satu juta, ada versi lain tiga juta. Yang mana yang benar, hingga sekarang masih belum jelas.
Kelima buku ini tak akan menjawab fakta-fakta itu. Tetapi, mereka akan mampu membiarkan generasi pasca-1960-an untuk memiliki alternatif berpikir dan bersikap secara kritis terhadap sejarah. Salah satu contohnya, ungkapan Sulami bahwa tak pernah ada anggota gerwani yang menari-nari di Lubangbuaya ketika para jenderal disekap di sana, adalah satu suara yang perlu didengar sebagai bukti tentang rekayasa sejarah.
Bagaimanapun, untuk bersikap imbang, kedua "sumber", baik pemerintah maupun korban, akan memiliki kelemahan. Menurut Asvi, kelemahan utama buku putih versi pemerintah adalah karena buku putih itu dibuat berdasarkan data dari persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa). "Bagaimanapun, data yang didapat dari interogasi tak akan luput dari tekanan dan represi," tutur Asvi. Sementara itu, keterangan yang diperoleh dari para korban akan memiliki kelemahan lain, yakni masalah memori. "Pelaku sejarah itu umumnya berusia 70 tahun ke atas. Memori mereka sudah lemah, di samping bisa saja ada hal-hal yang belum mau diceritakan," ujar Asvi.
Kelemahan psikologis kisah-kisah para pelaku sejarah ini adalah apa yang biasa disebut "selective memory". Secara sadar atau tidak, mereka lupa atau bahkan tak bisa mengingat sebagian dari peristiwa yang dialami. Maka, tentu saja kisah-kisah ini akan menjadi sebuah kolase dari berbagai pelaku sejarah yang memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda-beda.
Buku-buku ini menjadi berharga karena semua sosok itu, baik sosok nyata dalam kisah biografis maupun tokoh fiktif dalam novel-novel, adalah sosok manusiawi para tapol dan napol yang digambarkan sebagai orang-orang yang juga memiliki rasa cinta dan rindu. Selain itu, seperti diutarakan Melani Budianta, karya semacam ini berharga karena, "Sejarah, bagaimanapun, merupakan suatu ajang pertarungan interpretasi, dan perlu diuji kebenarannya."
Maka, dengan suara-suara yang datang dari arah yang berbeda, sejarah tak akan lagi menjadi sekadar serangkaian dongeng yang disepakati.
Leila S.Chudori, Darmawan Sepriyossa, Setiyardi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini