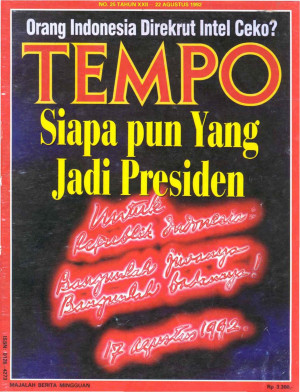SEBUAH pertunjukan, tapi juga sekaligus sebuah ritual: di bawah bulan yang penuh di atas Borobudur dan dilingkungi suasana candi yang khidmat, suatu gelombang gerak dalam beberapa komposisi berlangsung di halaman terbuka museum di taman candi tua yang luas itu. Hening, tapi hidup, dan pada umumnya menggetarkan, tapi juga meneduhkan. Penata tari Suprapto Suryodharmo, seorang budhis dari Surakarta, dan Katsura Kan, penari dari grup "Byakosha" dan lulusan sebuah universitas budhis di Kyoto dengan didukung 18 orang Indonesia dan 9 orang Jepang mementaskan "Prahara di Borobudur" (Tempest in Borobudur) Jumat pekan lalu. Judul itu mungkin merupakan judul yang agak kodian dan bisa menyesatkan, tetapi tidak mengapa. Pada akhirnya, karya tari itu bisa dicatat sebagai salah satu titik penting dalam untaian dramaturgi Indonesia yang sejak sekitar dua dasawarsa ini digerakkan oleh Sardono W. Kusumo. Dalam tujuh episode yang dirangkum dalam tiga bagian, Tempest berangkat dan berakhir dengan motif religius yang ditekankan secara cukup menonjol: pada awalnya adalah sebuah meditasi dan pada akhirnya adalah sebuah "pemberkatan", dengan kehadiran seorang bhiksu di bagian penutup. Tetapi yang kemudian menggerakkan adalah anasir yang lebih bersifat estetis: gerak, warna, kontras antara gelap dan cahaya, komposisi dan musik yang sepadan. Tempest dalam keluasan halaman museum Borobudur itu memanfaatkan ruang dengan efektif. Bagian pertama berlangsung di pekarangan bagian kiri, di sekitar patung sang Budha yang terletak di sebuah lingkaran berlantai batu tiga lapis. Dari dalam gelap, suara lirih seperti gumam dan bunyi mengantar adegan. Sepasang tubuh dalam pakaian putih salah satunya wanita dengan kesan kostum Jepang teronggok. Gumam pelanpelan berubah menjadi tembang, dan dari gelap di ujung sana pula muncul seorang wanita bergerak mendekat dalam ungkapan penari Jawa. Bersama dengan bunyi yang semakin meningkatkan suspens, dari ujung kiri dan kanan sepasang tubuh dalam warna putih total muncul, dalam gerak yang kian lama kian cepat. Komposisi terbentuk dengan rapi. Suasana tersusun dengan warna surealis yang sayup-sayup. Pada akhirnya klimaks adalah pertautan semua unsur gerak yang bergelora dalam suara gong yang hadir sebagai fokus. Bagian ini menunjukkan perpaduan unsur Indonesia (Jawa atau Sunda) dan Jepang yang seimbang. Namun perlu dicatat, unsur Indonesia di sini masih berada dalam taraf yang lebih fisik, dan akibatnya yang ada adalah perpaduan yang tanpa sepenuhnya pembauran. Mungkin itulah sebabnya Penata Tari Bagong Kussudiardjo menilai kedua unsur itu "masing-masing kelihatan tegas terpisah". Yang memberi daya yang kuat di sini tampaknya adalah para penari Katsura Kan: mereka punya energi yang terungkap dari semangat butoh, dengan batin yang peka dan kaya untuk improvisasi. Yang terbagus adalah bagian kedua. Pentas berpindah ke kolam segi empat yang berada di tengah halaman museum. Di tiap sisi, pelanpelan muncul empat ekspresi, mengimbangi sosok dalam tubuh putih yang menjadi pusat gerak di tengah-tengah kolam. Tak ada yang berlebih-lebihan di sini: hampir tiap penari adalah perwujudan sebuah eksplorasi ke ruang di luar dan terutama di dalam dirinya. Gamelan, suling Bali yang pilu, antara suasana angker sebuah pentas noh dan bunyi alam membentuk bukan saja sebuah tableaux, sebuah komposisi yang menggetarkan yang terangkum dalam sebuah pigura, tetapi juga sebuah ritual. Memang bisa timbul kesan bahwa pertunjukan sangat terikat pada sebuah desain: pengadegan diatur sejak mula berdasarkan tempat yang sudah direncanakan. Seorang penata panggung mengatakan bahwa Tempest seharusnya yang dilakukan ialah "mengeksplorasi tempat secara maksimal". Ia memuji bagian ketiga dari Tempest. Baginya, bagian ini, yang berpindah ke halaman belakang museum yang bergunduk dan bersemaksemak, merupakan bagian di mana semaksemak, pohon kelapa, atau tanah dengan permukaan yang berbeda tingginya sudah dipergunakan secara bebas dan optimal. Tetapi kuat kesan bahwa bagian ini yang merupakan klimaks merupakan bagian yang kurang terkontrol. Dengan perpindahan dari bagian satu ke bagian lain dan tempat yang satu ke tempat yang lain, yang berlangsung terampil dan cepat, Suprapto dan Katsura Kan berhasil membangun suasana dari sebuah ekspresi yang liris ke arah ekspresi yang lebih eksplosif. Dan mungkin untuk itu di bagian ini segala anasir dipergunakan: obor, layar putih, bayang-bayang, gerak yang sangat dinamis, komposisi yang sangat beragam, bunyi di pentas maupun tembang dan narasi di latar belakang dan akhirnya kehadiran hampir semua penari yang seakanakan ke sebuah titik kulminasi. Tapi tampaknya terlampau banyak yang ingin dikemukakan. Yang terkesan adalah keinginan membuat sebuah "spektakel", dan bukan sebuah proses menuju ke sebuah kearifan sesuatu yang terkait dengan motif religius pementasan ini. Tapi, toh ketika pertunjukan usai, di bawah bulan purnama dan suasana candi yang hening, puisi Suprapto dan Katsura Kan tetap terasa kuat sisanya. "Pertunjukan kami hanyalah merupakan terminal sementara dari suatu proses, dan proses itulah sasaran kami," kata Endo Suanda, musikus yang mendukung pementasan ini. Kesenian yang piawai memang seharusnya begitu. Dan Tempest, yang akan dibawa ke Jepang September nanti, kita harap akan terus menghidupkan proses itu kapan saja, di mana saja. R. Fajri dan Goenawan Mohamad (Borobudur)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini