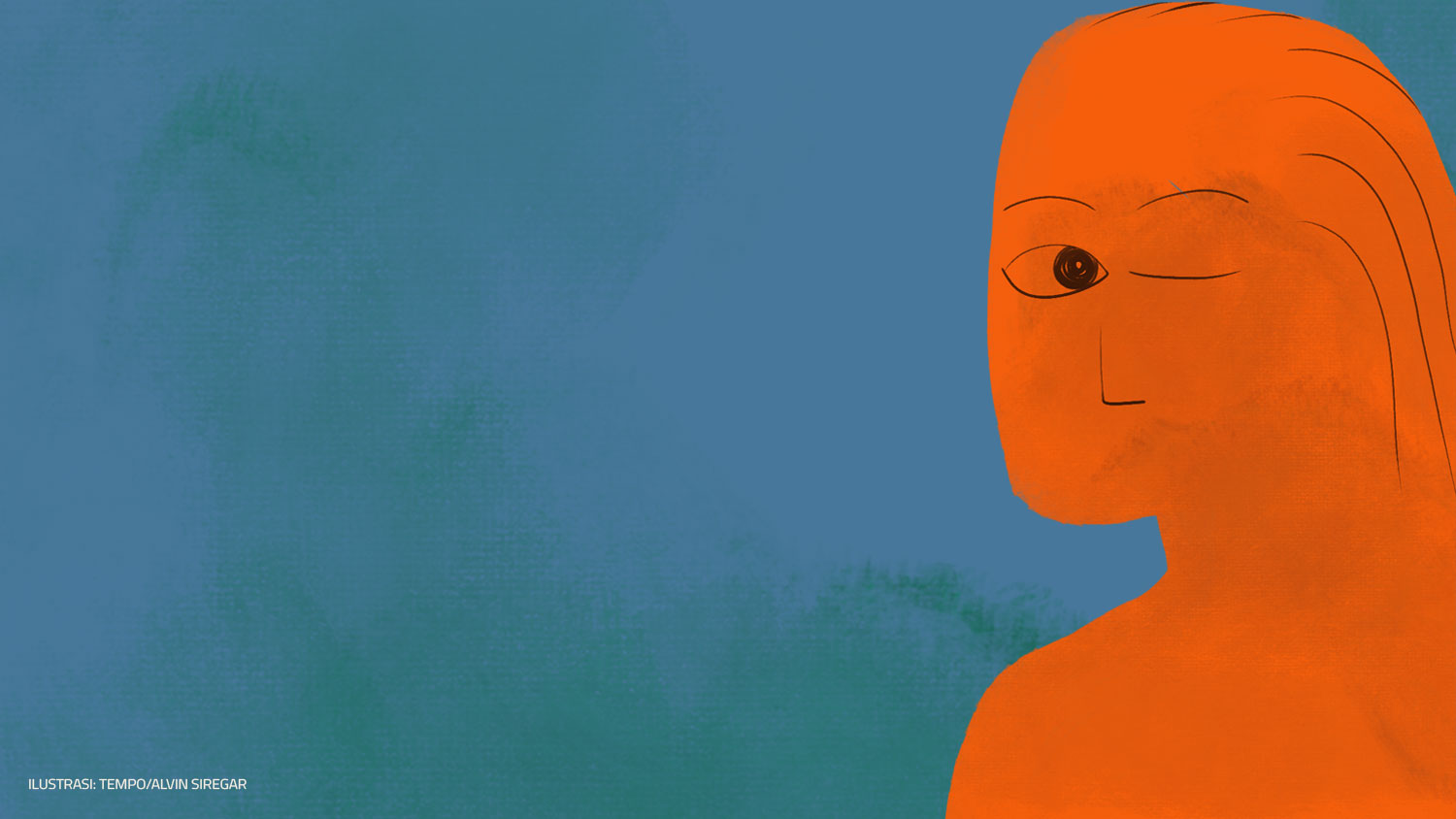Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TIGA penari berkostum merah darah mengacungkan parang ke langit dan mengoles-oleskannya ke sebagian tubuh. Bersorot mata tajam dan tanpa senyum sama sekali, seorang di antaranya memasukkan ujung senjata itu ke mulutnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo