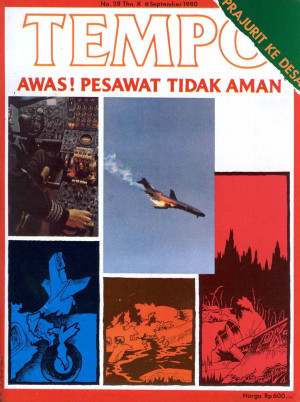AKAN makin tampak munculnya beberapa jenis 'teater tak resmi'.
Baik dari pembacaan cerpen maupun puisi. Model yang dibawakan
Putu Wijaya, pembawaan cerpen di TIM 28-29 Agustus, termasuk
yang secara sadar memanfaatkan akal-akalan (trick) untuk tetap
memikat. Dan ini khas akal-akalan panggung.
Putu membawakan delapan cerpen pendek -- tujuh buah diambilnya
dari buku kumpulannya berjudul Es, 17 cerpen singkat, yang
diterbitkannya sendiri khusus untuk keperluan acara. Ia berdiri
-- dan bergerak -- di depan mikrofon telanjang, sementara di
sebelah kanan-belakang dua orang berdiri di belakang mimbar dan
sebelah kirinya tiga orang duduk bersila -- menghadapi gendang
plus lonceng pukul. Kedua kelompok pengiring itu, para anggota
Teater Mandiri, membantu Putu dengan mengambil oper beberapa
dialog tertentu dari cerita yang sedang dikumandangkan -- dan
membangun suasana dengan pukulan gendang maupun bunyi ting ting
ting.
Tidak hanya satu model memang, akal-akalan untuk mengantarkan
cerpen atau puisi tertulis ke tengah forum. Leon Agusta, yang
pertengahan Agustus juga muncul di tempat yang sama, mengakrol
sajak-sajaknya dengan menghadirkan beberapa pengiring yang
menyanyikan kalimat-kalimat tertentu.
Betapa pun kedua-duanya, denga warna berbeda, telah memunculkan
satu jenis lain dari teater tak resmi tersebul -- yang selama
ini terutama populer pada Rendra dan kemudian Sutardji Calzoum
Bachri.
Baik Rendra maupun Sutardji, pada pembawaan sajak, adalah pemain
tunggal. Rendralah memang yang, barangkali tak disadari banyak
orang, pertama kali merubah sebuah pembacaan menjadi
pertunjukan. Tapi hanya "dengan sendirinya". Sebagai pemain
jempolan ia membawakan sajak-sajaknya yang dramatis -- dan
secara tak terasa orang masuk dalam daerah imaji. Bila toh puisi
yang dilontarkannya bukan dari jenis bertutur yang penuh adegan
(Khotbah, Nyanyian Angsa, Ricky dari Corona, misalnya), yang
menyebarkan ilusi seperti yang dilakukan panggung, setidaknya
orang menikmati suara dan tubuh-aktornya untuk sajak-sajaknya
yang liris.
Adapun Sutardji pertama kali memang mengundang kecurigaan orang,
acara sajaknya menjadi teater lantaran ia minum bir -- lalu
bergaya. Tapi kesadaran untuk bikin tontonan secara sengaja
memang dimulai dari dia. Mantra-mantranya yang "tanpa
ujung-pangkal", tiba-tiba memang menarik dilantunkan dalam udara
setengah mabuk, dengan tubuh sempoyongan dan tawa penonton yang
menyambut sebuah pribadi yang konyol. Kesengajaannya untuk
menjadi orang teater ditingkatkan lagi dengan digantungnya
sebuah kapak yang diayun-ayun -- pada pembacaan terakhir --
meski sebenarnya hanya punya hubungan dengan salah-satu sajaknya
yang memang berjudul Kapak. Ia mendapat keplok luar biasa.
Kimono Biru
Lalu puisi, dan kemudian cerpen, akhirnya memberi suguhan
visual. Itu tentu tak cocok dengan "pembaca murni" yang bagus
seperti Taufiq Ismail. Penyair ini merupakan contoh terbaik
untuk seorang "wakil sastra" --bukan teater -- yang hanya masuk
ke daerah teater pada seginya yang paling umum penyuaraan teks
yang menarik. Seperti bila Bung Karno berpidato, dahulu meski
warna keduanya tentu berkebalikan. Jelas ada penguasaan ritme,
di samping syarat vokal dan bekal penguasaan khalayak.
Tapi untuk kelompok cerpen, adalah Khairul Umam yang pertama
kali mengetengahkannya di TIM untuk satu acara khusus -- akhir
Januari 1978, dengan sebuah cerpen panjang Umar Kayam Kimono
Biru Buat Istri yang makan waktu lebih satu jam. Sutradara film
yang juga bekas anggota teater Rendra dan teater Arifin C. Noer
ini memang dikaruniai suara bariton yang empuk dan santai.
Dengan teknik vokal yang sempurna, peragaan tubuh sangat efisien
untuk beberapa bagian tertentu, ia memenuhi ruangan dengan udara
segar yang penuh tawa dan celetuk penonton, di samping klimaks
dan keheningan.
Masih tercatat sebagai pembaca cerpen terbagus, Mamang
(panggilannya) memang ditolong oleh pemilihannya pada karya Umar
Kayam yang memungkinkannya menyusun ritme dan mengembangkan
berbagai warna.
Tak demikian dengan pembacaan cerpen Putu Wijaya terakhir ini.
Cerpen Putu mutakhir merupakan bagian dari karya-karyanya yang
menggebrak. Dengan plot sederhana yang lebih memunculkan aksi
daripada perenungan, masing-masing karya itu sebuah letupan
hanya beberapa alinea yang tidak berpijak pada logika
sehari-hari -- dan rata-rata memberi satu kejutan di bagian
akhir.
Yang bergerak adalah semangat (dan bahasa) yang cergas. Dan
meski barangkali juga semuanya bisa dicoba dibawakan dengan
santai, Putu telah memilih bentuk tontonan yang atos, tegang dan
dalam tempo tinggi. Ia menghentak-hentakkan kaki, atau berjalan
ke belakang untuk memberi aksentuasi maupun membuka kesempatan
bagi para pembantunya. Ia memang bukan orang yang ingin
berkomunikasi langsung dan terbuka dengan penonton. Ia ingin
mewujudkan salah-satu bentuk teater dalam tingkat pertama --
yang diubah dalam sebuah acuan yang kempal, yang akhirnya toh
hanya sebuah jembatan ke arah satu dunia di seberang.
Penonton yang tidak begitu penuh, tidak tertawa dan hanya
sedikit bertepuk. Mereka juga tetap diam di tempat. Sebab yang
khas memang terasa.
Syu'bah Asa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini