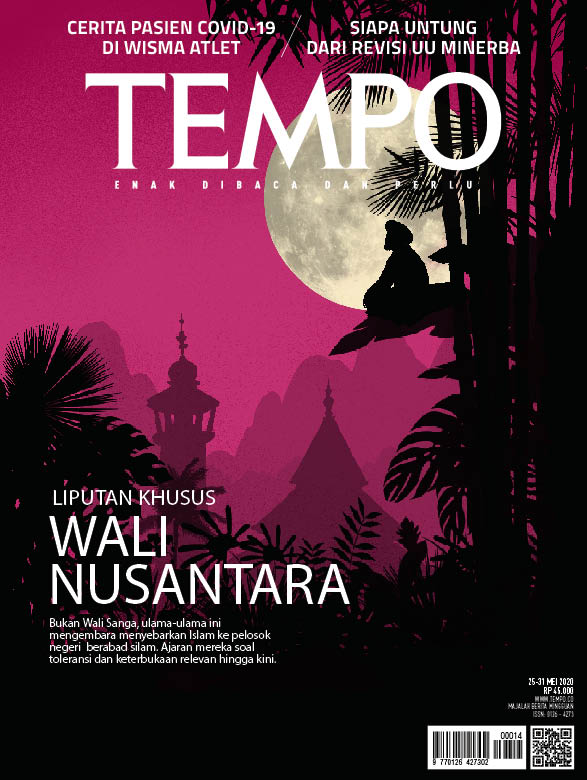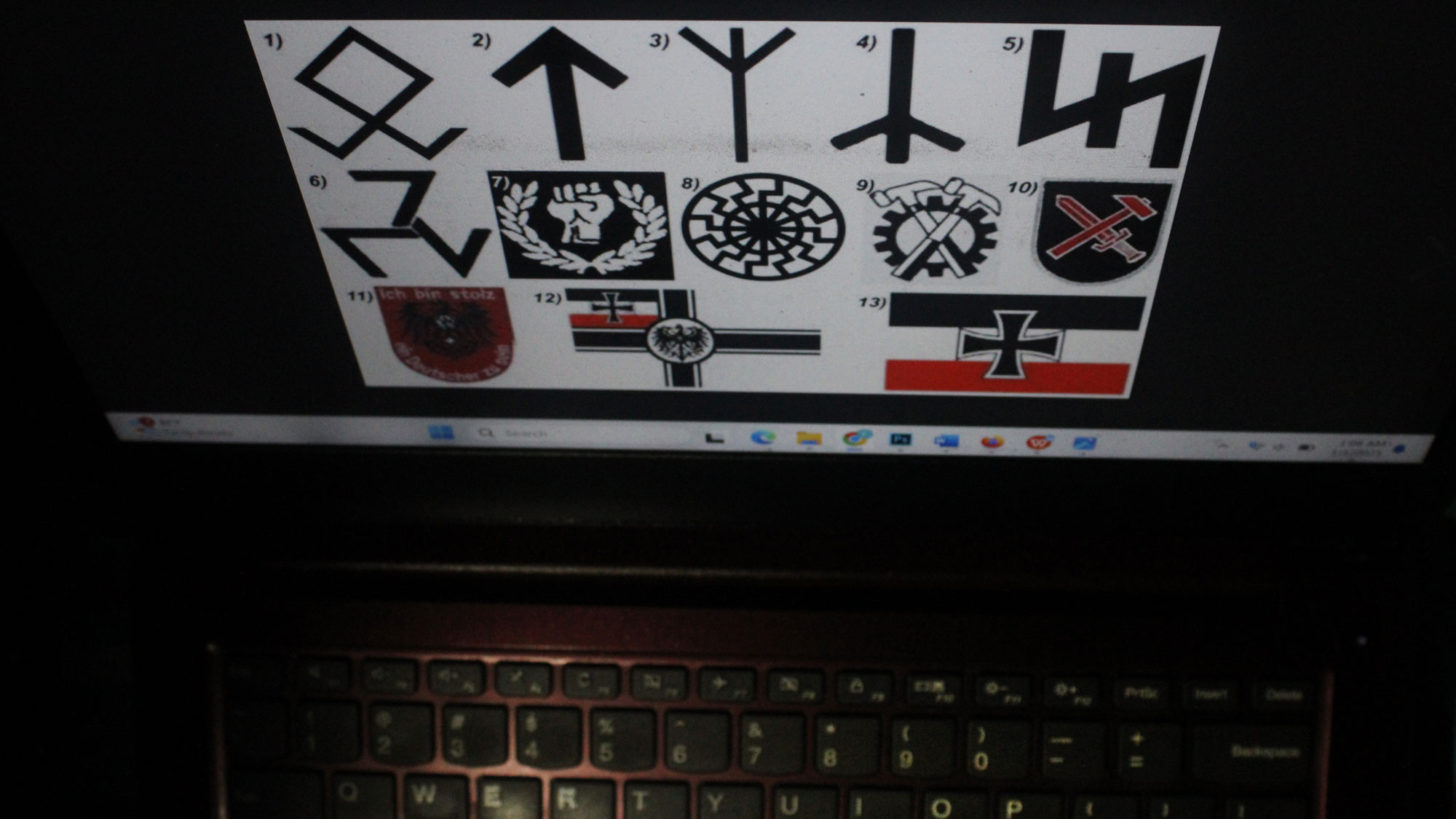Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah wali Nusantara dari Banjar, Kalimantan Selatan.
Syekh Arsyad banyak mengarang kitab fikih hingga tasawuf.
Sejumlah judul kitabnya menjadi nama masjid di Banjarmasin.
LIMA menara, empat kecil dan satu besar, mengelilingi masjid dua lantai berwarna cokelat dan emas seluas 5.250 meter persegi di sisi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Banjarmasin. Di depan bangunan utama membentang taman dengan kolam serta pancuran air. Di dalam kompleks masjid juga terdapat sejumlah bangunan, seperti kantor pengurus masjid, kantor Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin, dan area parkir.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo