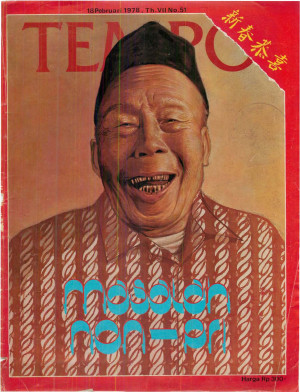GEDUNG itu dulu milik kraton Mangkunegaran. Semenjak
kemerdekaan, 1945, ia diambil-alih pemerintah kota Surakarta.
Dan jadilah ia kantor Palang Merah Indonesia cabang kota Sala -
sampai 1978. Setelah melalui sedikit protes dari PMI setempat,
Kamis pekan lalu gedung yang jadi tempat lahirnya Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) itu pun secara resmi jadi Monumen Pers
Nasional. Peresmiannya, tepat dilakukan pada hari ulangtahun PWI
yang ke 3 dihadiri oleh Presiden Soeharto dan Ny. Tien.
Hari itu mau tak mau jadi hari yang menarik. Para tokoh PWI,
dengan Ketua Pelaksana Harmoko dan Sekjen Sunardi D.M. yang
sangat aktif itu, tentu saja hadir. Juga para ketua cabang dari
daerah-daerah yang datang ke Surakarta juga untuk konterensi
kerja. Tak ketinggalan: hampir semua pemimpin redaksi penerbitan
di Jakarta, yang kebetulan juga pengurus PWI. Semuanya berharap
cemas menunggu apa yang akan diucapkan Presiden Soeharto hari
itu - yang merupakan pidato pertama tentang pers setelah 7 koran
dilarang terbit dan kemudian diizinkan kembali beredar.
Ternyata, agak tak terduga, tak ada suasana tegang. Kepala
Negara banyak tersenyum, bahkan tertawa. Menteri Penerangan a.i.
Sudharmono SH mendatangi dan bersalaman hangat dengan para
pemimpin koran, antara lain dengan B.M. Diah dari merdeka dan
Jakob Utama dari Kompas - keduanya yang terakhir boleh terbit
kembali. Ketika keesokan harinya Kompas terbit dengan cuplikan
pidato Presiden "Syukurlah Semuanya Telah Berlalu," judul beritz
utama itu boleh dibilang memang mencerminkan sedikit banyak
suasana hari Itu.
Ketidak-sengajaan
Presiden sendiri menyebut larangan terbit terhadap 7 koran
baru-baru ini sebagai suatu "musibah". Suasana dua minggu tanpa
7 koran itu bahkan disebutnya sebagai "memprihatinkan." Dengan
nada dasar memahami, pidato resmi itu juga menyebut bahwa peran
pers yang mengakibatkan tajamnya pertentangan politik di masa
lampau sebagian besar "terjadi karena ketidak-sengajaan."
Tapi tindakan pemerintah menjelang akhir Januari 1978 yang lalu
- ketika beberapa pemimpin redaksi tiba-tiba mendapat telepon
dari perwira Laksusda dan esoknya koran mereka terpaksa tak
muncul - oleh Presiden dinilai sebagai satu-satunya pilihan.
"Sungguh tidak menyenangkan bagi pemerintah untuk bertindak
demikian itu. Dan saya tahu, lebih-lebih tidak menyenangkan bagi
pers sendiri." Tapi, kata Presiden pula, ada kepentingan yang
lebih besar: yakni kepentingan "keselamatan bangsa dan negara."
Presiden menilai bahwa sampai menjelang akhir Januari yang baru
lalu, "kebebasan pers telah berkembang hampir-hampir tanpa
kendali." Ini berbahaya. Pengaruh pers sangat besar, dan
pengaruh ini "dapat bersifat baik" tapi "dapat juga sebaliknya?"
Maka Presiden pun berpesan agar pers nasional "hendaknya
baik-baik dalam mengembangkan kebe basan yang bertanggungjawab."
Yang menarik ialah rumusan Kepala Negara bahwa daJam kebebasan
pers terkandung dua arah: bebas memuat sesuatu berita dan bebas
tidak memuat sesuatu berita. Dengan kata lain kepada pers
diharapkan pengekangan atau "penyensoran" diri sendiri. Buang
jauhjauh "lamunan" bahwa kebebasan hanya untuk kebebasan, kata
Presiden. "Hal itu sungyuh terlalu mewah bagi kita, dan mungkin
akibat akibat bu ruknya bagi keselamatan bangsa dan negara harus
kita tebus dengan mahal."
Banyak para wartawan yang menilai pidato itu "baik sekali." Yang
jelas: melegakan. Semangatnya adalah rekonsiliasi. Di dalamnya
tak ada terkandung sesuatu yang bisa dinilai sebagai
"menakut-nakuti" - hanya mengingatkan kembali hal-hal yang
selama ini sudah ditandaskan. Tentu saja hal-hal itu juga
sebenarnya sudah dilakukan oleh pers Indonesia, walaupun bagi
pemerintah hasilnya ternyata dianggap masih kurang. Terbukti
dengan terjadinya tindakan 20 Januari.
Sehabis pidato Presiden dan upacara pembukaan oleh Ny. Tien
Soeharto, para tamu pun berduyun masuk ke ruang dalam Monumen.
Di bagian depan terpasang contoh-contoh penerbitan pers
Indonesia sejak zaman lalu hingga kini - satu pameran menarik
yang disusun oleh penulis sejarah pers terkemuka, Subagio l.N.
dengan bantuan D.S. Moelyanto. Dan apa yang diucapkan Kepala
Negara tentang sejarah pers nasional sebagai pers pejuang nampak
di situ.
Tentu saja terlihat juga di sana betapa terasa jarak antara
"pers pejuang" di masa perang kemerdekaan dengan pers dewasa
ini. "Sekarang pers kita sebenarnya bukan pers perjuangan," kata
seorang wartawan lama yang berdiri di depan panel pameran,
"melainkan pers sebagai bisnis."
Di dalam pers perjuangan, ada nampak semangat memihak yang
nyaris mirip pamflet, tapi berani dan dengan semangat bebas,
walaupun menghadapi ancaman. Di dalam pers sebagai bisnis ada
semangat "profesionalisme" dengan menganggap berita sebagai
suatu "komoditi." Jua pertimbangan yang lebih besar ke arah
laba, kesejahteraan karyawan dan keselamatan usaha.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini