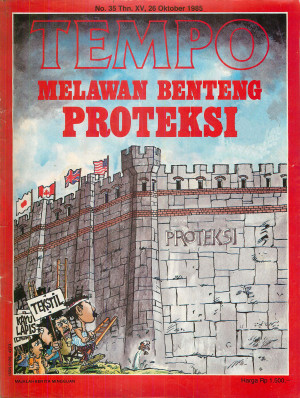HARAPAN PT Dan Liris, Solo, memperoleh dolar pupus sudah. Minggu malam lalu, ketika rombongan ketiga dari 8.000 buruhnya baru mulai masuk pukul 22.00, kebakaran mendadak saja menggigit pabrik tekstil milik grup Batik Keris itu. Api dengan cepat melahap sebagian besar dari 1.400 unit mesin tenunnya yang baru dipakai September 1983 lalu. Rusak berat. Akibat kerusakan itu cukup hebat: sekitar 90% kegiatan produksi Dan Liris, yang setiap bulan menghasilkan tekstil 5,5 juta yard dan 200 ribu pakaian jadi, jadi macet. Karenanya, peluang Dan Liris bisa menangguk dolar lebih banyak dengan restrukturisasi industrinya itu ikut menjadi asap. Padahal, perusahaan yang berkembang pesat dan dikenal efisien. itu termasuk salah satu swasta yang dijagokan. Dukungan pemerintah terhadap Dan Liris memang tidak setengah-setengah. Sejumlah bank pemerintah bergabung jadi satu membentuk konsorsium untuk menyalurkan kredit Rp 46,5 milyar bagi pendirian pabrik tekstil terpadu itu. Di Jawa Tengah bukan hanya Dan Liris yang melakukan perluasan investasi. Ada empat pabrik tekstil lain di sana, yang juga mencoba ikut menangkap kesempatan di tahun 1983 itu. Sayang, usaha restrukturisasi yang dilakukan berdasarkan keadaan pasar tahun 1981 itu (ketika permintaan tekstil dan pakaian jadi masih kencang) kurang membawa hasil. Di tahun 1983 itu, waktu lima pabrik yang menelan investasi Rp 192,7 milyar tadi diresmikan, pasar tekstil dan produk tekstil lokal mendadak kusut. Dalam dua tahun berikutnya itu rupanya terjadi kristalisasi di antara mereka. Hanya Dan Liris, yang terus-menerus membangun jaringan pemasarannya ke pasar lokal dan luar negeri, yang akhirnya bisa bertahan. Restrukturisasi - kata itu mulai didengungkan sejak tiga tahun lalu -dianggap perlu dilakukan terhadap industri tekstil dan pakaian jadi jika ingin memenuhi keinginan konsumen. Sebab, menurut penelitian T. Akip, Direktur Utama Unico (United Industrial Consultant), mutu dan lebar tekstil Indonesia secara umum banyak yang belum memenuhi keinginan pembeli di luar negeri. Ia menyebut lebar kain di sini yang 36, 42, 44, dan 58 inci, berbeda jauh dengan standar kain yang dibutuhkan pasar ekspor. "Soal label, pengepakan, dan kontrol kualitas kita juga lemah," katanya. Hasil penelitian itu diperkuat oleh pernyataan S. Sinaga, Direktur PT Unilon Textile Industries. Mesin-mesin perusahaan patungan itu, yang dibeli antara 1970 dan 1974, dirasakannya sudah terlalu tua dan ketinggalan teknologinya. Dengan mesin yang sekarang, Unilon hanya mempunyai kemampuan maksimum menghasilkan kain dengan lebar 122-125 cm, atau hanya sekitar 50 inci. "Mana mungkin kami bisa bikin sprei?" katanya. "Tapi, kalau mau restrukturisasi banyak dana dibutuhkan." Jadi, memang benar, kelemahan itu sendiri sesungguhnya sudah diketahui para pengusaha tekstil. Dalam soal teknis, mereka juga dianggap masih kurang. Menurut Akip lagi, industri tekstil Indonesia masih lemah dalam pencelupan benang, dyeing and finishing, pemintalan rotor, combing dan conewinding (knotless), serta pertenunan shuttleless dengan lebar 70 inci sampai 110 inci. Pendeknya, kata dia, teknologi industri tekstil di sini sudah ketinggalan zaman. Ia lalu menunjuk contoh kasus ekspor kain grey (bahan dasar) ke Jepang, yang kemudian direekspor ke Amerika. Para pengusaha, di pihak lain, juga menyadari, jika kekurangan teknis itu tidak diperbaiki, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap permintaan pembeli. Perusahaan dengan skala ekonomi besar, seperti Century Textile Industries, tcntu, tak ingin ketinggalan sepur. Secara berangsur perusahaan patungan yang sudah go public itu, mulai November 1984, mengganti sejumlah mesinnya. Baru US$ 3 juta dana perusahaan disalurkan untuk mengganti 10% mesin-mesinnya, lalu berhenti. "Macet karena tidak ada dananya," ujar sebuah sumber di situ. Centex memang sedang mengalami ujian cukup berat. Penjualan bersihnya, tahun lalu, naik cukup bagus - terutama dari pasar lokal. Penjualannya di luar negeri dalam rupiah ternyata malah turun sekalipun dalam volume, perusahaan bisa menggenjot penjualan dari 9 juta yard (1983) jadi 10 juta yard (1984) tetoron cotton. Tapi, naiknya penjualan itu, ternyata, banyak termakan oleh makin naiknya harga pokok penjualan. Akibatnya, perusahaan malah rugi. Kerugian cukup besar, lebih dari Rp 802 juta, terjadi akibat rugi kurs sesudah rupiah didevaluasi 1983 - yang dibebankan pada tahun buku kemudian. Tentu saja, tidak semua perusahaan berskala besar bernasib seperti itu. Sebuah grup perusahaan tekstil terkemuka yang berkantor di Pintu Kecil sudah memutuskan untuk menambah investasi Rp 20 milyar bagi kelangsungan usahanya. Mesin tenun yang akan dipasangnya berjumlah 500 unit, dan di jagokan pemegang sahamnya akan mampu menghasilkan tekstil halus. "Dengan mesin tenun air jet itu, produksi tekstil akan berjalan lebih cepat dan halus. Hasilnya juga akan sesuai dengan permintaan pasar ekspor," katanya. Di luar dugaan, sebagai konsekuensi ditekennya perjanjian GATT dalam code on subsidies, pemerintah diharuskan mencabut SE mulai April 1986. Pencabutan fasilitas itu diduga akan mengurangi daya saing produknya. Dan kesulitan kelihatan makin bertambah dengan akan disahkannya RUU Jenkins. Karena itu, pengusaha terkemuka ini terpaksa menangguhkan pemasangan 300 mesin. Yang sudah telanjur, 200 unit, dibiarkan berjalan. Penundaan harus dilakukan, "Untuk melihat kemungkinan munculnya kesempatan baru," katanya. Antisipasi pengusaha ini menghadapi perkembangan mendadak di dalam dan luar negeri itu tampaknya dilakukan cukup hati-hati, karena ekspornya ke Amerika tahun lalu cukup besar: US$ 20 juta. Pasar ekspornya ke Eropa Barat dan Timur Tengah sebesar US$ 40 juta mungkin juga akan terganggu karena Masyarakat Eropa menunjukkan gejala akan makin proteksionistis juga. "Kalau rancangan Jenkins itu diterima, kapasitas terpakai pabrik kami akan berkurang 20%," katanya. Dalam situasi yang serba kurang menguntungkan itu, iklim berusaha bagi mereka juga terasa kurang nyaman. Daya saing tekstil dan pakaian jadi Indonesia berkurang karena dikurung biaya tinggi. Penyebab biaya tinggi itu 80% berasal dari komponen produksi seperti listrik, transportasi, terminal perhubungan laut, darat, udara, serta bank yang dikuasai pemerintah. Sisanya berasal dari ketidakefisienan pengusaha swasta sendiri. Fakta itu dikemukakan Ketua API Frans Seda, Maret lalu, sebelum Inpres No. 4 tahun 1985 keluar. Kini mungkin ada sedikit perubahan. Bagi pengusaha yang maju, tingginya komponen produksi itu bukan menjadi salah satu alasan untuk menghentikan sama sekali usaha restrukturisasi. Sekitar tiga tahun lalu, ketika soal restrukturisasi mulai didengungkan, dana yang dibutuhkan untuk memenuhi tindakan itu adalah US$ 2 milyar lebih. Mahal memang. Belakangan usaha itu kabarnya akan dikombinasikan dengan menyediakan semacam fasilitas export estate di Cakung. Industri yang berusaha di sini, selain menjual hasilnya ke luar negeri, juga diperbolehkan melegonya di pasar lokal. Nah, jangan ketinggalan lagi. E.H. & Max Wangkar Laporan Ahmed S. & Suhardjo Hs. (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini