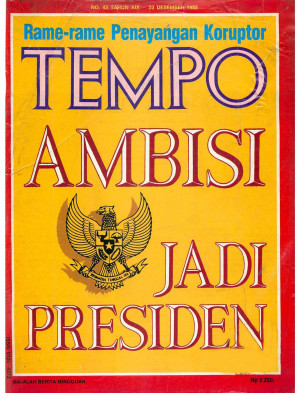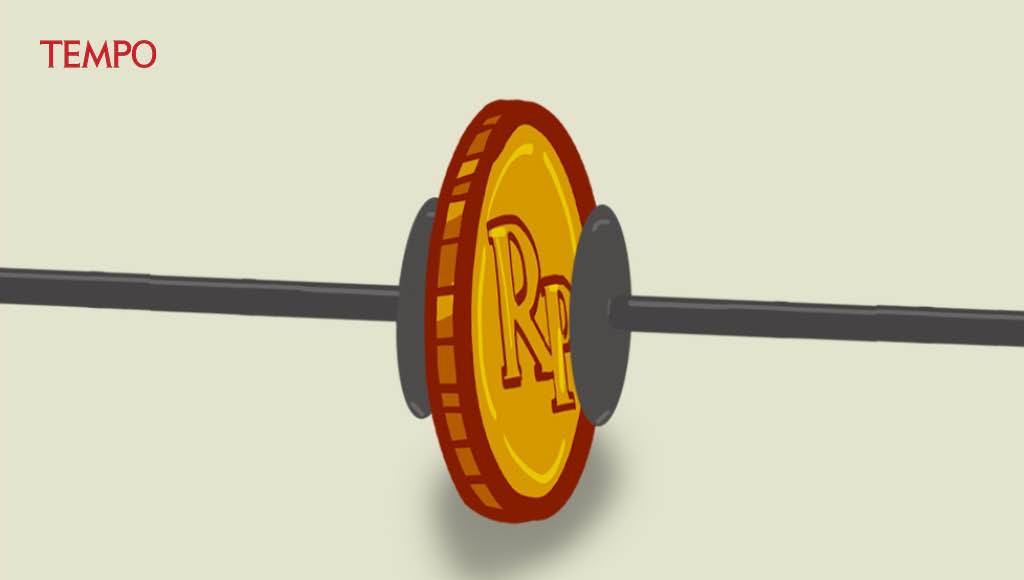BERBICARA tentang ekspor nonmigas, komoditi rotan bukanlah primadona, kendati oleh Presiden Soeharto dinyatakan punya nilai strategis. Mungkin karena itu pula, pemerintah dan pengusaha industri hilir, yang menggunakan rotan sebagai bahan baku, begitu repot mengurus komoditi yang satu ini. Pada November 1986, misalnya, ekspor rotan mentah dilarang. Serentak dengan itu, ekspor rotan setengah jadi (RSJ) dibolehkan hanya sampai Januari 1989. Tapi, dengan alasan untuk mengejar nilai tambah, pemerintah mempercepat larangan -- lewat SK yang diturunkan oleh Menteri Perdagangan -- terhadap ekspor RSJ, menjadi 1 Juli 1988. Rupanya, protes berlompatan dari segala arah. Tidak hanya dari pengusaha RSJ, juga dari luar negeri -- tepatnya dari Amerika Serikat dan negara-negara MEE. Protes yang dilancarkan melalui surat kabar di Hong Kong, Singapura, dan Jakarta itu bukanlah gertak sambal semata. Mereka mengancam, seandainya Indonesia tidak meninjau kembali larangannya, persoalan ini akan dibawa ke dalam pertemuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Bahkan ancaman itu terus bergaung hingga pekan lalu. Lantas apa tanggapan pemerintah? "Kami akan meneliti dulu masalahnya," kata Paian Nainggolan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Sementara pemerintah masih berpikir-pikir, sebuah gagasan muncul dari "raja kayu plus rotan" Bob Hasan. Menurut dia, Indonesia sebenarnya siap menghapus larangan ekspor rotan mentah serta setengah jadi. Tepatnya, Indonesia siap menghapus proteksi non-tarif semacam itu. Tapi, "Harus dikompensasi dengan menaikkan pajak ekspor yang tinggi," ujarnya. Tidak jelas, berapa kenaikan pajak yang dimaksud Bob. Tapi, dari nada kalimatnya, Bob menginginkan pajak ekspor (PE) setinggi mungkin. Dalam realisasinya kelak, rotan mentah ataupun RSJ tetap saja tak bisa diekspor, karena tak mungkin bersaing dengan PE yang tinggi. Nasibnya akan persis seperti kayu olahan dan kayu gergajian, yang dikenai PE 250-1.000 dolar per meter kubik. "Wah, itu sih sama saja dengan pelarangan ekspor," komentar Sjahrir, ekonom yang aktif mengamati sektor industri. Menurut dia, kalau rotan mendapat perlakuan yang sama dengan kayu olahan, maka Indonesia kembali melanggar aturan main yang telah digariskan GATT. Sebab, Konperensi GATT di Uruguay telah dengan tegas melarang negara mana pun untuk menambah proteksinya. Selain itu, pada dasarnya, Sjahrir tidak setuju kalau ekspor rotan mentah dan RSJ dilarang. Alasannya, industri hilir yang membuat mebel-mebel ekspor itu belum tentu mampu mengumpulkan devisa sebanyak yang telah dikumpulkan oleh rotan mentah dan RSJ. Soalnya, menurut Sjahrir, mebel memiliki pasar yang elastis, sehingga akan sangat mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan desain. "Yang saya heran, kenapa kita berani mempertaruhkan sesuatu yang sudah pasti didapat, untuk sesuatu yang masih samar-samar," ujarnya. Apalagi yang dikorbankan bukan hanya devisa, tapi juga lapangan kerja. Larangan ekspor rotan dan kayu gergajian ini telah mengakibatkan 2.000-an perusahaan kayu, plus 200-an pengusaha otan, gulung tikar. Belum lagi ribuan pengumpul rotan yang kehilangan mata pencaharian. Industri hilir juga terkena sabetannya. Kini ratusan perusahaan lampit terancam bangkrut. Pasalnya, sekitar 750 ribu meter kubik lampit menumpuk di gudang, karena harganya dua bulan belakangan ini anjlok, tinggal 6 dolar per meter kubik. Dan coba dilongok tumpukan rotan mentah. Orang-orang di sektor hulu ini -- dalam kondisi yang begitu nelongso -- terpaksa mengerem penjualan rotan, karena harga yang diajukan produsen mebel kelewat rendah. Rotan mentah jenis irit misalnya, dihargai Rp 300 per kilo. Gawatnya lagi, industri hilir yang dilindungi itu kini hanya menawar Rp 120. Nah, mau apa lagi? Budi Kusumah dan Yopie Hidayat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini