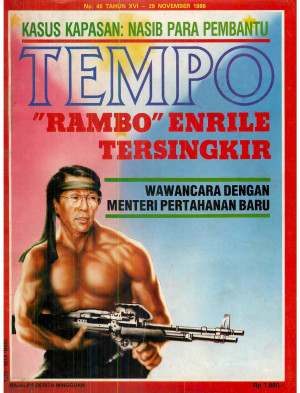BILA ada koran murah, pembaca senang. Tapi rupanya ada yang sewot, yakni sesama surat kabar. Bulan ini, harian terkemuka Kompas menaikkan sedikit harga langganannya, dari Rp 5.250 menjadi Rp 6.300. Banyak sesama koran memprotes. Yaitu koran daerah. Karena harga baru yang ditetapkan koran besar itu terlalu rendah, tidak sesuai dengan ketentuan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS). Seharusnya, kata sebuah sumber di SPS, surat kabar yang terbit 5 kali 12 halaman, dua kali 16 halaman, plus sekali sisipan dalam seminggu, harga langganan minimal Rp 7.500 per bulan. Angka itu diperoleh berdasarkan kenaikan harga kertas, ongkos cetak, dan biaya-biaya eksploitasi lainnya. Ketentuan harga tersebut diumumkan oleh SPS pada 22 Oktober lalu, "Tapi itu belum merupakan keputusan, baru berupa anjuran," ujar sumber tadi. Harga yang pasti baru akan diputuskan Februari mendatang. Jadi, untuk saat ini, setiap penerbitan masih bebas menentukan harga jualnya sendiri, "Seperti Kompas, ia bebas menentukan harga langganannya, karena itu hak dia," ujar Sunardi D.M., Ketua Umum SPS Pusat. Sementara pihak Kompas rupanya keberatan menjawab soal kebijaksanaan harga itu. Tentu, tidak semua penerbit surat kabar sepakat dengan pendapat itu, terutama para penerbit di daerah yang merasa pelanggan korannya bakal lari ke Kompas. Kata Budi Santoso, Ketua SPS Jawa Tengah, "Harga yang ditetapkan Kompas tidak rasional, dan amat merugikan koran daerah." Sebab, dengan harga yang tidak jauh berbeda, konsumen akan cenderung memilih Kompas sebagai "koran pusat". Pemimpin perusahaan harian Masa Kini, Yogyakarta, Mohamad Socheh, sangat menyesalkan kenaikan harga Kompas yang rendah. "Sudah koran daerah, kami ini 'kan koran kecil yang mengandalkan pendapatan dan pembaca, mana mampu bersaing dengan koran besar yang banyak memperoleh iklan," ujarnya. Koran-koran daerah sendiri mencoba menyesuaikan harga berdasar perbandingan oplah. Harga langganan Masa Kini, misalnya, masih Rp 3.750, sementara saingannya, Kedaulatan Rakyat, menetapkan harga Rp 5 ribu. Itu wajar, memang, sebab di Yogya harian Kedaulatan Rakyat merupakan koran terbesar dengan oplah 30 ribu eksemplar. Sedangkan Masa Kini hanya beroplah 5 ribu. Keluhan yang sama muncul juga dari SPS Jawa Barat. "Bagi koran yang banyak iklannya, dibagikan secara gratis pun saya kira tidak akan rugi," kata Krishna Harahap, Ketua SPS-nya. Repotnya, di Jawa Barat ada gejala perang harga antarpenerbitan daerah sendiri. Rupanya, usaha SPS Ja-Bar mengajak para anggotanya menetapkan harga bersama gagal. "Ada dua penerbitan yang tidak menyetujui," kata Krishna. Di Sumatera Utara, imbauan SPS Pusat ditanggapi dengan tertib. Harga langganan koran di provinsi ini seragam, Rp 7.500 per bulan. Soalnya, SPS Sum-Ut menetapkan sanksi bagi penerbit yang melanggar kesepakatan. Selain peringatan keras, dan tidak akan diberi Surat Pembagian Jatah Kertas, SPS Sum-Ut juga mengancam akan mencabut rekomendasi yang diberikan kepada penerbit. Tapi, itu tidak berarti lalu koran-koran Medan -- Waspada, Sinar Indonesia Baru Analisa -- misalnya, setuju dengan persaingan bebas. "Untuk melindungi koran daerah, SPS Sum-Ut harus memberikan tanggapan ke pusat," ujar Kepala Bagian Pemasaran harian Waspada. Harian ini, memang, merasa tersaingi Kompas. Tidak hanya dalam soal harga, tapi juga karena Kompas mampu sampai di tangan pembaca dalam waktu yang bersamaan. Tapi, sebenarnya, belum ada data bahwa oplah koran daerah lalu turun akibat harga koran pusat di bawah imbauan. Bagaimanapun, surat kabar daerah yang baik tentu menyajikan berita daerah dengan lebih komplet -- berita yang tak bisa dibaca di koran Jakarta. Siapa yang harus dilindungi, sebenarnya? Para konsumen justru diuntungkan bila ada koran yang bisa dijual dengan harga lebih murah. Di zaman informasi diperlukan berbagai pihak, koran murah membantu meluaskan penyebaran berita -- termasuk berbagai penemuan dunia ilmu, pembaharuan kurikulum, pemberantasan wereng, sampai sore ini mau nonton di bioskop mana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini