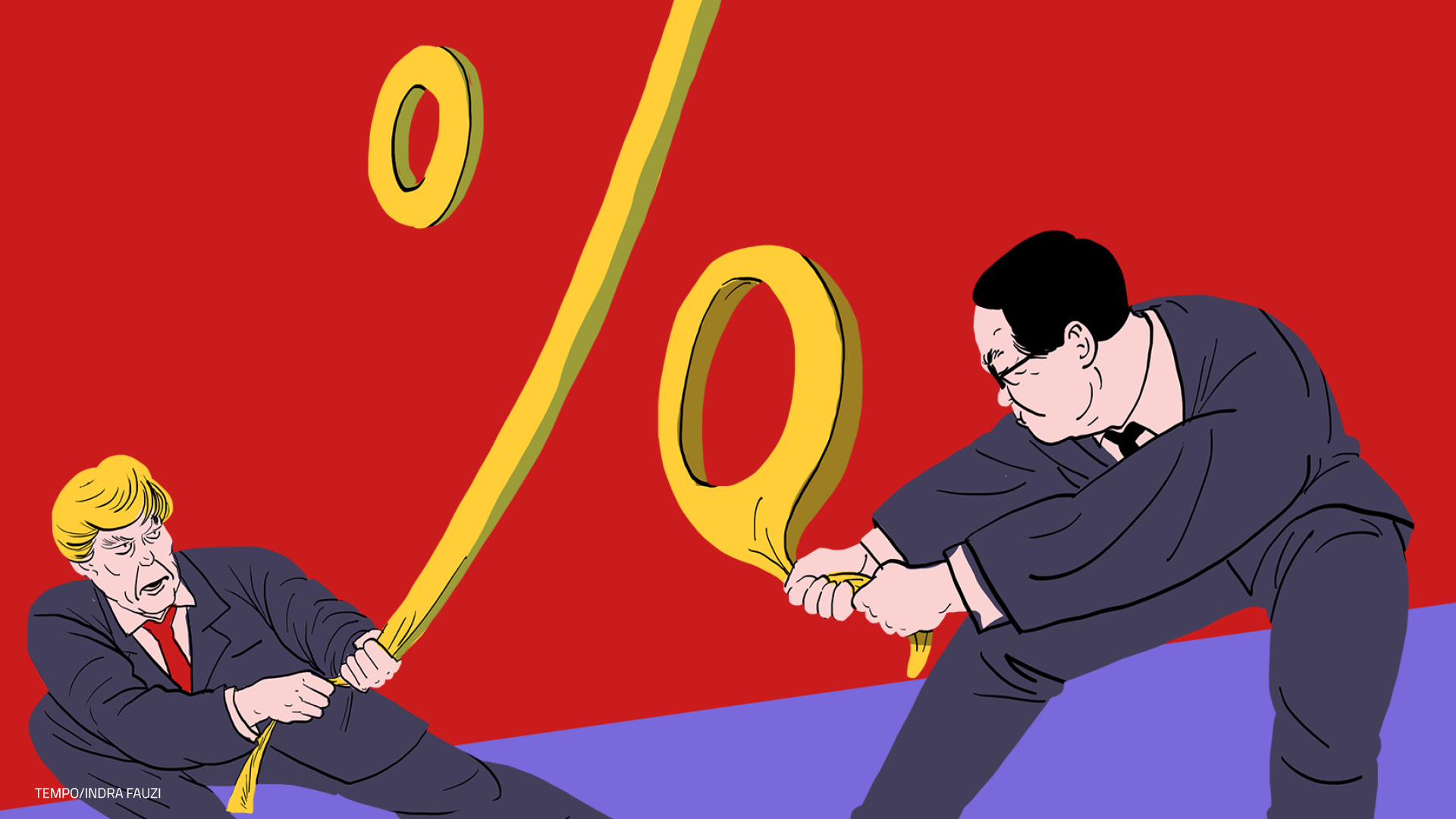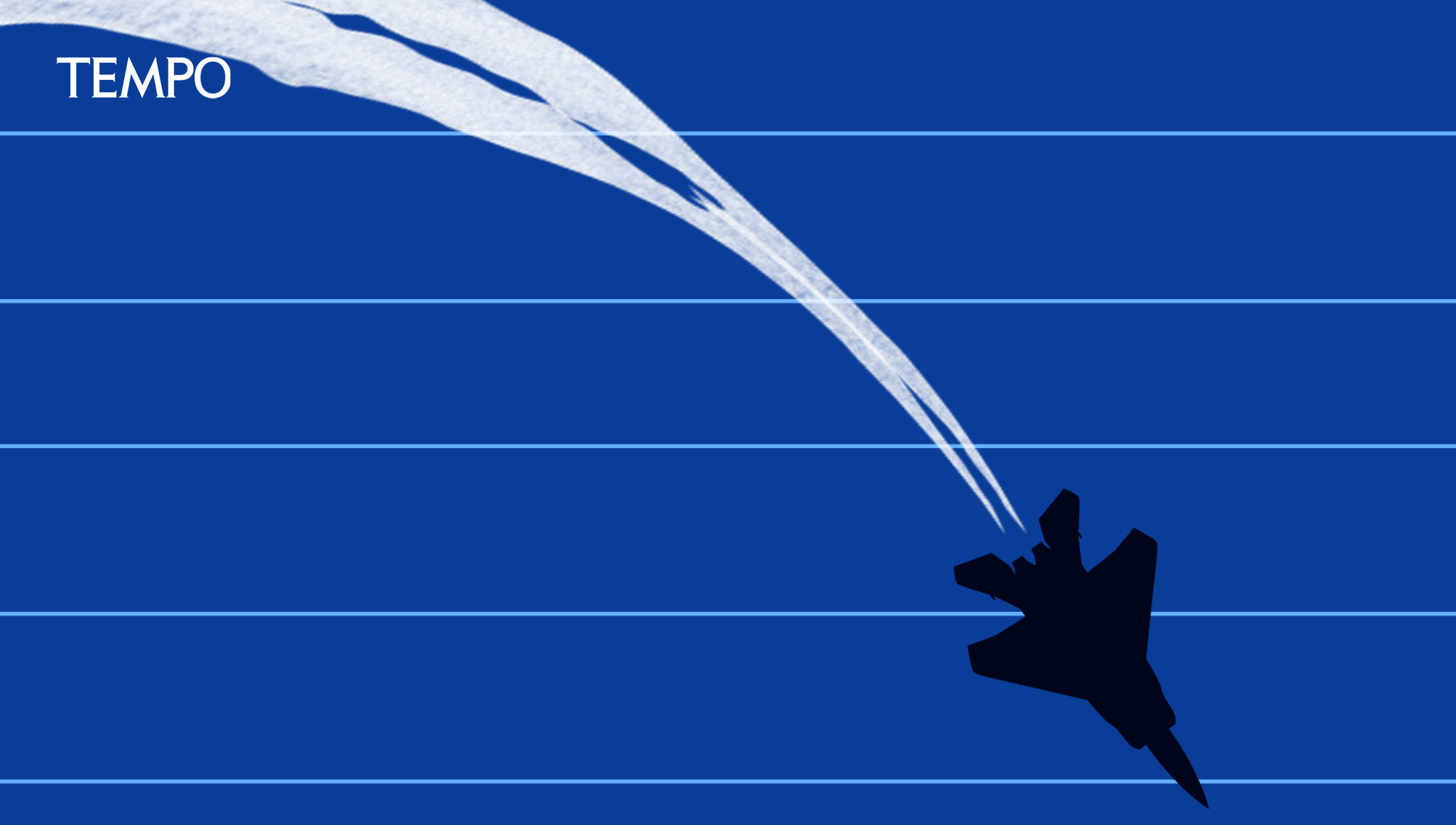Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PENYEJUK udara gedung MPR/DPR seakan tak sanggup mendinginkan Susilo Bambang Yudhoyono. Butiran keringat tampak membasahi dahi sang Presiden. Dua kali ia harus menyeka peluh dan meneguk air putih.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo