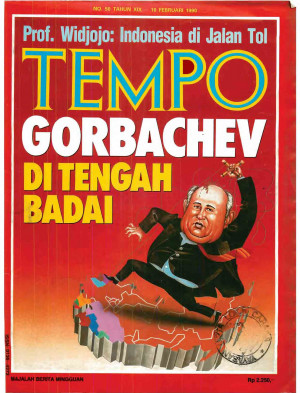Jor-joran di Dalam dan di Luar Lapangan Pers berolahraga di tengah umbul-umbul sponsor dan perhatian besar beberapa pengusaha kakap. Konglomerasi? PPN kertas koran diberlakukan 1 April 1990. KALAU ada acara yang paling semarak yang pernah dibikin wartawan Indonesia, maka itulah Porwanas IV -- Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Pesta olahraga dua tahunan itu diramaikan sekitar 1.000 wartawan -- termasuk yang mengaku wartawan -- berlangsung meriah dan wah di Surabaya. Dalam upacara pembukaan Jumat pekan silam sekitar 30.000 penonton berjejal di stadion Gelora 10 Nopember. Mereka mengelu-elukan 26 kontingen PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), yang mewakili provinsinya masing-masing. Hanya PWI Tim-Tim yang tidak tampil. Dalam suasana gegap-gempita, ke-26 kontingen dan penonton disuguhi atraksi menawan. Ada drum-band dari pabrik rokok Sampoerna, tarian balet Marlupi, pencak silat, tarian masal, dan masih banyak lagi. Belum lagi duet artis penyanyi Neno Warisman dan Franky Sahilatua, yang petang itu bagaikan mengguncang isi stadion. Menteri Penerangan Harmoko pun terbawa larut. "Luar biasa, dan saya tak menyangka bisa semeriah begini. Acaranya begitu padat dan tak membosankan," begitu puji Menteri. Pesta olahraga itu memang jadi ajang yang prestisius buat wartawan. Mereka bertanding dalam 7 cabang olahraga (tenis, tenis meja, bulu tangkis, bilyar, bridge, catur, dan lari 5 km) untuk memperebutkan Piala Presiden -- bagi kontingen yang terbanyak mengumpulkan medali emas. Demi prestise itulah, ada sejumlah daerah secara terang-terangan menyertakan wakilnya yang bukan "wartawan". Bahkan ada yang diwakili oleh atlet peserta PON XII 1989 lalu di Jakarta. Memang ada yang memprotes, namun tanpa hasil. Ironis. Semaraknya Porwanas IV di Surabaya itu juga tak lepas dari peran sponsor yang melimpah. Jangan kaget, Porwanas, yang berakhir Selasa pekan ini, dihitung-hitung menghabiskan Rp 1 milyar. Memang mewah. Bahkan tampaknya dunia pers melebihi dunia film, yang sejak dulu serba gemerlap. Dan ciri mewah itu melekat pada sebuah dunia yang kini bergerak dari era "pers perjuangan" ke era industri. Lebih dari itu, sejumlah pemilik modal mulai melirik pers yang katakanlah sedang boom. Data yang dikumpulkan oleh PT Surindo Utama -- sebuah lembaga penelitian di Jakarta -- menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu, biaya belanja iklan yang diraup surat kabar mencapai Rp 187,3 milyar. Ini belum termasuk majalah, yang mendapat Rp 62,8 milyar. Menurut Mohammad Chudori, Managing Editor harian Jakarta Post, meningkatnya jumlah pembaca menjadi faktor terpenting yang membuat pemasangan iklan melimpah. "Oplah total seluruh media di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini melaju pesat," katanya. Dari 5 juta eksemplar (1984), tahun lalu menggembung menjadi 10,5 juta eksemplar. Dan harian Kompas adalah sukses yang gemilang. Tahun lalu, penerbitnya, PT Kompas Media Nusantara, terpilih sebagai pembayar pajak peringkat 28 -- di antara 150 pembayar pajak terbesar di negeri ini. Bandingkan dengan PT Bogasari Flour Mills (peringkat 108) atau Philips Ralin Electronics (peringkat 138). Koran daerah juga tak mau ketinggalan. Harian Jawa Pos di Surabaya, pada 1988, meraih laba Rp 4 milyar, dan tahun lalu ditaksir Rp 5 milyar. Seiring dengan itu, Menteri Harmoko menunjuk jumlah pemakaian kertas, yang empat tahun silam masih sekitar 90.000 ton, kini sudah 140.000 ton. Adalah wajar saja kalau beberapa pengusaha seperti Fadel Muhamad, Aburizal Bakrie, Soetrisno Bachir, dan Edward Soeryadjaya mau ikut pula berpacu di sektor informasi ini. "Saya kira, mereka tertarik karena bisnis pers itu bisa dilihat sebagai komoditi politik. Setidaknya bisa digunakan sebagai sarana public relations buat perusahaan mereka," ujar Aristides Katoppo, Direktur PT Sinar Kasih, yang pernah menerbitkan koran Sinar Harapan. Namun, data PT Surindo Utama itu juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 surat kabar -- dari 263 penerbitan -- yang menikmati derasnya iklan. "Nasib pers di Indonesia memang masih belum merata," ujar Rosihan Anwar, wartawan tiga zaman. Celakanya, pers yang lemah (terutama modalnya) pasti tak mampu bersaing. "Akhirnya mereka ketinggalan dan keleleran," tambah Rosihan. Karena itu, ada yang risau begitu melihat sejumlah pengusaha kakap terjun dalam dunia pers. "Kalau sudah untung di bisnis lain, kenapa harus masuk ke bisnis pers. Bisnis pers tak semata-mata mengejar keuntungan, karena terselip misi lain berupa sumber informasi untuk kepentingan orang banyak. Jika konglomerat masuk dunia pers, terbuka peluang mereka menggunakan media untuk melindungi kepentingan bisnisnya," demikian komentar Mochtar Lubis, tokoh wartawan kawakan. Benarkah ada indikasi akan terjadinya konglomerasi dalam bisnis pers? "Saya pikir tak akan terjadi itu," tutur Harmoko menegaskan. Ia menunjuk UU Pokok Pers, yang sudah mengatur sejumlah pembatasan yang mengekang bakal terjadinya monopoli dalam dunia pers. Sementara itu, ada yang malah tidak takut pada konglomerat. "Hadirnya konglomerat justru bisa membantu koran daerah," kata M. Dahlan Kadir, Pemimpin Redaksi harian Tegas, di Ujungpandang. Mungkin karena itu pula, sejumlah koran lokal kini mulai berkembang. Pengusaha seperti Surya Paloh sudah lebih dulu menyambutnya dengan membeking sekitar 10 koran daerah -- antara lain koran Yogya Post, Lampung Post, atau Mimbar Umum (Medan). Dalam situasi jor-joran itu, pemerintah dengan tenang mengumumkan pemberlakuan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) buat kertas koran. Mulai 1 April 1990, harga kertas koran dikenai PPN 10%. Ini berarti harga kertas, yang semula Rp 1.050 per kg, akan menjadi Rp 1.115 per kg. Tampaknya, harga koran dan majalah juga akan terbawa naik. "Tapi saya kira masyarakat masih mampu membelinya," kata Harmoko. Ahmed K. Soeriawidjaja, Wahyu Muryadi, Bandelan Amarudin (Surabaya), Agung Firmansyah, dan Sri Pudyastuti R. (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini