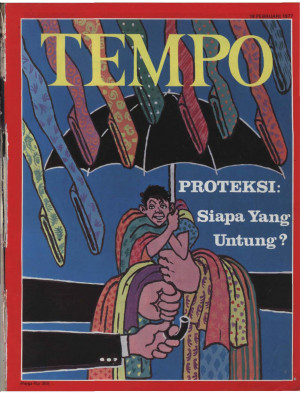KELUHAN dari dunia tekstil santer kembali. Kali ini yang
berteriak bertenaga raksasa, sehingga suaranya pun jadi lebih
lantang. Nadanya juga menuntut lebih keras: stop impor!
Kejadiannya berlangsung begitu cepat. Lima tahun lalu, pabrik
tekstil yang lazim disebut penghasil tekstil lokal walaupun
parau masih mampu berteriak: minta dilindungi kelangsungan
usahanya. Di kota tradisionil tekstil, seperti di Pekalongan
atau Majalaya, pengusaha sudah kehabisan nafas. Tekstil impor
membanjir. Benang susah dikejar. Semua itu dianggap menjadi batu
perintang di jalan usaha mereka.
Tapi saingan produksi lokal itu bertambah. Tak usah jauh-jauh
didatangkan: pabrik-pabrik baru muncul dilengkapi dengan
peraturan dan fasilitas penanaman modal asing (PMA). Segera
mereka bertongkrongan, umumnya di Jawa Barat. Lalu apa kabar
yang dulu disebut pengusaha lokal? Masih ada, cuma sudah tak
berkutik. Untuk berteriak minta proteksi, leher rasanya sudah
tercekik. Tapi ternyata kini suara minta proteksi datang dari
perusahaan-perusahaan yang mirip raksasa modern itu yang praktis
telah menggantikan si pengusaha lokal.
Dan tahun 1977 ini - karena teriakan itu - agaknya akan menjadi
tahun yang membawa keberuntungan bagi yang berteriak. Baik yang
3/4 modal asing, « asing, maupun yang berkapital domestik. Lewat
Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang diberlakukan tepat
pada hari pertama tahun ini penanam modal bidang industri itu
meletakkan seluruh harapan baiknya pada pemerintah.
Menteri Perindustrian, berturut-turut, akan menetapkan barang
apa saja yang sudah mampu dibikin dan mencukupi kebutuhan
konsumsi dalam negeri. Dengan ketetapan itu, barang yang
dimaksud harus berada di pasaran dalam negeri secara nyaman,
tanpa diganggu barang dagangan asing. Itu gampang. Sebab,
sebagai penandatangan SKB, Menteri Keuangan akan mencoba
menghambat masuknya komoditi impor.
Untuk ini, Menteri Ali Wardhana, diminta membangun tanggul yang
tinggi: bea masuk & pajak, serta berbagai syarat impor lain yang
berat, dikenakan. Tujuannya: melemahkan daya saing terhadap
produksi dalam negeri. Andaikata ada importir yang nekad, berani
membayar berbagai syarat dengan mahal dengan mengandalkan merek
luar negeri, dengan harapan mungkin masih ada peminat berani
bayar mahal - itu tak usah membuat produsen dalam negeri kecil
hati.
Giliran pertama yang memperoleh pengayoman, 1 Januari itu juga,
sederet daftar nama 33 jenis tekstil. Antara lain: kain sarung
serta tenunan sutera kain sarung atau tekstil katun bermotif
batik tiruan (atau cap), karpet, tikar wol, tekstil dari bulu
binatang dan sebagainya.
Berikutnya pengusaha besi beton dan karung goni tarik nafas lega
(lihat: Goni Dan Beton: Proteksi Langgeng?).
Juga 3 pabrik serat polyester sejak 28 Januari lalu mendapat
perlindungan. Belum lagi selesai pemerintah menunjuk siapa saja
yang dapat giliran dilindungl, mereka sudah mengancam hendak
meniru ulah pabrik besi beton: mogok produksi. Suaranya yang
keras itu dibawakan oleh Musa, Ketua Textile Club, di kuping
para anggota Komisi VI DPR.
Dari kesibukan ketiga departemen menyusun daftar barang yang
harus diproteksi, Menteri Radius Prawiro buru-buru menyatakan:
Bentuk proteksi yang seperti sekarang ini tidak dimaksudkan
sebagai 'stop impor total'. Alasan Radius: "Setiap larangan
impor itu selalu mengandung unsur negatif, yang justru lebih
banyak ketimbang positifnya".
Namun bagi Musa cs, apapun komentar Radius atas kebijaksanaan
pemerintah mengenai pembinaan industri dalam negeri, sudah lebih
dari cukup menggembirakan. Selesai sidang bersama Komisi VI DPR,
dalam kesempatan dengar pendapat umum bulan lalu, Musa berkata
kepada TEMPO "Pada hakekatnya proteksi yang seperti sekarang
ini, sudah berarti stop impor".
Betul juga. Bea masuk akan "disesuaikan". Artinya, dinaikkan
tarifnya. Syarat impor jadi berat: bea harus dibayar kontan di
muka, harus ada uang jaminan 100%, dan semuanya harus dibayar
dari kantong importir sendiri. Total jenderal, itu semua memang
sudah cukup mengganjel pintu impor.
Namun, seperti tujuan SKB sendiri yang kelihatan cuma ingin
membina industri, lagi-lagi hanya kaum industriawanlah yang
paling bisa menikmati. Mereka itu adalah 485 pabrik tekstil
besar. (420 PMDN dan 65 proyek PMA).
"Apakah peraturan baru itu dapat menjamin kelancaran distribusi
di dalam negeri secara terus-menerus, dengan harga yang baik dan
kwalitas yang memenuhi kebutuhan konsumen?", begitulah
pertanyaan Zahri Achmad, ketu organisasi importir (GINSI).
Sebab diketahui, industri tekstil umumnya hanya berpusat di Jawa
saja. Dan mereka memang tak pernah berkewajiban menjanmin
kelancaran distribusinya. Seperti kata Musa kepada para anggota
DPR: "Soal distribusi bukan urusan kami. Ada aparat negara yang
mengaturnya. Di jalur distribusi itu ada manipulator dan
spekulator. Itu bukan tugas kami untuk menertibkannya".
Nah. Ini mengingatkan orang pada urusan pabrik baterai.
Seahdainya ada larangan impor total -- dan semua penyelundupan
batu baterai diberantas mungkin penduduk Indonesia di Kepulauan
Riau, sebelah utara Sulawesi atau Irian Jaya, tak bisa ikut
mendengarkan siaran RRI. Sebab distribusi batu baterai dalam
negeri ternyata belum sampai terjangkau konsumen di daerah
terpencil. Bagaimana kalau mereka harus pula tak berbaju?
Belum lagi soal harga. Begitu SKB terbit, pasar tekstil yang
sebenarnya masih menyimpan stok impor lama, sudah mulai tegang.
Kain shantung eks RRC, yang biasanya dijual di Pasar Tanah Abang
dengan Rp 8.000 per pis, sekarang pengusaha batik harus
membayarnya Rp 8.600. Shantung buatan Muriatex Kudus, yang
tadinya cuma Rp 6.200 per pis, naik dari Rp 7.500 hingga Rp
8.000. Begitu juga kain paris impor. Sebelum Januari per yard Rp
330, sekarang Rp 370. Sementara kain paris lokal, yang
kwalitasnya menjemukan, dari harga Rp 200 per yard terus
meningkat mendekati harga impor. Juga harga tekstil lain handuk,
kain kasur, taplak dan sebagainya - untuk masa awal SKB sudah
meningkat harganya 10% sampai 40%.
Konsumen, ambil contoh pengusaha batik, tentu kalang kabut.
Kenaikan harga blacu lokal (sampai 56%) tentu tak mungkin
diikuti harga jual batik jadi. Kenaikan kain batik paling cuma
10%. "Apalagi suasana pasar sepi begini", kata seorang
pengusaha di Tanah Abang. Orang dagang bukannya tak punya jalan
keluar untuk mengatasi keadaan. Caranya, apa boleh buat:
terpaksa potongan panjang kain dikorting dan mutu obat batikpun
dipilih yang 'memadai'.
Kekecewaan berikutnya, karena harga dan mutu yang tak menentu,
tentu akan dirasakan oleh konsumen yang lebih luas. Itu suasana
awal SKB. Bagaimana keadaannya jika stok lama mulai menipis dan
habis? "Ah, tenang saja", kata seorang pemilik toko tekstil.
Sambil mengerling ke arah teman dagangnya ia berkata: "Ada saja
nanti jalannya. . . misalnya penyelundupan yang biasa".
Namun begitu Musa, Ketua TC dari Daya Manunggal Group yang
bekerjasama dengan Kuraray dari Jepang, mencoba menyangkal
kenyataan ini. Di muka para anggota DPR ia menegaskan: "Kami
akan mempertaruhkan nama baik dan merek kami untuk menjaga
mutu". Perkara harga? Itu soal lain. Dari permulaan ia sudah
mengeluh: "Harga jual selalu lebih rendah dari kalkulasi".
Dari banyak industriawan yang mengharap proteksi, memang
pengusaha tekstillah yang paling keras suaranya. Ini pernah
mengundang rombongan penting ke 'lapangan'. Satu rombongan
Fraksi Karya Pembangunan, dipimpin Ketua Komisi VI Jakob Tobing,
pertengahan Nopember lalu meninjau pabrik tekstil di Cibinong
dan Ciawi. Hasilnya tentu saja: menampung sebakul keluhan. PT
Daralon, di Cibinong, suatu usaha orang sini dengan Amerika,
mengaku telah mulai menutup pintu pabriknya sejak beberapa bulan
lalu. Di Ciawi, PT Ratna mengeluh kreditnya dari Bank Bumi Daya
sebanyak Rp 2 milyar macet. Dua pabrik ini punya alasan yang
sama: tak bisa menjual barangnya. Padahal, seperti dikemukakan
PT Ratna, mereka telah berusaha menjualnya 40O di bawah harga
semestinya.
Untuk mendukung dan melengkapi keluhan, dari Majalaya dikabarkan
ada 4.100 alat tenun masinal yang dicutikan oleh pemiliknya,
karena tak menguntungkan. Kabar yang sama datang juga dari
Bandung. Berbagai keluhan pengusaha tekstil, rupanya didengar
baik oleh - tak kurang dari - Wakil Kepala Bakin, Letjen Ali
Murtopo. Pejabat ini bersemangat ikut menyerukan perlunya
proteksi industri tekstil untuk waktu tertentu. Tapi ada juga
fikiran lain. Pengusaha industri sebenarnya sudah cukup
diperlengkapi untuk terjun ke pasar dengan leluasa. Mereka
memperoleh fasilitas liburan pajak selama 5 tahun, dibebaskan
dari bea mengimpor peralatan pabrik dan bahan baku, mendapat
kemurahan kredit dari bank pemerintah, juga boleh mendatangkan
tenaga ahli asing. Maka timbul pertanyaan: "Kalau yang
memperoleh- fasilitas itu mengeluhkan kalkulasi yang tinggi
dibandingkan harga jualnya, bagaimana dengar yang kecil?" kata
TD Pardede, tokoh Pardedetex dari Medan. Padahal, "pabrik
mereka, mestinya, memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat
untung". Itulah sebabnya Pardede secara terus terang minta
kepada Musa cs, agar memberikan bahan tertulis mengenai struktur
komponen harga.
Anggota DPR yang lain, malah memberondong Musa dengan berbagai
pertanyaan: Siapa konsultan pabrik polyester itu? Bagaimana
feasibility-study yang dibuat sebelum pabrik berdiri? Apakah ada
faktor lain di luar yang diperhittmgkan oleh konsultan? Tak
semua pertanyaan dijawab para tamu DPR yang dipimpin Musa itu.
Namun di luar acara ini ada pengusaha lain yang menjawab. Ia
adalah H.A. Djunaid, pengusaha asal Pekalongan, bekas Ketua Umum
GKBI. Ia menjawab sebagai Presiden Direktur PT Primatexo
lndonesia - suatu usaha patungan GKBI dengan modal Jepang dan
bank di Amerika. "Dalam rencana pendirian pabrik semua tentu
sudah diperhitungkan. Juga faktor yang menghambat, misalnya
adanya tekstil impor di pasaran baik yang legal maupun ilegl".
Jadi? "Bagaimanapun, karena faktor itu sudah diperhitungkan,
pabrik berjalan seperti yang diinginkan: untung!"
Faktor penting yang menguntungkan, kata Djunaid, "pemerintah
sudah cukup memberi fasilitas, tinggal kewajiban kita untuk
mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima, yaitu jangan
mengeluh!" Pabriknya di uesa Sambong, dekat Pekalongan, menurut
Djunaid, "untungnya sudah lebih dari memuaskan". Sebagai bukti,
disodorkannya rencana perluasan pabriknya dua kali lipat dari
yang diresmikan oleh Presiden Soeharto 5 tahun silam.
Perluasan itu mungkin, kata Djunaid karena segala fasilitas yang
telah diterima dari pemerintah seharusnya menghasilkan pabrik
yang baik. Misalnya soal permesinan yang didatangkan ke mari
tanpa pungutan impor. Seandainya memang betul yang didatangkan
ke mari itu mesin baru - sebab kenyataannya banyak juga yang
mendatangkan mesin lama - tentu peralatan itu akan
menguntungkan. Kerjanya sangat efisien. Suasana di Primatexo
misalnya, yang kedengaran cuma gemuruhnya suara mesin, tanpa
kelihatan kesibukan operatornya. Sebab, di sana, untuk
menjalankan 40 mesin sekaligus cuma perlu seorang karyawan.
Menurut Presdir Primatexo ini, "efisiensi pabrik baru harus di
atas 95%".
Dengan keadaan pabrik yang demikian itu, "sebenarnya kalau mau
bisa saja saya turunkan harga jual produksi prima yang ada -
jika memang ada persaingan keras". Tapi persaingan itu dianggap
belum begitu rupa hingga perlu menurunkan harga yang fantastis.
Di pasar mori, prima milik Primatexo memang tidak sendirian. Di
samping prima hasil pabrik sebawahan kalibernya, juga ada dari
"textex" besar lainnya. "Tapi, seperti saya katakan", kata
Djunaid, yang juga menjabat sebagai salah seorang Ketua TC,
"bagaimanapun persaingan dengan tekstil impor sekalipun -
dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, saya yakin
seharusnya masih menguntungkan".
Lalu bagaimana dengan keluhan Musa cs? "Saya sebagai salah
seorang Ketua TC belum pernah diajak berunding oleh Musa,
mengenai semua keluhan dan tuntutannya itu". Tapi, "kalau toh
saya diajak bicara, saya juga tidak akan ikut-ikutan menuntut
ini dan itu". Sebab, kata haji yang masih memimpin beberapa
pabrik tekstil milik koperasi batik PPI di Pekalongan ini, "saya
meragukan keluh kesah itu". Bagaimanapun tipisnya kentungan
dari bisnis tekstil, "asal menghitung kalkulasinya menurut
ukuran yang wajar, tak perlu mengeluh"
Menurut berbagai orang dari kalangan tekstil, sebenarnya masih
ada beberapa pos dari komponen harga yang bisa ditekan -- agar
kalkulasi tidak tampak begitu meninggi. Seorang akuntan, yang
banyak memegang buku perusahaan tekstil di Jakarta, membenarkan
hal itu.
Salah satu yang mungkin bisa ditekan, misalnya, biaya yang
terlampau banyak untuk membayar gaji pegawai asing yang
didatangkan kemari sebagai ahli. "Entah mereka itu ahli betul
atau cuma siluman", kata akuntan yang enggan disebut namanya
ini. "Yang terang mereka makan gaji beberapa kali lipat lebih
besar dari karyawan pribumi".
Rata-rata mereka bergaji 2000 dolar sebulan, ditambah jumlah
yang sama untuk apa yang disebut "tunjangan jauh dari keluarga".
Belum lagi biaya untuk perumahan, mobil dan fasilitas yang
'layak'. Pendapat akuntan itu dibenarkan oleh Djunaid. Itulah
sebabnya ia berusaha keras, berkelahi dengan partner asingnya,
agar kalkulasi dari pos ini ditekan terus. Di pabriknya dulu
pernah ada 40 tenaga ahli bangsa Jepang di antara 700 karyawan
anak negeri. Tapi sekarang jumlah orang asing yang ada di sana
tinggal lagi 6 orang (3 di antaranya direktur) di antara hampir
1.200 karyawan. Maunya sih orang asing mau tinggal lama-lama di
sini, tapi buat apa kita mesti menyenangkan orang asing - yang
gaji di negaranya sendiri mungkin jauh dari yang mereka terima
di sini?" ujar Djunaid.
Di samping itu, ada soal kalkulasi yang berhubungan dengan
mesin. Dalam keadaan yang wajar saja sebenarnya mesin yang
sekarang ada - yang dimaksud: milik perusahaan raksasa yang baru
berdiri -- banyak menguntungkan. Namun pada kebanyakan pabrik,
terutama yang PMA, cenderung untuk menilai terlalu tinggi harga
mesin dalam membebankan penyusutannya ke dalam kalkulasi.
Mending kalau mesinnya betul-betul baru gres. Kadang-kadang,
seperti yang diketahui akuntan di atas, "saya pernah melihat
sendiri ada 1.200 unit mesin bekas eks-Belgia, yang dalam
pembukuannya dihitung sebagai mesin baru". Dalam kasus semacam
ini, begitu menurut akuntan tadi, "orang asing jelas bermaksud
bukannya hendak menjual tekstil sebagai barang jadi, tapi lebih
kentara mau jual kapital: mesin, bahan baku dan sekalian
mengekspor tenaga mereka ke luar negeri".
Itu sama sekali bukan mustahil. Seperti kata Djunaid: "Sebelum
pabrik berdiri dan beroperasi, mereka sebenarnya sudah banyak
menarik keuntungan dari harga penjualan mesinnya saja". Itulah
sebabnya fihak Indonesia dalam PT Primatexo Indonesia, dalam hal
ini CKBI yang punya saham cuma sekitar 26%, tidak tertarik untuk
sedikit demi sedikit berusaha memiliki perusahaan sampai 100%.
"Sepintas lalu, memang, idealnya perusahaan itu lama-lama harus
jadi milik kita". Tapi agaknya Djunaid memang hendak berfikir
lain. "Pengalaman sudah cukup memberi contoh: begitu kita
selesai bersusah payah menguasai modal, ternyata yang kita
terima cuma suatu pabrik atau hotel yang sudah usang". Dan yang
usang itu, walaupun masih ada harganya, tentu sudah mulai
kehabisan potensi ekonomisnya.
Apalagi bicara pabrik tekstil selalu berarti harus bicara soal
teknologi baru. Begitu pabrik mulai 100% jadi milik orang sini,
orang asing juga sudah mulai siap dengan mesin model mutakhir
yang hendak ditanamkan. Jadi, "buat apa kita harus membeli mesin
tua yang sudah ada di Indonesia?" kata Djunaid. "Lebih baik
keuntungan yang kita peroleh, dari saham sekian persen itu, kita
gunakan untuk memperluas pabrik secara lebih modern atau membeli
saja mesin baru". Maksudnya, lebih jelas, "lebih baik kita hanya
mempunyai andil 25% di empat pabrik baru atau di sebuah pabrik
yang tems diperluas secara modern, dari pada memiliki sepenuhnya
pabrik tua".
Memburu-buru modal asing agar cepat diambil oper, "tak lebih
cuma memburu-buru agar orang. asing itu mengambil keuntungan di
sini". Dan untuk itu hanya ada satu jalan saja: menaikkan
setinggi mungkin angka kalkulasi. Dan untuk menjual hasil
produksinya, "giliran pemerintah lagi - yang sudah cukup memberi
fasilitas itu - dituntut harus melindungi harga jual mereka yang
payah bersaing", ujar Djunaid keras. "Dan fihak kita, yang harus
memperjuangkan proteksi, berteriaknya lebih keras dari Jepang
atau Hongkongnya sendiri!"
Namun teriakan industriawan tekstil belakangan ini menurut
seorang pejabat Departemen Perdagangan, sebenarnya tak begitu
sulit untuk diuji ke mana arahnya. Asal "pemerintah lebih dulu
mempunyai norma untuk menilai: apakah kalkulasi yang disodorkan
pengusaha itu wajar", kata pejabat itu. Misalnya, salah satu
cara: pemerintah lebih dulu dapat membuat kalkulasi untuk blacu
atau tekstil dari serat sintetis. Dengan mengukur melalui
kalkulasi yang dibuat pemerintah, yang mesti betul karena
pemerintah mempunyai alat penghitung yang baik -- tentu bisa
dicek, sejauh mana kewajaran kalkulasi yang dibuat produsen.
Itu soal kalkulasi. Namun kalkulasi saja memang tak menjamin
kelancaran pemasaran. Di bursa tekstil Pasar Klewer -- Sala,
orang tidak lagi menanyakan pembukuan pabrik untuk menawar
barang. Dan itu membuat suasana pasar penuh dengan pelototan
mata -- saling mengincar.
Itulah kenyataannya: di bursa orang gampang mencari baran, mori
prima atau blacu, yang harganya di bawah harga buku pabrik.
Sebabnya tak sulit diketahui. "Kami selalu membutuhkan uang
kontan untuk sesuatu keperluan", kata Bakri, fabrikan Patex
Batari, terus terang. Kalau tidak Bakri, juga ada orang lain --
bukan dari kalangan pabrik yang tiba-tiba menjual barang dengan
banting harga Padahal blacu itu dibelinya juga dari Bakri dengan
harga pabrik. Rugi? Ternyata, setelah dihitung-hitung, tidak.
Sebab ia membeli dari pabriknya Bakri, tidak kontan, dengan
tempo pembayaran 2 atau 3 bulan. Untuk memperoleh uang kontan,
orang ini bersedia menjualnya rugi. Kalau dihitung, untuk
memperoleh uang kontan sekian dari bank dengan jangka waktu 2
atau 3 bulan, bunganya masih lebih tinggi daripada bersikap
merugi di bursa tekstil.
Kali ini tekstil menjadi alat spekulasi. Ini mungkin, "karena
bursa sudah jenuh", kata Bakri. Baik di Sala maupun di
Pekalongan, bursa tekstil memang sudah kelebihan suplai.
Berbagai merek pabrik dalam negeri hingga eks penyelundupan ada
di sana. "Untuk mengatasi kejenuhan ini, harus ada proteksi
lagi", ujar Haji Mirza, dari PPIP Pekalongan.
Proteksi lagi? "Tapi ini lebih sehat dari stop impor", kata
Mirza sembari tertawa. Begini: "Pemerintah harus menentukan atau
mengatur, jenis-jenis tekstil yang harus diproduksi setiap
pabrik". Jangan seperti sekarang: "Ramai prima, bikin prima,
laku blacu, bikin blacu musim sintetis, semua main sintetis".
Mirza usul, "agar hanya pabrik milik koperasi batik saja yang
diizinkan membuat mori". Tentu jika produksinya memang cukup
tersedia memenuhi kebutuhan konsumen. "Untuk membuat palekat,
biarlah pengusaha kecil yang mengerjakannya dengan alat tenun
bukan mesinnya (ATBM), agar yang kecil juga bisa bernafas",
katanya.
Tapi pabrik yang berkaliber raksasa seperti PMA dan PMDN tentu
lebih cerdik memilih barang apa yang laku dijual. Bukankah
mereka lebih mampu membuat banyak variasi: dari mulai kain pel,
serbet, kelambu hingga bahan tetoron? Dalam hal itu, pemerintah
perlu memberikan batas. Untuk membagi-bagi kerja. Yang artinya:
rejeki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini