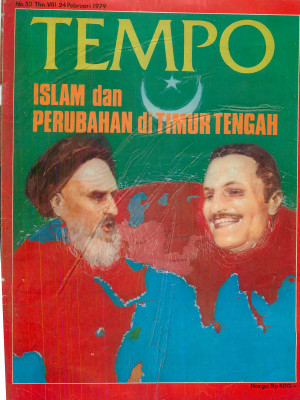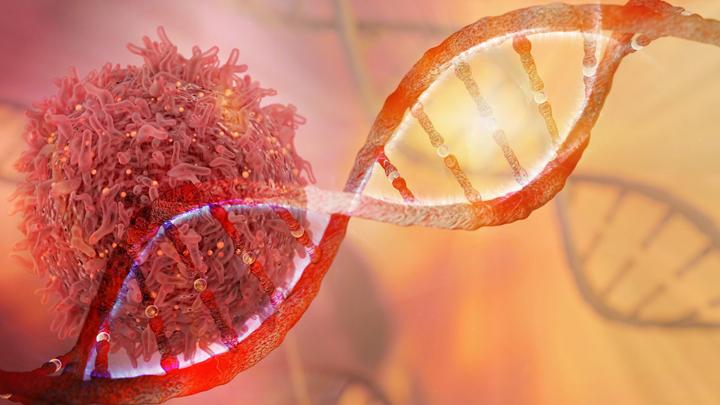DI daerah Karawang, Jawa Barat, juga banyak petani tidak punya
sawah. Mereka menyebut dirinya "buruh tani". Mereka dilahirkan
dari keluarga yang juga tidak punya tanah.
Otong, 49 tahun, di Jatisari, Karawang, menyebutkan ia keturunan
buruh tani. Kini penghasilannya Rp 350 sehari. Ia mencangkul
sawah orang mulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Siang hari
majikannya akan memberi dia makan, tanpa tambahan apa-apa lagi.
Ia masih bisa memilih pekerjaan lain, jadi tukang kayu, tukang
batu, tapi keahliannya tak ada.
Setiap hari, Otong naik sepeda ke Ciasem (12 Km) untuk bisa
menjual tenaganya. Barangkali ini sebabnya tubuhnya jadi segar
terus. "Itu senam pagi yang membuat sehat dan awet muda," ujar
Otong kepada Helman Eidy dari TEMPO.
Otong menumpang hidup di rumah mertuanya. Ia punya anak dua
orang, dengan hidup yang tak pernah enak. Menu makannya setiap
hari sekitar daun singkong, kangkung dan ikan asin.
Kadang-kadang ia sempat menangkap belut atau mancing ikan,
selagi bekerja di sawah. "Kalau tidak begitu tidak akan pernah
makan ikan," katanya.
Otong tidak setuju kalau orang punya tanah secara berlebihan. Ia
melihat sendiri orang kota yang punya tanah di desa seringkali
tidak mempedulikan hidup orang-orang yang tidak bertanah. Tapi
ia bisa berbuat apa? Mula-mula ia berharap anak-anaknya bisa
merubah nasib. Lalu keduanya ia masukkan ke sekolah. "Saya
menginginkan mereka jadi Camat. Camat 'kan enak, punya sawah
lebar-lebar," ujarnya. Tapi mimpi itu tak kesampaian. Karena
kesulitan biaya, kedua anaknya menyerah di kelas III SD.
Sekarang mereka hanya jadi camat di kali, menguber-uber belut
atau ikan untuk tambah-tambah dapur ibunya.
Buruh tani sebenarnya tidak terbatas pada lelaki saja. Perawan,
janda atau nenek, banyak juga yang memburuh di sawah. Hanya saja
pekerjaan mereka musiman. Mereka bukan tukang pacul.
Pekerjaannya terbatas pada saat-saat menyiangi sawah, menanam
benih atau menuai padi. Ini dianggap agak ringan, sehingga
hasilnyapun lebih sedikit. Untuk setengah hari kerja upahnya Rp
100, sedangkan kerja penuh hanya Rp 150. Praktis, kesempatan
memburuh di sawah bagi wanita agak terbatas.
Radinah, 37 tahun, di desa Kuta Ampel, Batujaya, masih di
bilangan Karawang, adalah seorang buruh tani. Tujuh tahun yang
lalu suaminya meninggal. Sakam, suaminya, tidak meninggalkan
apa-apa, kecuali 6 jiwa yang harus dirawatnya. Radinah yang
berasal dari keluarga buruh tani, tak punya kepintaran lain. Ia
tidak punya pilihan lain, kecuali jadi tukang rambet (menyiangi
sawah). Dan karena untuk makan saja sudah susah, tak satupun
anaknya yang mampu ia sekolahkan.
Radinah dengan anak-anaknya makan bubur setiap hari. Kadangkala
Idih, abang iparnya yang berusia 50 tahun (suami almarhum
kakaknya) mengulurkan sekedar bantuan. Sampai-sampai Radinah
yang menumpang di rumah tetangga diberikannya tumpangan,
berlindung di bawah atap rumahnya. Idih sendiri adalah buruh
tani.
Entah karena Tuhan sudah menuliskan sebuah kisah cinta yang
sederhana, Idih dan Radinah akhirnya bersatu. Maka buruh tani
kembali ketemu buruh tani. Ini berakibat lumayan dalam ekonomi
keluarga. Sementara itu tenaga Idih juga sudah mulai luntur,
sehingga lama-lama kurang memenuhi syarat sebagai tukang
cangkul. Sebagai gantinya Idih pergi ke kali Citarum, menjadi
pemikul pasir dengan upah borongan.
Sebelum bersatu dengan Idih, hidup Radinah kadang-kadang
mencekik. Kalau musim rawan, sering tidak makan. Kadang-kadang
hanya punya satu gelas beras bulgur. Ini dibikin bubur campur
garam dan dibagi bersama-sama. Satu ketika keadaan kritis
sekali. Beras nol sejak pagi anak-anaknya menangis minta makan.
Radinah hanya bisa termangu-mangu di pinggir jalan.
Tak tersangka lewat sebuah mobil membawa beras. Tanpa diminta,
seseorang melemparkan kantong berisi 2 kg beras. Radinah
bengong, lalu hanya bisa memuji Tuhan. Sejak saat itu ia sering
Jongkok di pinggir jalan, rupanya lebih menguntungkan timbang
kerja di sawah. Ditatapnya setiap mobil yang lewat. "Mereka kan
datang bawa beras untuk dibagikan," ujarnya. Syukurlah sesudah
bersama Idih, ia meneruskan kembali hidupnya sebagai tukang
rambet.
Ada juga buruh tani yang berasal dari petani biasa. Amad asal
kampung Tengah yang berusia 46 tahun bermula petani biasa.
Ayahnya seorang polisi desa (Opas Culing) punya 3 hektar tanah.
Tanah tersebut kemudian dijual, karena ayahnya takut kalau nanti
jadi sengketa di antara anak-anaknya. Meskipun kemudian hasil
penjualan tanah itu dibagi rata di antara saudara-saudara Amad,
sampai sekarang Amad tidak berhasil punya tanah sendiri.
Bendera Biru
Kesempatan untuk memiliki tanah sebenarnya ada. Tapi Amad waktu
muda lebih membina kariernya sebagai playboy lokal. Ia sudah 19
kali menikah. Seringkali dengan janda atau orang tua kaya,
sehingga ia otomatis punya tanah. Tapi dasar gelisah, pernikahan
itu selalu ditinggalkannya untuk nikah lagi. Akibatnya, pada
usia 46 tahun sekarang, ia tetap tidak memiliki tanah.
Sejak tahun 1973 Amad menyudahi petualangan kawin cerainya.
Isterinya yang terakhir janda berusia 25 tahun. Pernikahan ini
menghasilkan tiga orang anak. Sebagai buruh tani yang menggarap
setengah hektar tanah, Amad sering kewalahan. Karena itu ia
mencoba mencari tambahan dengan menjadi tukang tambal ban
sepeda.
Amad juga berhasil menambah penghasilan dengan menjadi penjaga
Sekolah Dasar di kampungnya. Dari pekerjaan ini ia dapat
fasilitas tanah dekat sekolah, untuk mendirikan gubuk. Tetapi
semuanya berantakan pada saat pemilihan Kepala Desa. Amad
ternyata memilih Kepala Desa yang memakai bendera merah
sementara Kepala Sekolahnya memilih yang pakai bendera biru.
Akibatnya, Ahmad didepak ke luar.
Ketika Ahmad terpaksa harus meninggalkan gubuk tumpangannya,
rekan-rekannya buruh tani mencoba menolong. Mereka mencarikan
pinjaman tanah, di mana Ahmad bisa menegakkan gubuk baru.
Sesudah itu mereka mengumpulkan sekedar sumbangan untuk biaya
pindah Ahmad. Melihat ini Ahmad hanya bisa menitikkan air mata.
Apa daya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini