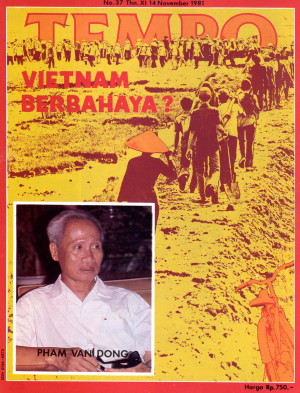GELOMBANG Samudra Indonesia selalu tampak ganas. Tapi penduduk
Cilauteureun Kecamatan Pameungpeuk, Jawa Barat, rupanya tak
peduli. Sebab justru di hamparan batu karang di pantai desa itu,
mereka mengandalkan hidup sebagai pemetik rumput laut! Laki-laki
maupun wanita, lengkap dengan dudukuy (topi lebar dari bambu)
terbongkok-bongkok memetik tanaman laut itu sambil menyeret
kantung plastik sebagai wadah.
Ombak-ombak yang setiap waktu datang menggulung, lalu menghempas
ke pantai, bagaikan benda mainan mereka. Jika seorang melihat
gulungan ombak sedang berlari menuju tepian, dia akan berteriak
mengingatkan temantemannya. Teriakan disambut riuh sambil
mendorong ke pinggir. Begitu ombak memecah dengan keras, mereka
pun berteriak senang sambil berlari ke tempat semula, ke karang
tempat rumput laut itu tumbuh. "Nasib kami memang harus selalu
berpacu dengan ombak--sedikit kurang gesit kami akan ditelannya,
" ungkap salah seorang pemetik rumput laut itu, Said.
Pantai Cilauteureun dan sekitarnya, seperti Gunung Sulah,
Cimari, Ranca Buaya dan Sancang, Kecamatan Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, sejak lama dikenal sebagai penghafsil rumput
laut. Setiap bulan puluhan ton rumput laut diangkut dari pantai
ini. Penghasilan para pencari tumbuhan laut pun lumayan. Bila
sedang mujur, Said misalnya, bisa mengumpulkan 30 kg rumput laut
merah. Bila dari jenis yangbaik setiap kilogram bisa laku Rp
200. Rumput laut hijau, yang biasa disebut kades, laku Rp 40/kg
dan yang bernama pars cuma Rp 15/kg.
Eee, Dia Tersenyum
Ditambah perolehan Itang, istrinya, Said bisa hidup tenteram
dengan empat anaknya. Sayangnya ia cuma bisa beroperasi bila
laut sedang surut. Yaitu sekitar tanggal 1 - 4, tanggal 11 - 13
dan tanggal 26 - 29 tiap bulan. ltu pun hanya untuk sekitar 2 -
3 jam. Di luar waktu itu, ombak Samudra Indonesia sungguh tak
bisa diajak berkompromi.
Di saat air pasang, para pemetik rumput laut biasanya
menganggur, meskipun ada juga yang tetap nekat, tak mempedulikan
gelombang. Tapi Eon tak merasa kecil hati. "Tuhan memang telah
mengatur begitu," katanya, "kalau rumput laut bisa dipetik
setiap hari, pasti akan segera habis." Jadi, katanya lagi, air
pasang itu ada hikmahnya juga.
Menyadari bahaya yang mungkin timbul, terkadang Said dan Itang
merasa ngeri. Tak hanya diancam terkaman ombak, terperosok ke
celah batu karang yang bisa mengundang maut. Paling sedikit
kalau sedang sial, kaki tersenggol bulu babi, sejenis binatang
laut yang punya duri berbisa.
Tapi rasa ngeri segera sirna bila ingat, keempat anak mereka
perlu makan. Lagi pula, mencari rumput laut punya arti
khusus--yang romantis--bagi suami istri ini. Said membisikkan
peristiwa yang dialaminya sekitar 16 tahun lalu. Ketika itu ia
masih bujang dan Itang yang lagi "mekar" banyak diincar pemuda.
Seperti biasa mereka mencari rumput laut. Tiba-tiba ombak
bergulung cepat sekali. Semua lari pontang panting menyelamatkan
diri. Tak sengaja Said menabrak Itang. Keduanya jatuh saling
tindih, gelagapan kena air laut. Semula Said mengira Itang akan
marah-marah. "Ternyata . . . eee, dia tersenyum," kata Said.
Sejak itu keduanya tambah intim dan lalu bersumpah setia di
hadapan penghulu .
Walau harus sering menganggur, pencari rumput laut umumnya
enggan jadi petani. "Mencari rumput laut lebih menguntungkan,"
tutur Enoh. Ia pernah membuktikannya dengan bertanam kacang
tanah. Dari areal seluas 1.500 meter, ia cuma bisa memetik 2
kuintal atau Rp 100 ribu. Itu pun setelah bekerja keras dan
menanti 3 bulan lamanya.
Memetik rumput laut, sekali turun Enoh memperoleh Rp 700. Dan
kerjanya cukup santai. "Kalau gesit, bisa mendapat lebih
banyak," kata ibu dari lima anak ini. Sang suami yang ikut turun
ke pantai, membuat keluarga mereka hidup cukup memadai.
Usaha KUD Unit Rumput Laut Pameungpeuk pun turut lancar.
Ketuanya, Ondo, biasa membeli rumput laut yang sudah agak kering
Rp 130/kilo. Di KUD rumput itu disortir dan dikeringkan lagi.
Satu kuintal rumput laut basah, paling banyak menjadi 10 - 15.kg
bila sudah kering. Harganya pun sudah melonjak jadi Rp
600/kg--untuk selanjutnya diangkut dengan truk ke Jakarta atau
Surabaya. Untuk selanjutnya diekspor atau diolah -di dalam
negeri. Selain untuk bahan kue (agar-agar) rumput laut berguna
untuk industri gula, cat, karet atau film.
Kabar selentingan bahwa ekspor rumput laut dihentikan, sempat
pula singgah di telinga Ondo. Ia menuding kabar itu dilontarkan
sesuatu pihak untuk menekan harga. Tanpa ekspor, katanya, pabrik
agar-agar dalam negeri sebenarnya cukup banyak menyedot rumput
laut. Nyatanya, omzet penjualan KUD yang dipimpinnya sampai
sekarang tak mengalami perubahan.
Para pencari rumput laut pun tetap tenang bekerja. Kokom, gadis
berusia 13 tahun, biasa turun ke pantai bersama ibunya. Yang
bisa dikumpulkan mereka tak banyak, hanya sekitar 20 kg rumput
laut jenis kades atau paris. Mencari rumput laut merah atau
biasa disebut agar-agar, mereka tak berani. Jenis yang harganya
lebih mahal ini tumbuh jauh di tengah laut. Kokom dan ibunya
cukup mencari yang tumbuh di pinggiran, karena mereka tak kuat
berlari kencang menghindari ombak. Toh hasilnya lumayan. Kokom
bisa membiayai sekolahnya. Ia kini duduk di kelas VI SD.
Peristiwa tragis pernah menimpa Uus. salah seorang pemetik
rumput laut. Pemuda berusia 20 tahun (ketika itu) seperti biasa
turun ke batu karang. Tiba-tiba ombak besar datang. Teriakan
peringatan agar menghindar, tak sempat didengarnya. Tapi Uus
yang berada jauh di tengah masih mencoba berlari. Ia terpeleset
dan jatuh terjerembab. Ombak besar datang, lalu menyeretnya ke
tengah Laut Kidul.
Sampai kini mayat Uus tak pernah ditemukan. Itu sebabnya Odi,
saudara sepupu Uus, agak ngeri bila melihat mendung dan ombak
yang menderu bergulung-gulung. "Bulu kuduk saya selalu berdiri,"
katanya. Di saat begitu, ketimbang mengalami nasib seperti Uus,
ia merasa lebih baik pulang ke rumah dengan tingan hampa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini