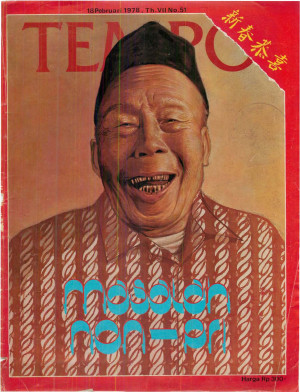BERNAMA Tarmiji. Tidak sempat makan sekolahan - dan barangkali
itu sebabnya ia jadi lugu dan nekad. Dengan pertolongan seorang
kawan, ditulislah sebuah surat ke pusat pemerintahan Republik
Indonesia: Jakarta. Dialamatkan kepada Laksamana Sudomo. Isinya:
pengaduan nasib seorang rakyat kecil yang kena gusur di sudut
Kota Samaria.
Tarmiji dalam keadaan sangat sedih. Ia telah membuat serangan
perdata menggugat kebijaksanaan Walikota Samarinda. Tetapi
barangkali terlalu banyak loket, terlalu banyak meja, kursi dan
tumpukan kertas, yang telah mengganjal gugatannya sehingga tak
pernah menggigit. 3 tahun ia menunggu dengan was-was. Sedang
rumahnya telah lama diratakan dengan tanah oleh petugas
Balaikota atas nama Repelita 1975. Idham Cholid.
Sesungguhnya orang tua berdarah Kalumantan ini hanya minta porsi
perhatian yang lebih baik untuk ganti kerugian. Jadi bukan emoh
digusur. "Baik tanah maupun rumah kami, ada surat-menyuratnya,"
ujar bapak dari lima orang anak itu. Memang. Sudah beberapa kali
ia dipanggil oleh tim pembebasan tanah. Tapi sayangnya bukan
merundingkan soal harga yang pantas, tapi buat mendengarkan
bujukan. Rayuan. Dan kemudian ancaman. Bahwa ia harus segera
angkat kaki dari sisi Hotel Internasional Lamin Indah, yang
termasuk barang paling mewah sekarang di sana.
Sadar pada haknya, Tarmiji tetap menolak sebelum ada penegasan
mengenai harga ganti rugi. Apalagi kalau dikenangkan: tanah
pengganti yang diulurkan untuk kediamannya yang baru adalah
tanah kampung - yang juga hanya dipinjamkan tidak lebih dari 3
tahun. Tarmiji membangkang dan berhasil mengelak dari segala
bujukan. Maka ia pun dikecam sebagai penghalang pembangunan.
Stempel itu tentulah merupakan muatan buruk bagi hidup seseorang
di pedalaman. Namun si tua ini tidak takut hanya ancaman
pembongkaran paksa membuat ia panik. Sebagai akibat, tekadnya
untuk memperjuangkan keadilan setidak-tidaknya menurut ukuran
Tarmiji sendiri - makin membaja. "Seng hewan saja dibangunkan
kandang scbelum dipindah. Masak saya lebih rendah dari hewan,"
kata orang tua itu dengan sebal.
Kisah ini kemudian seperti cerita pendek Anton Chekov, itu
pengarang kesohor Rusia yang lucu dan sekaligus getir memotret
masyarakat. Entah dari mana datangnya gelombang fikiran, Tarmiji
malam itu teringat sebuah nama yang disanjung-sanjung di
Amuntai, Kalimantan Selatan. Negeri asal orangtuanya itu masih
memiliki sebuah nama besar sebagai lambang kebanggaan daerah dan
fanatisme NU. Dialah KH Idham Cholid -- waktu itu menjabat Ketua
DPR/MPR.
Isterinya, yang sudah tidur, dibangunkan. Sekarang ia yang
mencoba membujuk isterinya. Agar kalung yang melingkar di leher
wanita itu dilepaskan. Demikian juga cincin yang masih cukup
berharga untuk dijual. Isterinya bengong. Tapi Tarmiji sudah
bulat. Ia ingin mengadukan nasibnya kepada Idham Cholid. Tidak
melalui surat, tapi langsung dari mulut ke mulut dengan empat
buah mata, dengan mengandalkan "solidaritas satu kampung".
Rancangan yang tiba-tiba itu membuat seisi rumah tidak tidur
sepanjang malam.
Pagi berikutnya, Tarmiji langsung ke pasar. Tidak banyak, tapi
cukup untuk terbang ke Jakarta. Dasar orang sederhana, ia tidak
berfikir jauh-jauh bagaimana nanti di Jakarta dan bagaimana
pulangnya. Dengan menggagahkan hatinya ia pun memasuki kendaraan
yang baru pertama kali dijamahnya. Melayang di udara, penuh
semangat bahwa Jakarta akhirnya akan membagikan keadilan dengan
merata kepada seluruh warga dipelosok dengan tidak pandang bulu.
Minta Hotel
Di Pelabuhan Udara Kemayoran, tatkala para penumpang dengan
tenang menuju arah masing-masing, Tarmiji baru tercenung. Ia
begitu terlena dan kagum. Begitu ramai, begitu banyak orang.
Seorang sopir taksi kemudian memungutnya. Kebetulan sopir baik,
tahu di mana rumah Ketua DPR itu. Tarmiji langsung dibawa ke
depan pintunya. Dihadapkan kepada seorang ajudan. Orang tua ini
cepat pasang omong dalam bahasa Banjar: "Saya datang ke mari
mencari hukum, macam apa keadaan hukum di sini?"
Tentu saja ajudan heran. Tapi setelah ia faham apa yang terjadi,
ia jatuh simpati. Apalagi ternyata Idham Cholid berkenan
menerima Tarmiji. Lebih dari itu, orang kampung ini dipersilakan
menginap di rumah sang pejabat. Herannya Tarmiji menolak. Ia
minta hotel. Lho kenapa? "Ya supaya bisa meragakan macam apa
hotel itu," jawabnya kalem.
Ia memperoleh sebuah hotel di bilangan Senen. Tapi dari posnya
ini ia tidak benar-benar dapat mengetahui apa sebenarnya yang
terjadi di Jakarta. Ia hanya berkurung dalam kamar. "Habis saya
tidak berani ke luar kamar, dan tidak bisa tidur. Hotelnya besar
sekali dan dingin." Nama hotel itu saja ia tidak tahu. Pagi
harinya sedan Menteri-ini istilah Tarmiji sendiri - sudah datang
menjemput dengan seorang ajudan. Hebat juga Tarmiji ini. Ia
berhasil memperoleh sebuah surat pengantar dari tangan Idham
Cholid.
Dengan senjata surat tersebut, Tarmiji mulai menembus
gedung-gedung penting yang barangkali cukup sulit bagi orang
Jakarta sendiri. Tanpa banyak halangan, lancar seperti arus air
Sungai Barito atau Mahakam ia menemui Mendagri Kapolri, Jaksa
Agung, Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung akhirnya
langsung ke Bina Graha menemui Menteri Sudarmono. Hanya dalam
tempo satu hari saja ia berhasil mengumpulkan tanda tangan dan
stempel dari para penjabat tersebut.
Semuanya tertera dalam sebuah surat, yang isinya pada pokoknya:
agar pembongkaran dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku.
Sebuah itikad baik yang kedengarannya manis, tetapi masih
merupakan formulasi kata-kata yang terlalu menggaris besar --
sementara Tarmiji memerlukan butir-butir keputusan yang konkrit.
Tapi dasar orang sederhana, si tua ini merasa sudah cukup
kuat dan puas.
Hari kedua warga Samarinda ini ditemani seorang ajudan
melihat-lihat Jakarta. Duka hatinya di Samarinda jadi terobat.
Ia merasa yakin kini bahwa Idham Cholid benar-benar - seorang
Amuntai yang baik. Lega, senang merasa mendapat perlindungan
sebagai rakyat. Ini semuanya membuat ia pulang kampung
bagaikan "pria Brisk" - penuh kepercayaan diri.
Sampai Padang Mahsyar
Sesampainya di tanah lahir kembali Tarmiji punya kesibukan baru.
Ia mengedarkan fotokopi surat penuh tanda tangan yang hendak
dipakainya sebagai senjata pemungkas. Dari Camat ke Walikota
sampai Gubernur dan Laksus disentuhnya dengan surat tersebut
hatinya berubah mantap. Lalu ia pun mendapat kegairahan bekerja
sebagai pedagang kayu. Isterinya tidak merasa sedih lagi karena
kehilangan kalung, sebab buahnya jelas kelihatan.
Tapi empat hari setelah menyebarkan fotokopi, aduh -- rumah
Tarmiji dirobohkan dengan paksa. Tiang-tiangnya diikat dengan
tali, kemudian ditarik oleh mobil. Tarmiji tak melihat kejadian
itu karena sedang di pasar. Begitu pulang, segalanya sudah rata,
berikut tiga buah rumah yang bersebelahan. Ranjang dan kasur
memang sempat dikeluarkan tapi barangbarang lainnya tertimbun
atap. "Dasar benar-benar tidak ada hukum di sini," kata Tarmiji
mengenangkan peristiwa itu kepada Dahlan Iskan dari TEMPO.
"Sedihnya lagi, anak saya belum satu hari melahirkan? terpaksa
dipikul seperti mayat. Saya segera mencari di mana isteri saya.
Ternyata ia juga selamat."
Demikian kekalahan Tarmiji. Kemudian dia nebeng di rumah
iparnya--selama satu setengah tahun. Tapi juga dengan rasa
waswas karena rumah itu terancam digusur. Tarmiji akhirnya
memutuskan pindah dari situ, paling tidak untuk menenangkan
fikirannya sendiri. Ia berhasil membangun sebuah rumah yang
sampai sekarang belum benar-benar rampung. Ini pun ternyata
tidak aman.
Sekali waktu, kediamannya yang baru ini didatangi tentara yang
menanyakan apakah orang tua ini memiliki izin bangunan. Apa
jawab Tarmiji? "Buat apa izin. Pakai izin dibongkar, tidak juga
dibongkar." Hati terus kesal mengingat gugatannya tak pernah
digubris. "Sampai di hadapan Tuhan tetap akan saya tuntut. Nanti
di Padang Mahsyar saya akan adukan."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini