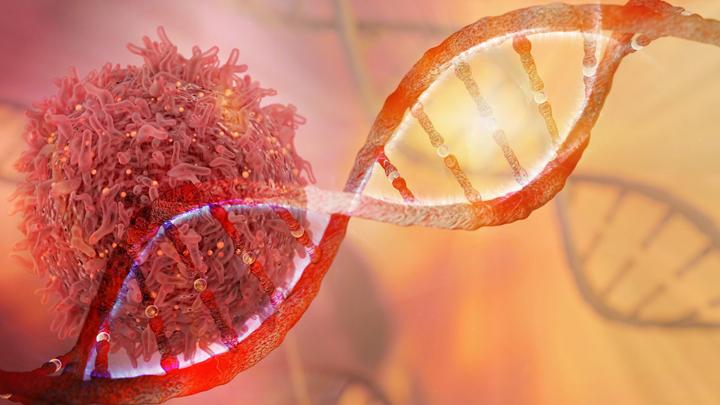ANDA pusing karena obat? Bisa dipahami, bila Anda hidup di Indonesia. Soalnya: harganya mahal amat. Kabarnya, harga obat di sini termasuk termahal di Asia Tenggara, terutama yang dijual di apotek. Ini soal yang tidak baru, tapi hangat lagi, ketika ada sebuah ide yang kontroversial untuk mencoba memotong biaya obat itu. Caranya: biarkan dokter memberikan obat langsung pada pasiennya, atau disebut self-dispensing. Ide ini datang dari Musyawarah Kerja (Muker) XI Ikatan Dokter Indonesia di Medan bulan lalu. Salah satu keputusan: menjajaki kemungkinan dibolehkannya dokter melakukan self-dispensing obat. Keputusan Muker yang dihadiri 169 pimpinan cabang IDI dari seluruh Indonesia itu antara lain didasarkan pada kenyataan tingginya harga obat di Indonesia. Tentu saja banyak yang kaget, termasuk Menteri Kesehatan sendiri. Maka, pagi-pagi Menteri Suwardjono menyatakan menolak ide self-dispensing itu. "Peracikan dan penyerahan obat keras merupakan wewenang dan tanggung jawab profesional apoteker," ujar Menteri, ketika membuka Konperensi Nasional Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, pekan lalu di Jakarta. Selain Menteri, juga sang dirjen pengawasan obat dan makanan (POM). Dirjen POM itu, Midian Sirait, tak bisa menerima alasan dispensing untuk mempermurah harga obat. "Soalnya, harga itu bergantung sepenuhnya pada industri obat dunia," katanya. Midian juga mempertahankan bahwa usaha menurunkan harga obat sudah banyak dilakukan pemerintah. Misalnya, program "Dana Sehat" bagi pegawai negeri, dan pelayanan obat DOPB (Daftar Obat Program Bersama), yang sejak Maret lalu digemakan ke semua ibu kota provinsi. "Biaya resep DOPB untuk setiap paket pengobatan berkisar antara Rp 500,00 dan Rp 2.000,00. Jauh lebih murah dibanding resep biasa yang bisa sampai Rp 10 ribu," ujar Midian. Keberatan ternyata juga tak hanya datang dari Depkes. Prof. Dr. Iwan Darmansjah, guru besar farmakologi UI, menyebut bahwa self-dlspensng berkemungkinan merugikan pasien juga. Kata Iwan, "Kalau dokter salah memberi obat, dengan self-dispensing itu, lalu siapa yang bisa mengontrol ?" Sejalan dengan Iwan, ahli ekonomi kesehatan, dr. M. Hasan, turut pula mengkhawatirkan akibat buruk self-dispensing, terutama jika hal itu dilakukan oleh para dokter di kota besar. "Jika praktek seorang dokter tidak menguntungkan, ia bisa cari keuntungan lewat self-dispensing ini," kata Hasan. Kalangan dokter tentunya paham alasan keberatan seperti itu. Meski demikian, IDI tampaknya sudah bertekad untuk tetap mengajukan hasil Muker itu kepada Depkes. Kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI, dr. Kartono Mohamad, setengah bergurau, "Jika tidak, saya bisa digantung teman-teman saya. Ini 'kan keputusan Muker." Sejauh ini, usulan itu -- lengkap dengan segala perinciannya -- baru dalam tahap disusun perumusannya. Tapi Kartono mengharapkan sebelum akhir tahun ini ide IDI itu sudah bisa diserahkan kepada Depkes. Soalnya, bagi IDI, ide perubahan dispensing obat itu bukan datang dari angan-angan. Sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan, yang banyak terjadi dewasa ini, adalah banyaknya obat keras yang dijual bebas di toko obat. Ini bisa membahayakan penderita. Sementara itu, seperti kata dr. Suhantoro, ketua IDI cabang Jakarta, dokter, termasuk yang berpraktek di daerah yang ada apotek, "boleh menyediakan obat-obat suntik tertentu dan obat emergensi di tempat prakteknya." Kenyataan lain, banyak pasien yang minta diberi obat oleh dokter sendiri. Selain itu, banyak pula resep yang oleh si pasien cuma diambil sebagian saja di apotek, mungkin buat menghemat, hingga mengurangi dosis yang semestinya. Yang menarik ialah hasil penelitian yang dilakukan IDI di tujuh provinsi, sebagaimana dikemukakan Suhantoro. Dari pengumpulan kuesioner, didapat hasil bahwa 90% dokter di tujuh provinsi itu sudah melakukan praktek self-dispensing. Kenyataan bahwa ini terjadi -- meski melanggar peraturan pemerintah -- menyebabkan Muker IDI bersepakat untuk mengajukan usulannya tadi, dengan catatan: perlu adanya aturan yang tidak merugikan pasien. Usulan itu, menurut Kartono, bukan dimaksudkan untuk mencabut peraturan yang dibuat zaman Belanda itu, "melainkan mengubah hal-hal yang tadinya berlangsung secara ilegal, supaya diatur lebih jelas dan tegas." Dengan demikian, jika usulan ini diterima, menurut Kartono, pasien juga yang untung. Pasien lebih dimudahkan urusannya memperoleh obat. Ia bisa menghemat biaya yang mesti dikeluarkan, karena tak ada ongkos penulisan resep, dan tak perlu uang buat transpor ke apotek. Mendengar ini, apoteker dan pengusaha apotek memang bisa berteriak. Tapi menurut Kartono, mereka ini tak perlu takut kehilangan peran. "Sebab," katanya, "bagaimanapun, obat yang disediakan untuk dispensing itu terbatas pada obat esensial yang sering digunakan." Akan halnya obat racikan dan obat nonesensial, tetap saja dokter mesti menuliskan resepnya untuk apotek. Dalam urusan ini, Indonesia sebenarnya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Menurut Suhantoro, sejauh ini di beberapa negara ASEAN dan Jepang dokter juga dibolehkan melakukan self-dispensing. "Dan apotek pun di sana berjalan seperti biasa, tidak mati," ujar Suhantoro pula. Para pengurus IDI juga membantah kecemasan bila self-dispensing ini akan dengan sendirinya berakibat buruk bagi pasien. Bukankah, kata Suhantoro, di perguruan tinggi, mahasiswa kedokteran diajar ilmu farmasi dan farmakologi? Menurut Kartono, IDI menyadari kemungkinan bahaya self-dispensing, dan "akan kami bicarakan juga cara pencegahannya" -- mungkin berikut masuknya usul itu. Tentu saja akan lebih baik bila pertimbangan seperti yang dikemukakan Iwan Darmansjah dan Hasan dibahas lebih jauh. Sementara itu, ada juga pendapat bahwa jika soalnya adalah tingginya harga obat, barangkali self-dispensing oleh dokter bukan satu-satunya cara pemecahan. Harga lewat apotek memang berat. Tapi siapa tahu kenaikan berkala harga obat -- tiap 3-6 bulan -- yang datang dari sebagian pabrik, juga merupakan sumber utama tingginya harga itu. Bila itu soalnya, seluruh ekonomi pengobatan -- dan kesehatan -- di Indonesia memang perlu diperbaiki. Siapa tahu itu tugas Depkes yang belum selesai. Syafiq Basri, Moebanoe Moera, Ahmadie Thaha, dan Tri Budianto Soekarno (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini