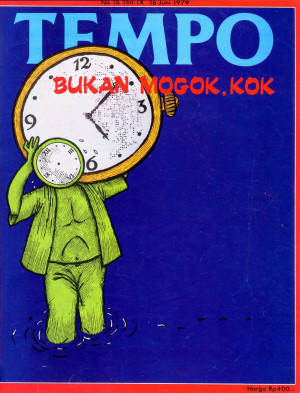DI Sumatera Utara, kulit ular sawah termasuk bahan ekspor.
Setelah Kenop 15, harganya dapat angin. Orangpun bertambah
gencar berburu ular. Lalu seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan
bernama Nurdin Otek Biyong yang juga merangkap ketua Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia mulai takut. Di dalam forum DPRD ia
menyerukan perlunya perlindungan terhadap ular sawah. "Kalau
diburu terus, bisa musnah, kalau musnah akan merusak
keseimbangan lingkungan dan tikus merajalela," katanya.
"Satu saat nanti pasti ular akan habis," kata A Hwa, 46 tahun,
seorang pedagang ular yang tinggal di jalan Hasanuddin --
Kisaran. Ia telah menjadi pedagang ular sejak tahun 1974. Ketika
usahanya mulai, rata-rata setiap hari ia bisa membeli 4 ekor
ular dari penduduk. Sekarang paling banter hanya tiga, itupun
dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Dulu ia masih bisa kasih
syarat minimal panjang ular 2,5 meter, sekarang sulit. "Dulu
cari ular panjang 3 meter tak sulit," kata A Hwa. Malah dia
sering dapat yang mencapai lima atau enam meter. "Sekarang cari
yang dua meter saja susah," katanya.
Diternakkan
Menurunnya jumlah ular, dapat dibuktikan dengan melihat
perjalanan yang harus ditempuh Hwa. Dulu ia cukup berkeliling
seputar kecamatan Kisaran (Kabupaten Asahan). Sekarang harus
melangkah keluar Kisaran, terkadang sampai ke Kabupaten Labuhan
Batu. Jadi meskipun Kenop 15 bikin harga melonjak, tak urung Hwa
ketir-ketir juga jadi pedagang ular. Apalagi ada kepercayaan
dari nenek moyangnya yang selalu menggodanya: cari duit dari
ular ditantang oleh kutukan.
Selama berurusan dengan ular Hwa belum melihat bagaimana wujud
dari kutukan tersebut. Bahkan ia belum pernah sampai kena gigit.
Menurut teorinya, ular sawah adalah binatang yang paling bodoh
dan malas. Bila sudah tidur bergulung, gampang sekali
menangkapnya, walau dengan tangan kosong. Caranya? Pegang saja
dia punya kepala, lalu masukkan ke dalam goni, ular tinggal
menurut saja. Bermula penduduk memang banyak yang takut, tapi
setelah tahu binatang itu bisa bikin duit -- apalagi belakangan
makin banyak bukti pemalas itu tidak bisa bikin celaka orang
beramai-ramai menangkapnya.
Bila ular sudah sampai di tangan Hwa, berarti maut sudah tiba.
Hwa memberinya minum air tembakau. Tak sampai 15 menit ular itu
kontan mati lemas. Lalu dengan sebilah pisau tajam, kulitnya
dilepas. Selama dua hari kulit itu dijemur -- tetapi tidak boleh
di panas terik, karena sisiknya akan gugur dan harganya bisa
jatuh.
Sekali seminggu Hwa mengirim paket kulit ular kepada taukenya --
seorang importir di jalan Pandan -- Medan. Berapa untungnya?
"Itu er ha es orang dagang," kata Hwa -- maksudnya "rahasia." Ia
juga keberatan mengungkapkan berapa harga ular yang diopernya
dari para petani. "Pokoknya kita musti kasi harga yang pantas,
karena sekarang banyak saingan, dan barang kian sedikit,"
ujarnya. Ia sudah mencium jejak dua orang pedagang kulit dari
Medan yang turun ke Kisaran, untuk berburu ular. Gawat.
Meskipun tidak mengaku, semua orang dapat mengukur bagaimana
keadaan ekonomi Hwa. Ia termasuk hidup cukup. Ia punya dua motor
gerobak (prah) yang masih baru. Punya ladang 5 ha yang ditanami
padi. Padahal sebelum menjadi pedagang ular, ia hanya kenek bus.
Tapi apakah ia akan dapat mempertahankan seluruh kekayaannya
itu, kalau persaingan sudah semakin ketat serta jumlah ular
berkurang? Hwa cepat menjawab: "Kalau ular nanti sudah habis,
saya jadi petani saja."
Hwa yakin ular akan segera habis, kecuali kalau diketemukan cara
untuk menternakkannya. "Tapi saya tak tahu apa bisa diternakkan,
soalnya makannya terlalu kuat, bisa satu ekor kambing, apa bisa
untung kalau begitu?" kata Hwa. Namun ia termasuk pedagang yang
sanggup bertahan. Satu-satunya yang masih ada di Kisaran. Tiga
lainnya sudah gulung tikar.
A Huat, 35 tahun, adalah salah seorang veteran pedagang ular, di
kawasan Binjai Baru -- Kecamatan Talawi -- masih Kabupaten
Asahan. Pengundurannya dari percaturan ular, karena dua hal.
Ular mulai habis, juga karena termakan oleh kepercayaan adanya
kutukan. "Untungnya memang tetap berlipat, tapi coba cari, tak
ada orang yang bisa kaya karena ular," ujarnya.
Huat mengaku jadi pedagang ular pada tahun 1974, karena pailit
sebagai "kedai sampah" (bahan-bahan keperluan dapur). Seseorang
memberi nasehat, agar ia berdagang ular untuk menghidupi anak
isterinya. Mula-mula hati Huat keder, karena itu kedengarannya
janggal. Dari kecil ia menyimpan cerita-cerita busuk tentang
ular. Bahwa binatang itu bisa mencelakakan atau bahwa binatang
itu adalah lambang orang yang culas. Toh ia sambar juga akhirnya
demi perut.
Kebetulan di sekitar tempat tinggalnya, terbentang persawahan
rakyat -- alias rawa-rawa. Ular di sana menjadi musuh petani,
diburu, kalau ketemu, dicincang sampai mati, bangkainya
diserakkan ke belukar. Huat lantas bikin maklumat, agar binatang
itu dibiarkan hidup, dijual kepadanya. Para petani tidak banyak
bertanya, langsung menyambut pengumuman itu. Malah beberapa
petani mulai sibuk menjadi pemburu ular. Habis harganya melawan.
Untuk ular yang panjangnya 3 meter, Huat berani bayar Rp 1500.
Melonjak sampai Rp 3000 untuk yang mencapai 5 meter.
Sebagai pedagang ular satu-satunya, Huat jadi orang berkuasa
dalam menentukan harga. "Saya tawar murahpun mereka pasti
melepasnya, habis mereka mau bawa ke mana lagi. Sedangkan mereka
tak perlu keluar modal," kata Huat. Ia juga mengaku bahwa
untungnya berlipat ganda. Sebab kalau petani menjual kepadanya
"per ekor" -- A Huat menjual lagi ular itu kepada pedagang kulit
dengan meteran. Satu meter harganya Rp 1500. "Rata-rata satu
bulan saya bisa untung bersih Rp 200 ribu," katanya
mengenangkan.
Meskipun perdagangan ular mencetak angka-angka ajaib, ternyata
keluarga Huat merasa tidak tenang. Ibu dan neneknya terus
marah-marah saja. Menurut mereka, pekerjaan Huat dikutuk Tuhan.
"Padahal saya tak pernah membunuh ular, karena kata mak pantang
besar," ujarnya. Jadi ia hanya meneruskan saja ular itu, dari
petani, ke pisau maut pedagang kulit. Padahal kalau menguliti
sendiri, untungnya bisa makin berlipat.
Akhirnya keuntungan saja tidak dapat membahagiakan hati Huat.
Karena betapapun banyak untungnya -- dengan secara mengherankan
Huat tak bisa kaya. Begitu uang masuk, begitu pula keluar
seperti sulapan. Ada-ada saja. Terkadang ada anggota keluarga
yang sakit. Terakhir Huat sendiri yang nyaris dijemput maut
dalam kecelakaan sepeda motor. Ini menyebabkan pedagang itu
mulai berpikir kembali.
Akhirnya ia mulai percaya cari duit dari ular bisa sial. Lalu ia
buka koceknya dan menukar usaha, mendirikan pabrik minyak
goreng. Sebuah pabrik kecil-kecilan saja. Ternyata usaha baru
ini berhasil, lalu sejak tiga bulan yang lalu, ia berhenti
mengurus ular. Tak peduli harga kulit melonjak sejak Kenop 15,
sedangkan para petani masih menjual dengan harga lama. "Sudahlah
saya berhenti saja, walau untungnya banyak, saya takut kena
kutukan, apalagi saya punya anak," kata Huat. Kemudian
ditambahkannya "Satu saat nanti pasti ular itu akan habis!"
Berkurangnya ular dengan jelas terlihat pula buktinya di rumah A
San alias Hasan, 40 tahun. Pedagang ular yang tinggal di desa
Simpang Gabus (Kecamatan Lima Puluh -- Kabupaten Asahan) ini,
hanya mampu mendapatkan ular-ular kecil. Pada suatu hari Amran
Nasution dari TEMPO melihat dua orang anak kecil berusia 10
tahun memakukan kulit-kulit ular kepada sebilah papan -- dalam
ukuran hanya satu meter. "Itu ular air, bukan ular sawah, ujar
nyonya A San, 35 tahun, menjelaskan.
Menurut sang nyonya, sudah sejak heberapa bulan terakhir ini
harga kulit memang naik. Lalu tauke-tauke di Medan mau menerima
kulit ular kecil, baik ular air, ular tenggiling atau ular sawah
gendang -- sejenis ular sawah yang tak mau besar dengan perut
buncit. Jenis-jenis ini panjangnya hanya antara satu sampai dua
meter -- harganya hanya Rp 75 sampai Rp 100 per ekor. Selama 10
tahun menjadi pedagang ular, nyonya itu mengakui jumlah ular
sudah berkurang sekarang. "Dulu cari lima ekor satu hari tak
sulit, sekarang dapat satu ekor ular sawah satu hari, sudah
lumayan," katanya.
Setelah ular sulit, keluarga A San menyusun strategi kerja baru.
Sang suami naik sepeda motor, keluar-masuk kampung mencari ular.
Sang isteri bersama anaknya, 10 tahun, serta dua anak tetangga
(dengan gaji Rp 500 sehari) di rumah menguliti dan menjemur.
Selain ular, biawak juga digarap, meskipun harganya tak
seberapa. Biawak yang kulitnya mulus harganya Rp 2000. Yang agak
cacat akibat pukulan waktu menangkap turun sampai Rp 1500. Yang
kelas tiga karena banyak cacatnya hanya berharga Rp 750.
Sementara anak biawak dihargai Rp 200.
Serius Lho
Bininya A San ini bukannya tidak percaya, cerita sial bagi
pedagang ular. Ia juga heran setelah tahunan berusaha, dengan
mengerahkan seluruh keluarga, toh hidupnya tetap susah. Tapi
sejauh ini keluarganya belum punya rencana untuk berhenti.
"Habis, mau usaha apa lagi? Buka toko tak punya modal," ujarnya.
Diakuinya terus terang para tetangganya ada yang kurang senang.
"Mereka was-was, habis rumah saya ini kan gudang ular," katanya
lebih lanjut. Apalagi pernah seekor ular lolos dari goni lalu
ngumpet di kolong rumah tetangga. "Ular itu hancur dipukuli dan
saya rugi karena tak bisa bikin duit, padahal ular sawah tak
berbahaya dan tak mengganggu orang," keluhnya sedih.
Ular sawah memang tidak berbahaya. Usman anak A San juga sering
digigit. tapi pakai obat merah saja sudah cukup sebagai
penawarnya. Nurdin Otek Biyong itu anggota DPRD mungkin juga
melihat bahwa hewan itu tak perlu dipunahkan, karena memang
tidak berbahaya. Demikianlah sejak tahun 1976, ia ribut perkara
menurunnya jumlah satwa itu. "Tetapi kawan-kawan di DPRD hanya
tertawa mendengar usul saya. Mereka menduga saya hanya
berkelakar, padahal saya serius lho," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini