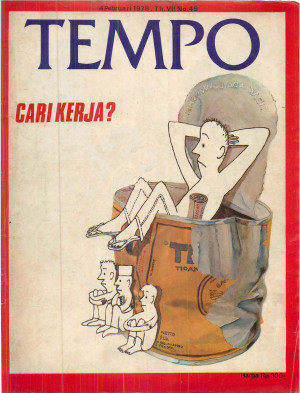ANAK muda yang tak dikenal di Ibukota itu tiba-tiba punya ide:
ia harus datang ke DPR.
Umurnya 26 tahun. Namanya Urip Murtado. Ia asli Jakarta. Putus
sekolah. Di pagi hari ia setengah menganggur menyewakan tenaga
untuk mengapur rumah, kadang-kadang. Di sore hari ia berjualan
koran Sinar Harapan dan Pos Sore. Ketika ia mendengar bahwa
kedua koran itu dilarang terbit, ia merasa injakan hidupnya
terancam. Ia tergerak untuk mengadu. Ia mengajak tiga orang
temannya ke gedung DPR. Siapa tahu ada wakil rakyat nun di sana
yang mau mendengar nasibnya.
Hari itu Senin 23 Januari 1978. Setelah naik bis dari daerah
Selamba jam 8.30 pagi ke daerah Senayan, empat pemuda itu
mungkin merupakan delegasi pertama yang datang ke parlemen untuk
membicarakan masalah pers nasional setelah dilarangnya 7 koran
terbit. Tentu saja mereka datang dengan ditunggangi "kepentingan
tertentu": supaya periuk nasi mereka tak terguncang. Mereka
diterima oleh wakil Fraksi PPP dan Fraksi Karya. Lalu hari
keburu siang, jam 12.30, dan mereka memutuskan pulang. Mereka
memang cuma 4 orang, kata Urip, karena kalau membawa
kawan-kawannya kebanyakan anak-anak kecil - bisa dianggap
demonstrasi. "Nanti malah ditangkap," kata Urip. "Yang kami
khawatirkan ialah kalau lama-kelamaan modal kami habis hanya
buat makan saja."
"Tunggulah .... "
Para wakil dari Fraksi PPP dan Karya tentulah mengangguk-angguk
mendengar permintaan anak-anak dari tepi jalan ini. Dan Urip dkk
- yang tidak insyaf betul lika-likunya pekerjaan para anggota
parlemen - pun menunggu: siapa tahu hari Selasa esoknya suara
mereka sudah didengar dan barang dagangan mereka diijinkan
beredar kembali.
Tentu saja tidak. Hari Rabu, agak cemas agak kecewa dan
sekaligus agak nekad dalam berharap, mereka mencoba mengadu ke
Kaskopkamtib Sudomo. Seorang petugas di Kopkamtib, menurut Urip,
menasihatinya supaya tenteram. "Tunggulah," katanya,
"pembreidelan ini tidak lama, hanya sementara." Patuh, Urip dan
kawan-kawannya pulang lagi - mengurungkan niat mereka buat
menemui Menteri Penerangan.
Urip merasa punya alasan kuat untuk resah. Ia, yang selama jadi
pengecer koran sore bisa memperoleh penghasilan Rp 700 sehari,
adalah anak kedua dari sebuah keluarga miskin yang punya anak 10
- setelah dua di antaranya mati. Bapaknya sopir oplet yang kini
suka sakit-sakitan. Ibunya "bisanya ya membantu masak kalau
tetangga lagi ada perkawinan atau sunatan."
Karirnya sebagai pengecer barangkali tak teramat istimewa bagi
seorang pemuda yang dibesarkan dalarn rumah tangga yang seret
penghasilannya. Ia tinggal di Paseban Timur, tak jauh dari
Universitas Indonesia. Di daerah ini lebih dari 100 anak
tanggung dan remaja bekerja menjajakan koran. Ada yang masih
meneruskan sekolah, yang cuma bisa jadi pengecer untuk koran
sore. Ada yang dari pagi hingga senja bekerja di bidang ini.
Urip sendiri sudah sejak masih di kelas VI SD jadi pengecer.
Gengsi
Sejak kecil itu ia berjalan dari Salemba ke Senen, terus ke
Pejambon dan ke Lapangan Banteng pulang-pergi, hampir tiap hari.
Dan ini berlanjut terus sampai ia menginjak SMP Begitu ia sampai
ke tingkat SMA, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang barangkali
bisa disebut gengsi. Ia malu untuk jadi pengecer koran terus.
Tapi keluarganya? Ongkos sekolahnya? Pembayaran buku
pelajarannya'? "Pulang ke rumah kalau masih ada nasi saja sudah
sukur," kata Urip mengenangkan masa itu. "Belum lagi kalau saya
melihat adik-adik saya di rumah. Saya jadi merasa serba salah."
Akhirnya ia mengambil keputusan: ia tak bisa bersekolah lagi.
"Sejak tahun 1974 itulah saya kembali lagi jual koran sampai
sekarang."
Itu pun dengan setengah hati. Ia tak mau berjualan koran di pagi
hari. Ia memilih jadi pengecer sore, dengan koran sore. "Habis
saya malu ketemu kawan-kawan. Kalau pagi berjualan rasanya
seperti penganggur saja." Bagi Urip nampaknya definisi bekerja
bukanlah menjadi pengecer.
Agaknya itu juga disebabkan karena ia melihat bahwa kaca-kaca
mobil kadang mendadak ditutupkan -- seperti takut ditodong -
bila pengecer koran mendekat ke kendaraan mengkilap yang
berhenti di perampatan. Atau barangkali karena ia juga melihat:
polisi sering mengejar-ngejar para pengecer.
Beberapa waktu yang lalu memang pernah ada diumumkan, bahwa para
pengecer koran dilarang berdagang di sekitar lampu
lalu-lintas--mungkin untuk menjaga kelancaran mobil-mobil. Dan
polisi pun sering bertindak melaksanakan larangan itu. Kata
Urip: "Yang tertangkap satu kali disekap sehari di kantor
polisi. Yang tertangkap dua kali disekap tiga hari. Dan kalau
sampai tertangkap untuk ketiga kalinya, akan ditransmigrasikan."
Urip tidak pernah ditangkap, tapi ia takut
ditransmigrasikan--meskipun ancaman "transmigrasi" itu mungkin
cuma main-main dan belakangan ini polisi toh sudah jarang
mengejar-ngejar pengecer. "Saya masih bisa bekerja di sini,"
kata Urip.
Tentu saja dengan harapan, bahwa barang dagangannya -- yang tak
lain adalah hasil karya jurnalistik Indonesia yang "merdeka dan
bertanggungjawab" -- akan bisa lancar beredar. Biasanya tiap
hari ia membawa 20 sampai 50 lembar koran, yang dibawanya
keliling di sekitar Salemba. Untuk Sinar Harapan ia bisa
mendapat keunturlgan Rp 20 sampai Rp 50 per lembar. Untuk Pos
Sore untungnya Rp 10. "Sekarang ini saya sedang merasakan
bagaimana sedihnya jadi penganggur," kata Urip.
MUHIDIN, pengecer koran umur 14 tahun, agaknya calon manusia
Indonesia yang bisa bersyukur. Anak ini merasa berbahagia dengan
hasil pekerjaannya setahun ini. Ketika ia datang dari Pekalongan
- setelah membolos dari ujian madrasah terakhir -- ia cuma punya
pakaian satu stel. Kini sudah 5 stel, dan "bagus-bagus,"
katanya.
Sebagai orang yang bersyukur, ia tak pernah mengeluh. Juga bila
hujan turun dan koran tak laku. "Kalau hujan ya berteduh," kata
Muhidin. "Semua tergantung nasib," tambahnya.
Bagi Muhidin semuanya pun tergantung nasib ketika beberapa koran
yang dijualnya ternyata dilarang terbit. Ia mengaku tak merasa
sedih atas pembreidelan itu. Baginya keuntungan yang
diperolehnya setiap hari sudah membahagiakan. Memang ia
terpukul, tapi tak teramat dirasakannya. "Kalau biasanya saya
pulang sampai jam 10 malam, sekarang jam 6 sore sudah bisa
pulang."
Tiap pagi, kecuali hari Minggu, dari jam 7 ia sudah mengambil
jatah koran di Dukuh Atas, dari rumah seorang agen. Setumpuk
koran (sekitar 50 sampai 75 lembar) dari pelbagai penerbitan
dibawanya ke arah perempatan Cik Di Tiro dengan Jalan
Diponegoro. Jarak ini tak terlalu jauh, sekitar 4 kilo. Jarak
yang rutin.
"Cukong"
Ia masih punya ayah, ibu dan seorang adik yang masih bersekolah
di SD kelas II - hanya mereka jauh ditinggalkannya di
Pekalongan. Setahun yang lalu Muhidin datang ke Jakarta, dengan
maksud mau mencoba nasib di sini selama tiga bulan. Rupanya ia
senang. "Saya senang di Jakarta, kumpul sama teman-teman dan
pegang duit," katanya. Padahal mulanya ia merasa ngeri tinggal
di kota seramai ini - takut dilanggar kendaraan. Dan ia meman
peMah mengalami sekali: ketubruk sepeda ... "Di Jakarta malah
ketubruk sepeda," katanya sendiri sambil ketawa.
Ia tinggal di sebuah rumah di daerah Jalan Setiabudi, berkumpul
bersama 10 temannya. Mereka satu serikat. Yang menyediakan
tempat adalah seorang "cukong", yang rupanya punya ide beramal
secara diam-diam memberi anak-anak itu sebuah sumber
penghasilan. Muhidin misalnya, mendapat uang Rp 1000 dari
padanya, untuk beli koran, dan sore hari uang itu dapat
dipulangkan setelah koran laku.
Tiap hari ia mengatakan bisa menabung sampai Rp 500. Setiap
bulan uang itu dibawanya pulang ke Pekalongan untuk diserahkan
pada orang tuanya. Ia bangga dengan hasil kerjanya itu. Meskipun
kadang ia merasa iri bila ketemu adiknya yang masih bersekolah
atau bila melihat temannya yang menyandang buku. "Saya pingin
sekolah lagi," kata Muhidin, "tapi ya tidak mampu."
"Bapak saya tidak bekerja. Ia hanya seorang buruh tani. Emak
saya berjualan. Tapi keluarga saya miskin makanya saya disuruh
berhenti sekolah dan disuruh cari duit." Di hari pertama di
Jakarta ia mulai berjualan permen, karena bantuan seorang kawan
sekampung. Kemudian, setelah mengetahui bahwa berjualan sinar
Harapan bisa lebih menguntungkan, ia ganti usaha.
Permulaan selalu tidak mudah. Misalnya, ia harus tahu bagaimana
mendapatkan tempat berjualan yang strategis, tanpa perkelahian.
Sebab sekali ia kena pukul para pengecer lain, hingga anak 14
tahun yang pemalu ini pun menyingkir begitu saja, karena "saya
tak berani berkelahi."
Sebenarnya bekas murid madrasah yang putus belajar ini kepingin
jadi seorang kiyai. Sampai sekarang pun Muhidin tetap mengaji di
rumah. Cuma ia tidak bersembahyang selama waktunya disita oleh
kesibukan berjualan. Juga di hari Jum'at ia tak pernah sempat ke
mesjid. Tentang ini, dengan mukanya yang mengkilap dan sudah
mulai ditumbuhi jerawat kecil, Muhidin rupanya merasa malu. Tapi
ia tak mampu berbuat lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini