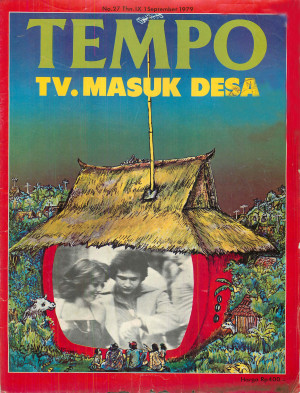TANAH garapan mendadak harus diperciut. Tentu saja para
penggarap di Jember tidak dapat menerima beitu saja. Sebab
tanah tersebut mereka peroleh seeara turun-temurun.
Perkebunan Tembakau PTP XXVII Jember dibuka sejak 1918 oleh NV
Lanbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD). Sebagian dibuka
sndiri oleh perusahaan kolonial tersebut dan selebihnya
dikerjakan dengan semacam kerja paksa oleh rakyat. LMOD
mengambil tenaga kerja dari Madura. Dengan bujukan dan janji
muluk-muluk orang Madura dipaksa membuka hutan dengan tenaga dan
biaya sendiri.
Setelah membuka hutan merekapun dipaksa pula menanam tembakau
pada muslm tertentu. Semua hasil panen, kecuali palawija sebagai
selingan, diharuskan dijual kepada perkebunan. Di samping itu
mereka masih pula dipungut pajak tanah (in natura) sebanyak 450
kg padi kering/hektar/tahun.
Demikian sejarahnya nenek moyang para penggarap perkebunan
tembakau Jember memperoleh haknya.
Tapi April 1978, Direksi PTP mengatakan pematokan-pematokan
dalam rangka apa yang disebut heregestrasi dan berkaveling
Setiap patok tanah luasnya hanya boleh 0,3 hektar. Setelah
pematokan selesai, menurut Direksi, akan disusul dengan
pencabutan hak garap seluruh penggarap dan seterusnya pemisahan
akan menentukan penggarap baru. Penggarap lama yang dianggap
patuh kepada peraturan perusahaan, masih akan menerima
masing-masing sepetak.
Tumpang Tindih
Para penggarap mempersengketakan hak turun-temurun mereka. Sebab
dari atau 3 hektar tanah yang semula mereka kuasai, tiba-tiba
harus menciut menjadi hanya 0,3 hektar saja. Padahal, seperti
kata Abdullah Eteng dari Komisi II/DPR, jika Undang-Undang
Agraria (UUPA) membatasi hak tanah, prinsipnya juga tidak boleh
memecah tanah pertanian yang sudah dalam batas minimun -- untuk
Jember, katanya, luas minimum itu 2 hektar.
Memang kisruh. Tapi sengketa tanah memang bukan barang baru di
sini. "Ini sebenarnya konflik yang kuno sekali," .kata ahli
sejarah Onghokham misalnya "antara penduduk di dekat hutan
negara dengan negara." Petani merasa hutan adalah haknya.
Sedangkan negara merasa memilikinya. Pelanggaran selalu saja
ada. Dalam zaman penjajahan pernah ada sekitar 5 ribu kasus
dalam suatu tahun.
Lalu, di zaman sekarang, apa kabar Undang-Undang Pokok Agraria?
Memang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti kata Direktur
Jenderal Agraria Daryono SH, kepada Harian Berita Baila.
Pengaturan tanah belum beres. "Masih tumpang-titdih," ujar
Daryono. Sedangkan kebijaksanaan pemerintah mengurusinya menurut
Dr. Soerjono Sukanto SEI, MA, Dosen Fak. Hukum UI, masih selalu
"bersifat ad-hoc atau sementara". UUPA, kata Soerjono, masih
perlu direvisi, selain memang banyak kelemahannya dalam
praktek."
Persengketaan tanah, begitu ditihat ahli hukum ini, banyak tidak
memilih peradilan sebagai lembaga untuk menyelesaikannya.
Sebabnya, antara lain, di samping perkara akan berjalan lama
juga memakan ongkos tidak sedikit. Apalagi, katarlya, bila
rakyat merasa akan memperoleh keadilan tanpa melalui pengadilan.
Cuma, ya itulah, kepastian hukum sering tak diperoleh sehingga
sengketa demi sengketa berlangsung terus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini