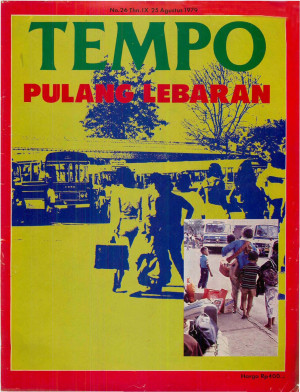DI Majalengka pernah terjadi peristiwa menggemparkan: Seorang
ayah, jagal kambing, dituduh menyembelih tiga orang anaknya yang
berumur 5 tahun, 3 tahun dan 9 bulan. Setelah itu dia berusaha
membunuh diri dengan menggorokkan golok ke lehernya sendiri.
Pengadilan berlangsung. Terdakwa menolak tuduhan dan bercerita.
Sebelum hari yang naas itu dia memang dalam keadaan bingung.
Hutangnya banyak. Di antaranya kepada seorang bernama AM yang
selalu menyuruh menantunya, seorang anggota Polri, menagihnya.
Sore itu ia membenahi alat-alat jagalnya. Lalu sore-sore, baru
jam 18.30, dia sudah masuk tidur. Tapi tiba-tiba dia merasa
berada di tempat pemotongan kambing. Di situ, katanya, dia
menyembelih 4 ekor kambing. Ketika sedang menyiangi kulit
kambing muncullah AM menagih hutangnya. AM seperti biasanya
marah-marah. Lalu, katanya, merebut pisau dari tangannya dan
langsung menebas lehernya. Tukang jagal merasa dirinya mati.
Tahu-tahu, dia terbangun di rumahsakit, dengan leher terasa
sakit.
Hakim Jua
Peristiwa jagal kambing tersebut terjadi 1975. Seorang
psikiater, dr. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman tampil di
pengadilan sebagai saksi ahii. Setelah melalui pemeriksaan yang
lama dr Hasan maju dengan kesaksiannya: terdakwa adalah
penderita penyakit epilepsi tipe psikomotor. Yaitu, kompleks
gejala-gejala perubahan kesadaran berkala, yang diikuti gerakan
kejang-kejang atau gangguan perasaan dan tingkah-laku atau
kedua-duanya.
Penyakit demikian banyak diderita orang. Bahkan orang seterkenal
Newton, Beethoven, Napoleon sampai Alfred Nobel. Kemungkinan
pembunuhan terhadap ketiga anaknya dilakukan terdakwa dalam
keadaan penyakitnya kumat: dalam ilusinya dia tengah menyembelih
kambing dan melihat AM menagih hutang dalam halusinasinya.
Kesaksian ahli penyakit jiwa itu ternyata ditolak hakim. Seorang
yang mengerjakan sesuatu perbuatan, karena kurang sempurna
akalnya atau berubah akal, memang tidak boleh dihukum (KUHP
pasal 44). Tapi, begitu pendapat hakim, terdakwa yang jagal
kambing itu tak menunjukkan gejala demikian. Nyatanya, katanya,
terdakwa sebelumnya berjualan daging dengan baik. Dia bukan
orang berfikiran terbelakang sungguhpun barangkali tidak cerdas,
dengan ukuran IQ 80. Pokoknya, menurut hakim, terdakwa tidak
menunjukkan sakit gila atau sebangsanya.
Begitulah. "Memang bagi psikiater pasal 44 KUHP itu sudah tidak
memuaskan lagi," kata dr Hasan yang mendapat brevet keahlian
ilmu kedokteran jiwa sejak 1964 itu. Pasal tersebut, kalau di
Negeri Belanda adalah pasal 37, disahkan dan berlaku sejak 1881
berdasarkan keadaan psikiatri abad XIX. Namun sejak 1928 di
Belanda sendiri pasal tersebut sudah mendapat berbagai perubahan
sesuai dengan kemajuan pandangan psikiatri. Lahirlah
Undang-Undang Psikopat. Undang-undang macam itulah yang belum
ada di Indonesia hingga sekarang. "Sekiranya Undang-undang
Psikopat sudah ada," menurut dokter yang pernah mengecap
pendidikan ilmu hukum ini, "masalah kejahatan yang dilakukan
penderita epilepsi dapat dipecahkan .... "
Beruntung terdakwa kemudian dibebaskan dari tuduhan membunuh
anaknya sendiri. Itu bukan berkat kesaksian dr. Hasan. Tapi
berdasarkan pembuktian dan kesaksian lain -- tak dijelaskan
bagaimana.
Tidak hanya dalam kasus tukang jagal kambing dari Majalengka
saja. Saksi ahli memang sering ditampilkan ke ruang pengadilan.
Tapi keterangannya, menurut dr Hasan (62 tahun) ketika
dikukuhkan menjadi Guru Besar Univ. Pajajaran di Bandung Juli
lalu (judul pidato ilmiahnya "Psikiatri Hari Ini dan Besok"),
tak banyak artinya. Vonis hakim berjatuhan tanpa mengindahkan
keterangan ahli psikiatri kehakiman. "Padahal kami telah
melakukan pemeriksaan 400 sampai 450 jam," ujar dr Hasan.
"Akhirnya hakim sendiri yang menentukan si terdakwa itu sakit
atau sehat."
Sudah Usang
Masalah yang menjadi duri dalam daging bagi psikiater khususnya,
ahli kedokteran kehakiman umumnya, menurut dr Hasan Basri Saanin
adalah kedudukan saksi di depan pengadilan seperti tersebut di
atas. Hukum mengatur (sejak tahun 1848) keterangan dan pendapat
ahli hanya berguna sebagai keterangan bagi hakim. 'Yang mulia'
(hakim) sama sekali tidak wajib menuruti jika keterangan ahli
bertentangan dengan keyakinannya sendiri.
"Oleh sebab itu," kata Guru Besar baru Unpad itu, "untuk
sementara waktu yang mungkin sangat lama, kita harus puas dengan
pasal 44 KUHP yang ada, yang sudah usang itu, sungguhpun
perjuangan akan nasib psikopat kriminil ini sudah dimulai oleh
Prof. Slamet Iman Santoso sejak 1954." Dalam keadaan sekarang,
katanya lagi, sulit memperjuangkan kesaksian ahli dalam bentuk
visum et repertum mendapat kekuatan sebagai bukti.
Tambahan lagi, seperti di Bandung saat ini, menurut dr Hasan
tidak ada satu fakultas hukum pun yang memberikan kuliah
psikiatri kehakiman. Yurist atau ahli hukum muda sedikit atau
sama sekali tidak memiliki pengetahuan tersebut. "Suatu hal yang
sebenarnya tidak boleh terjadi di dunia modern." Akibatnya,
tugas para ahli kedokteran kehakiman hanya membuat visum atau
dipanggil ke pengadilan, hanya untuk memberikan kuliah saja..."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini