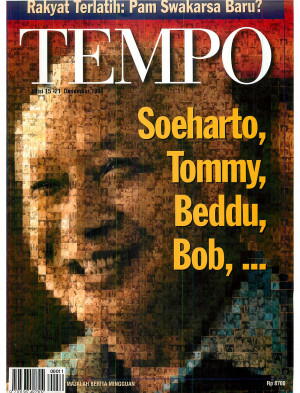Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak tahan serbuan bara, sebagian warga lalu mengungsi. "Mereka menyebar mencari penghidupan ke desa-desa yang jauh," kata Ding Kueng, Kepala Adat Matalibaq. Padahal, selama entah berapa generasi, mereka terjalin dalam ikatan primordial yang erat. Hampir semua penduduknya keturunan suku Dayak Bahau Telivaq dan beragama Katolik. Apa boleh buat, memang, akibat tragedi lingkungan tersebut, kehidupan Matalibaq yang penuh warna itu kini terasa hambar.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo