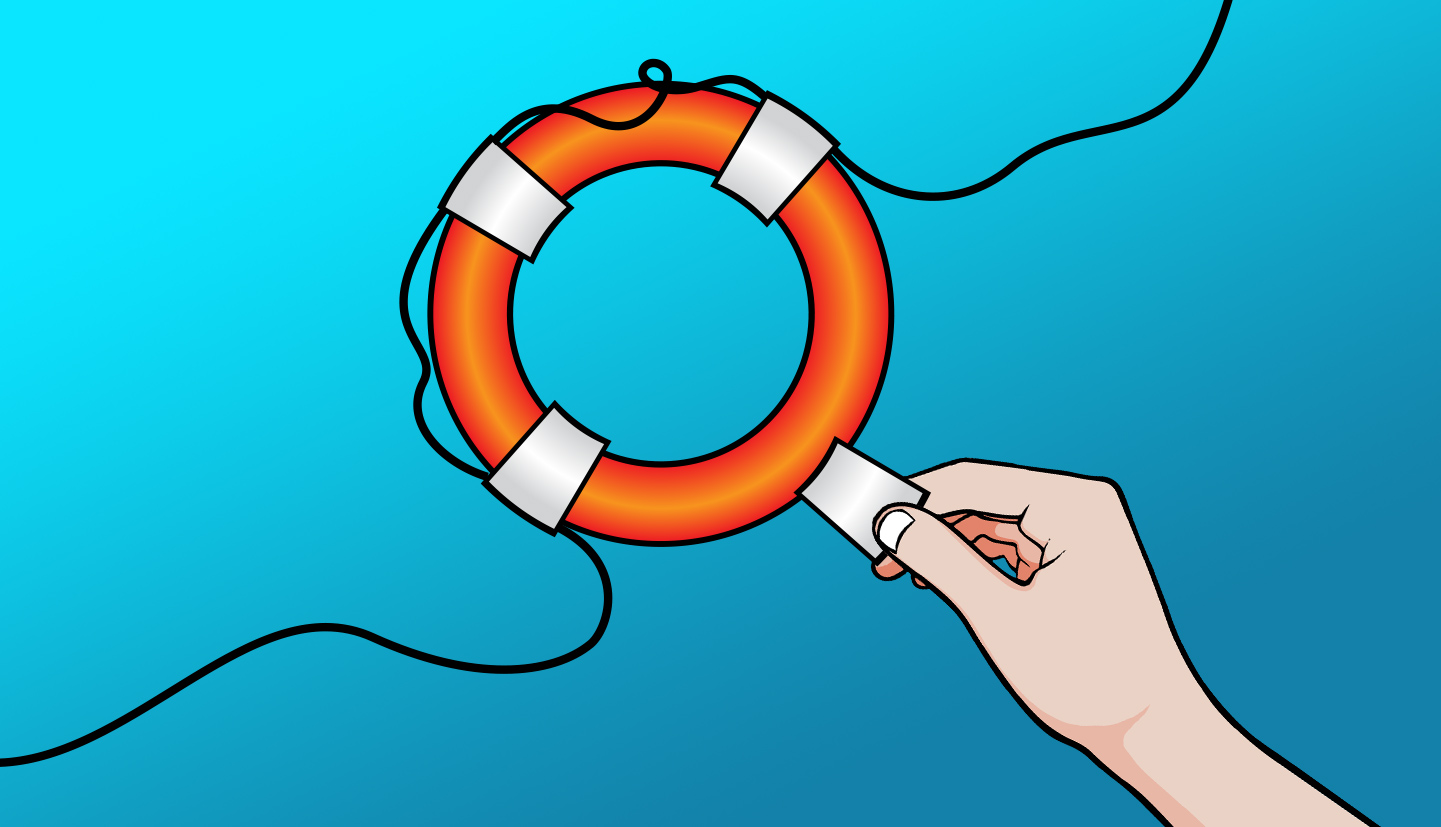Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setiap menjelang pemilihan umum, masalah golput atau golongan putih muncul kembali. Golput adalah gerakan informal yang menganjurkan masyarakat agar tidak memilih. Alasannya macam-macam.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo