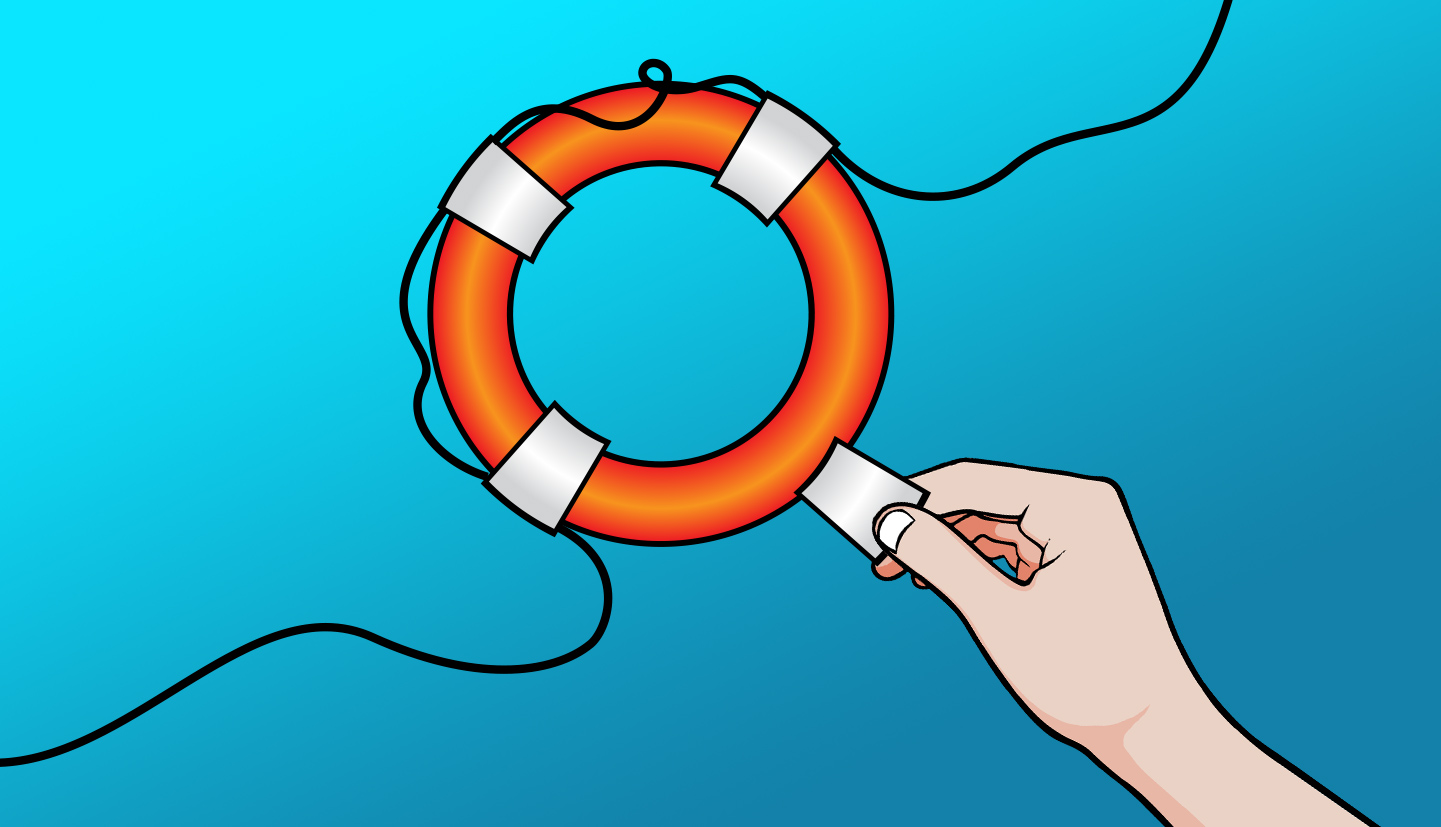Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Estimasi perolehan suara calon presiden melalui penghitungan cepat atau quick count menimbulkan ketidakpuasan di beberapa kalangan di Indonesia, baik politisi maupun peneliti. Ketidakpuasan itu rupa-rupanya muncul dari tidak tepatnya pengertian tentang perbedaan antara dua jenis estimasi yang dilakukan, sebelum pemilu presiden tahap satu dan sesudahnya. Yang satu adalah polling dan yang lain adalah penghitungan cepat. Dua jenis estimasi ini berbeda wataknya, yang kalau tidak disadari akan menimbulkan keberatan yang tidak perlu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo