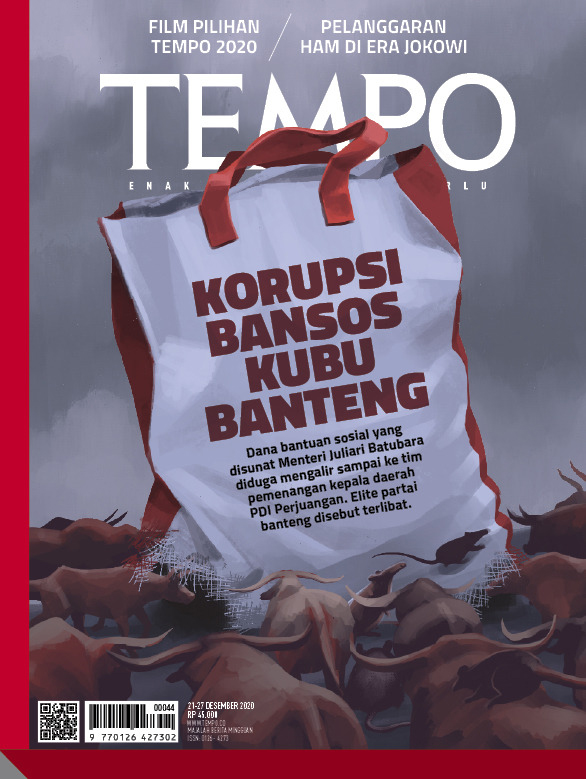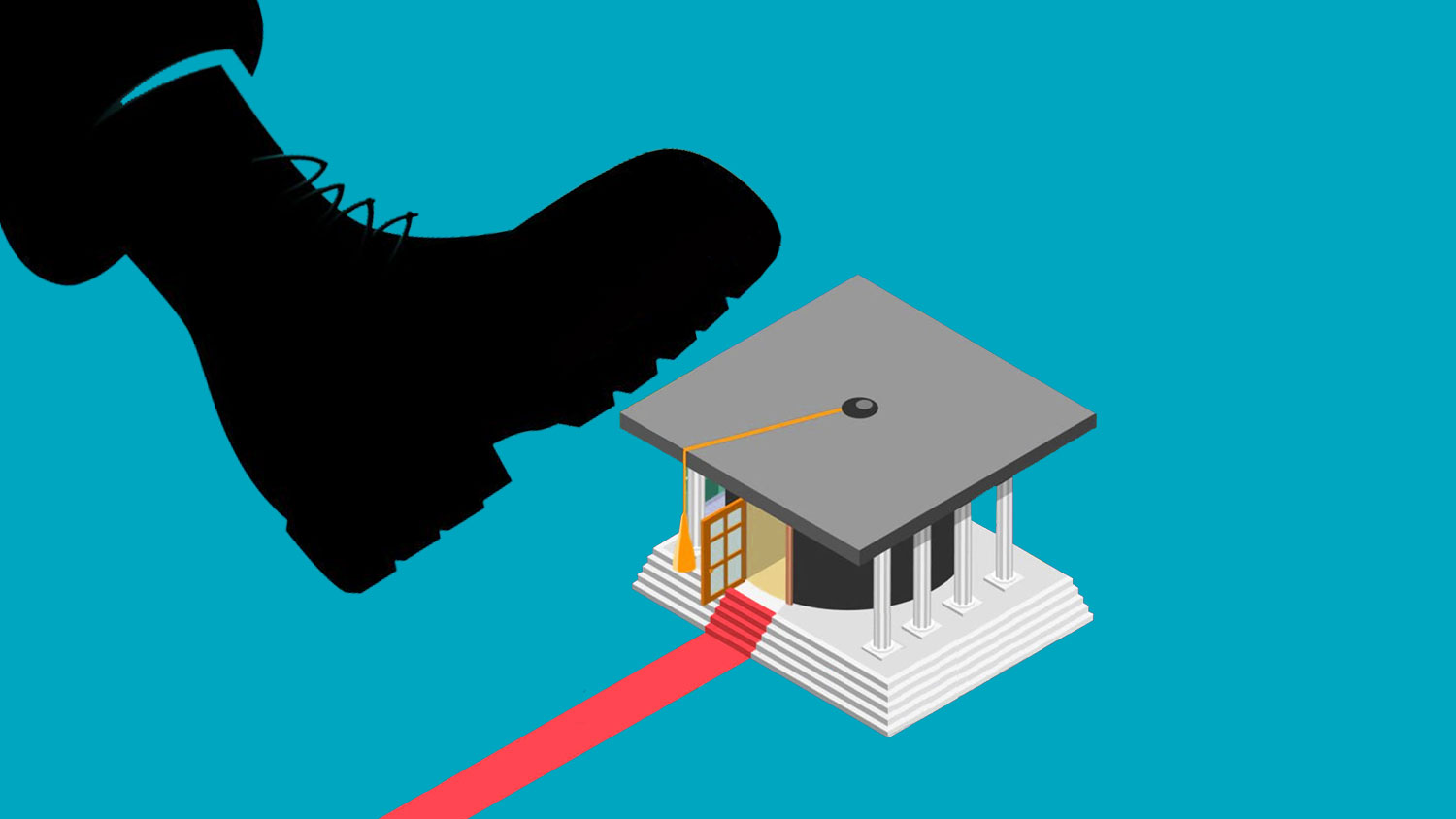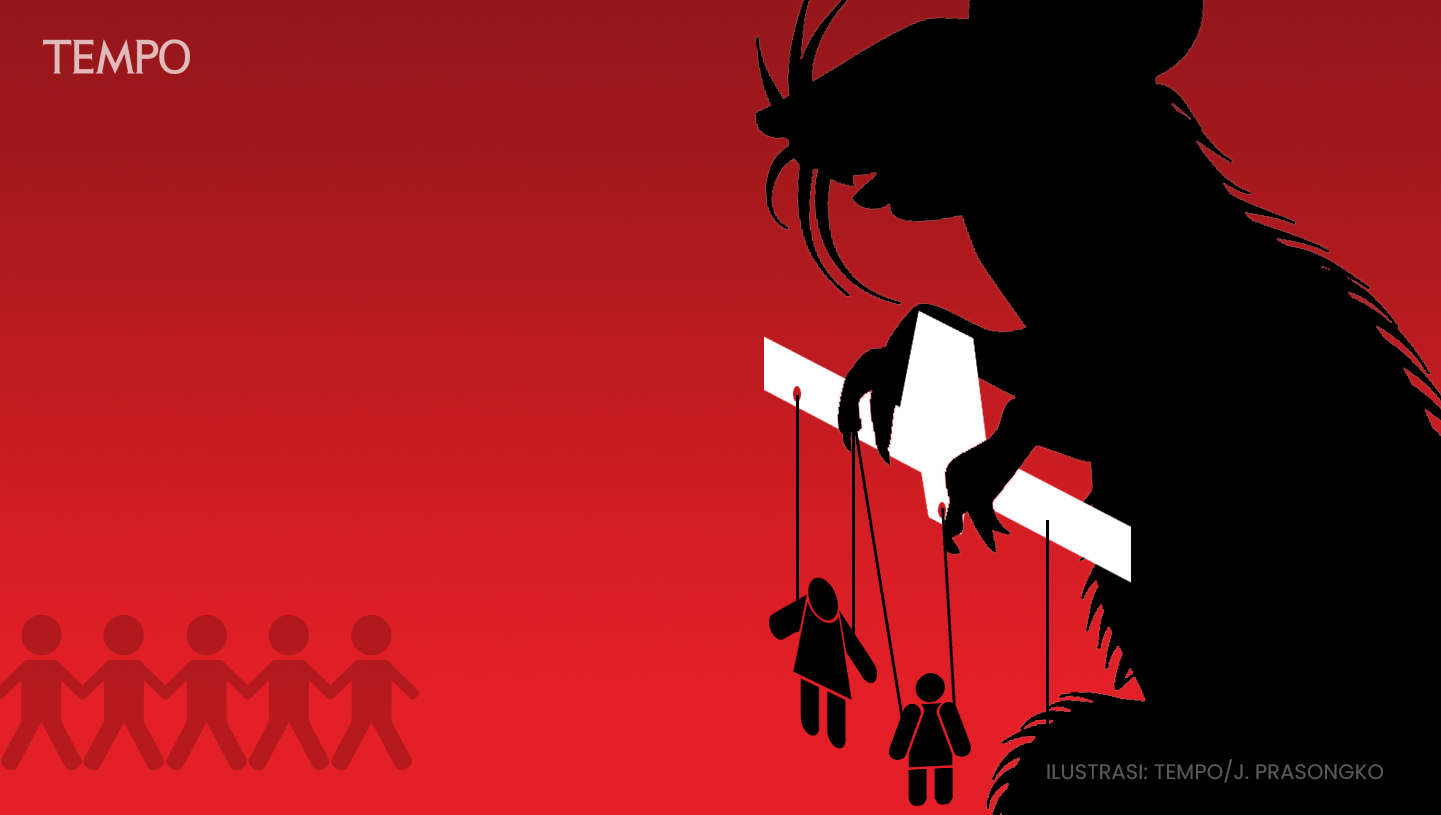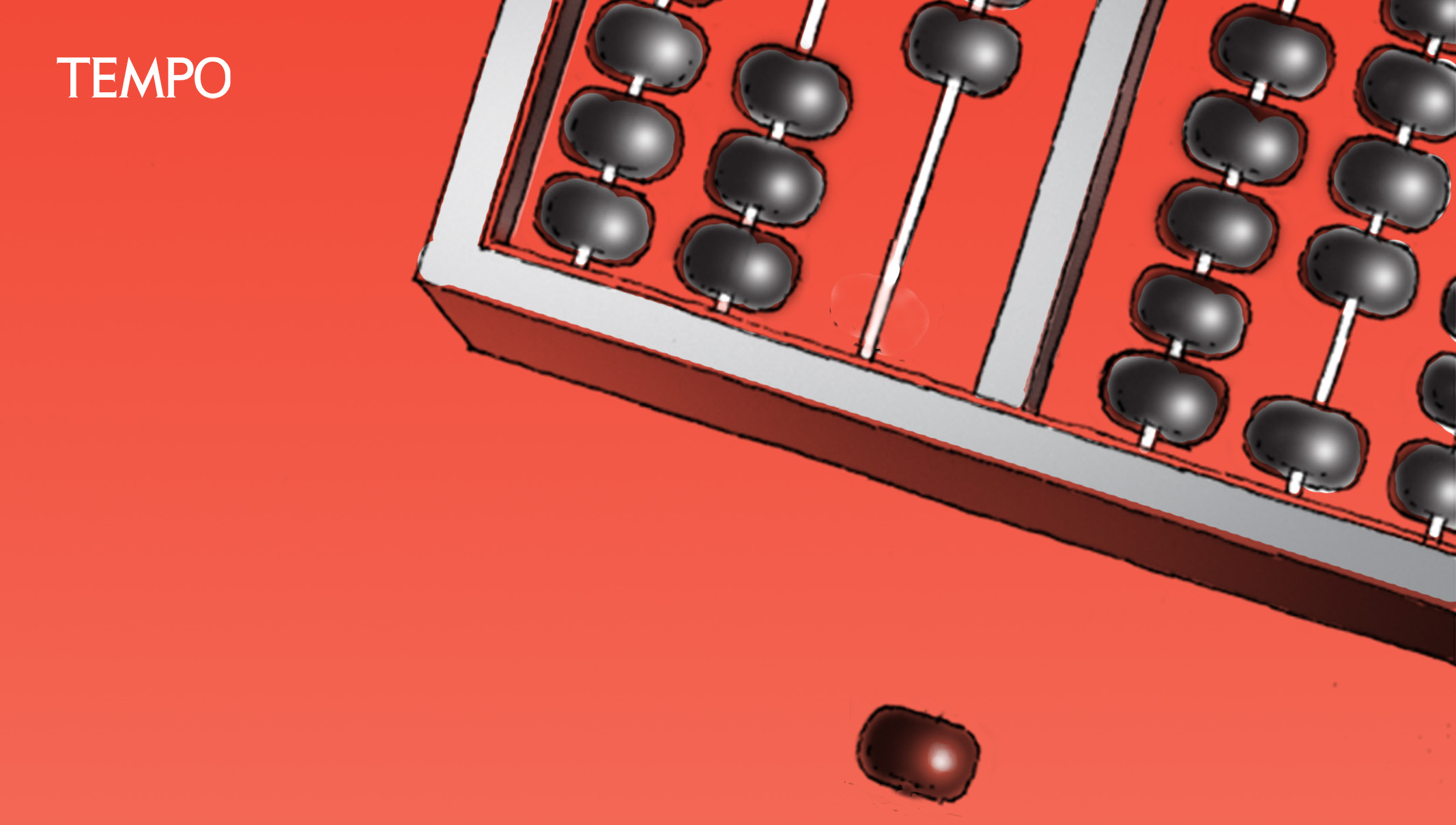Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

+ Njonja Santoso: Saja memang perlu hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo