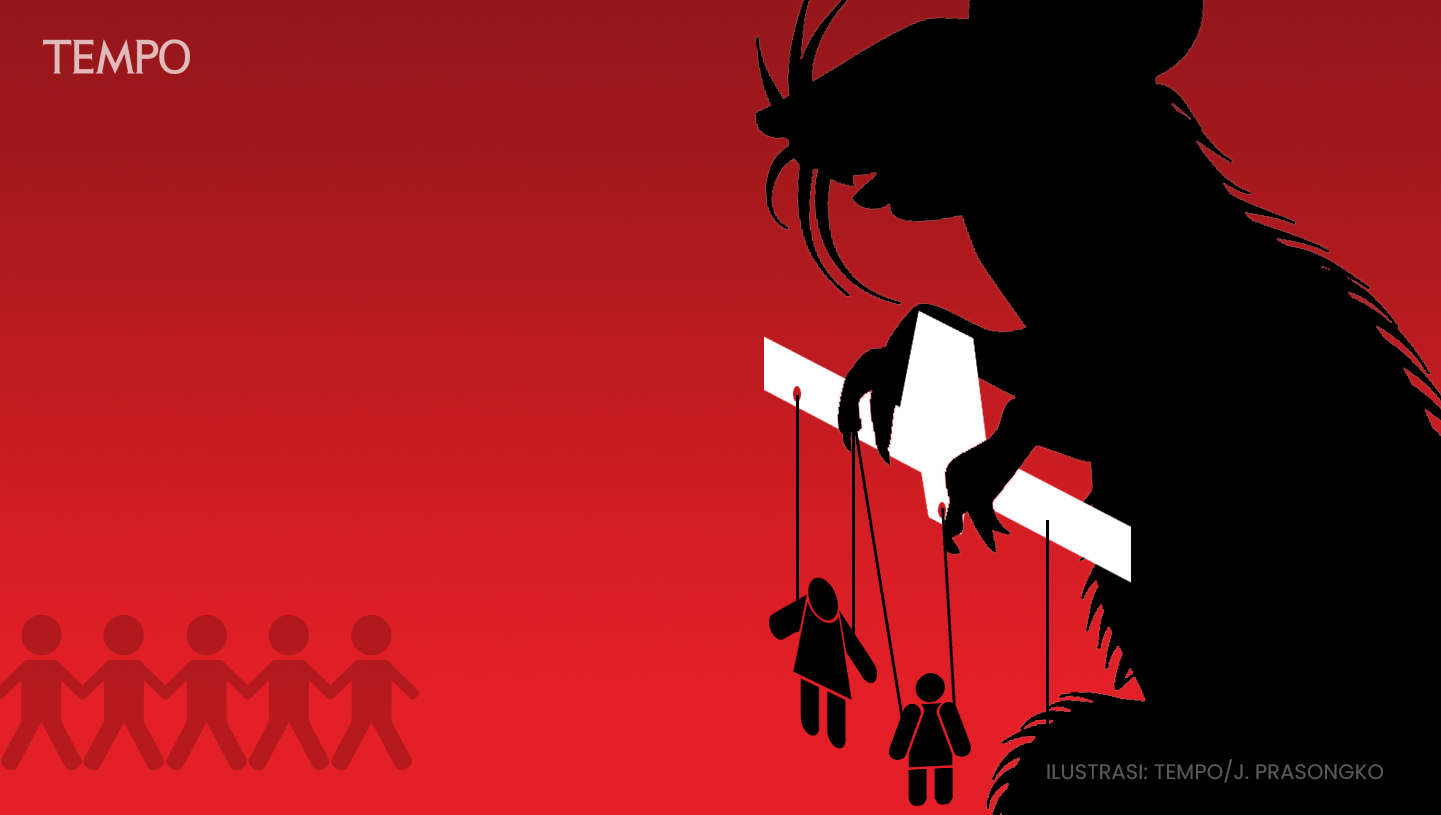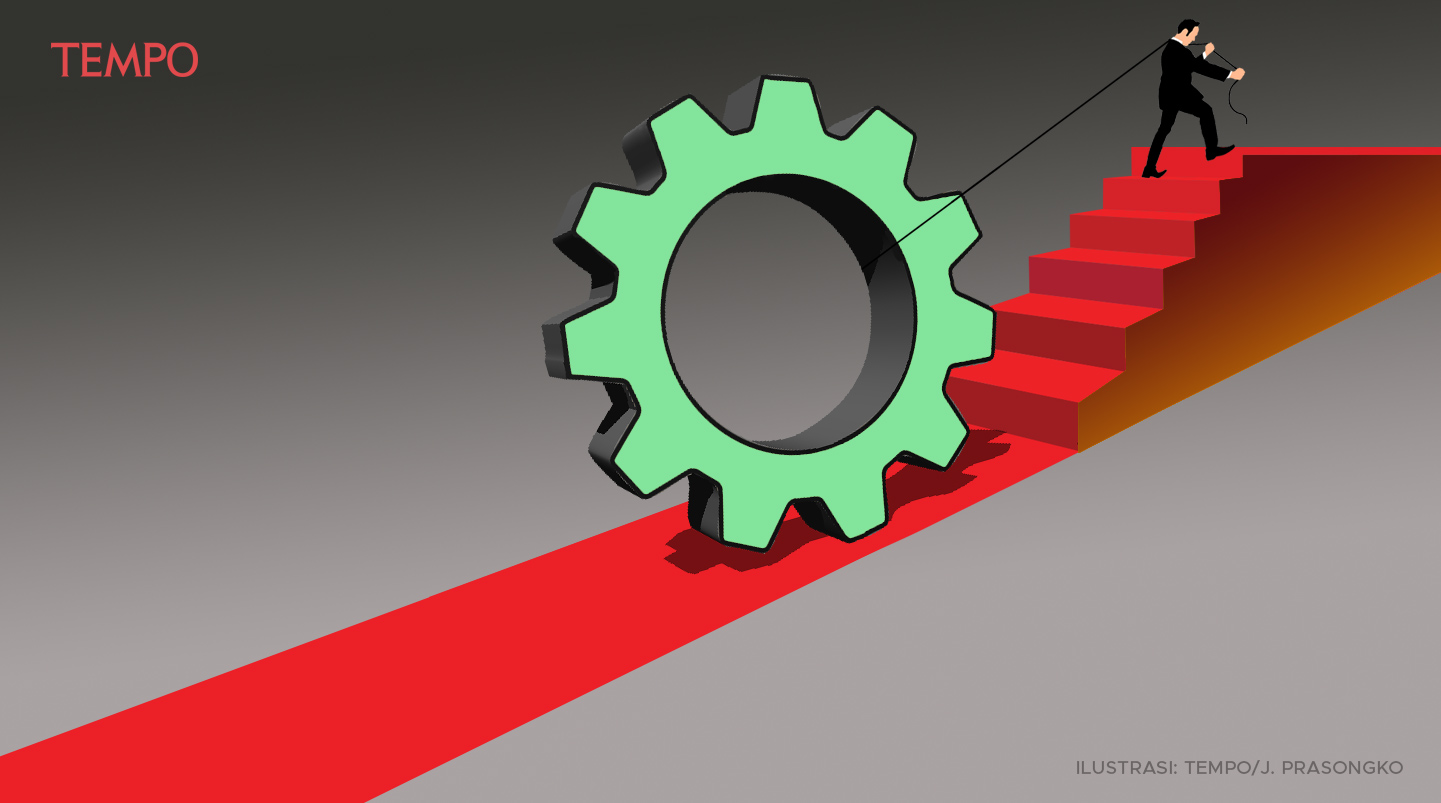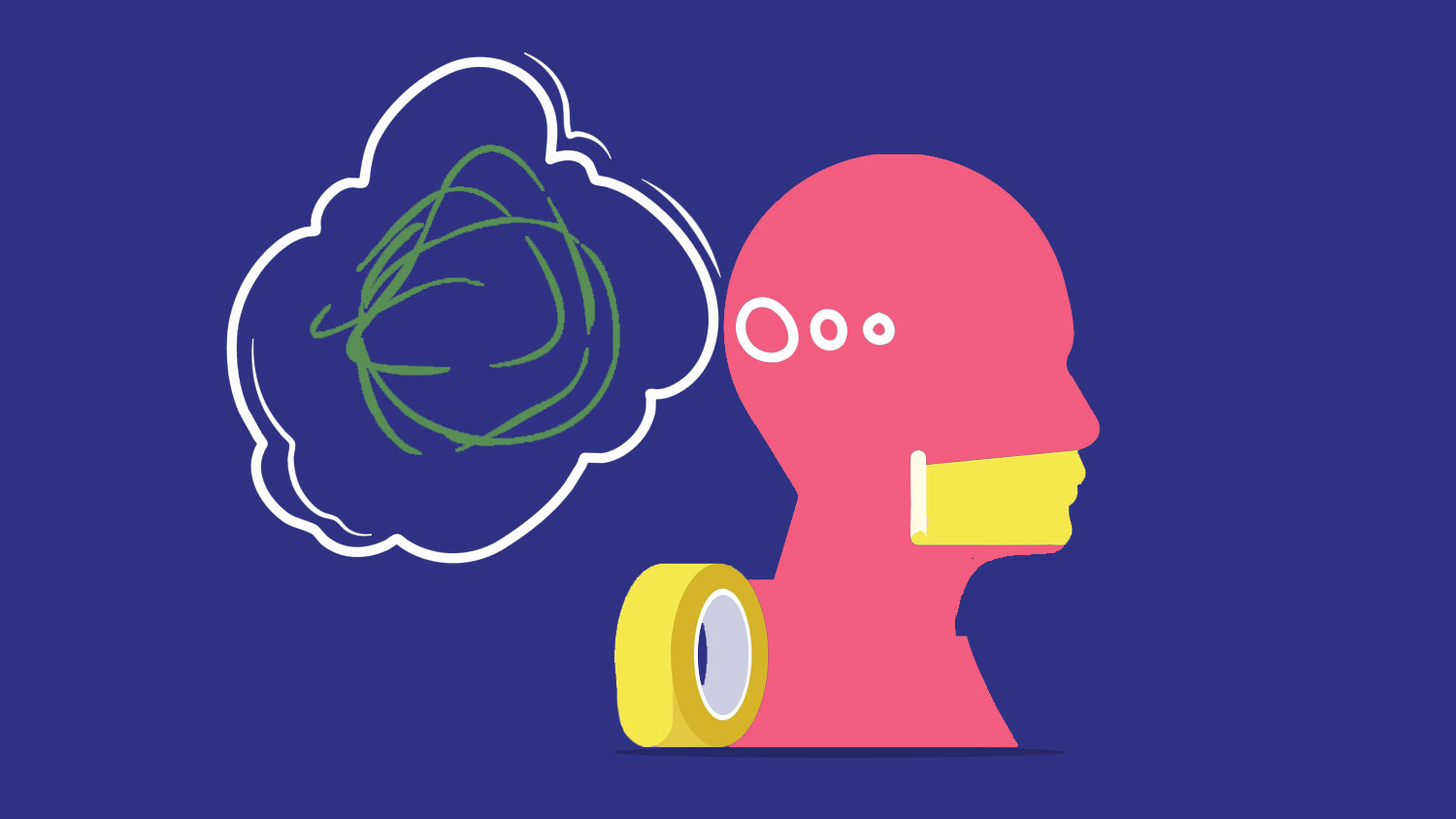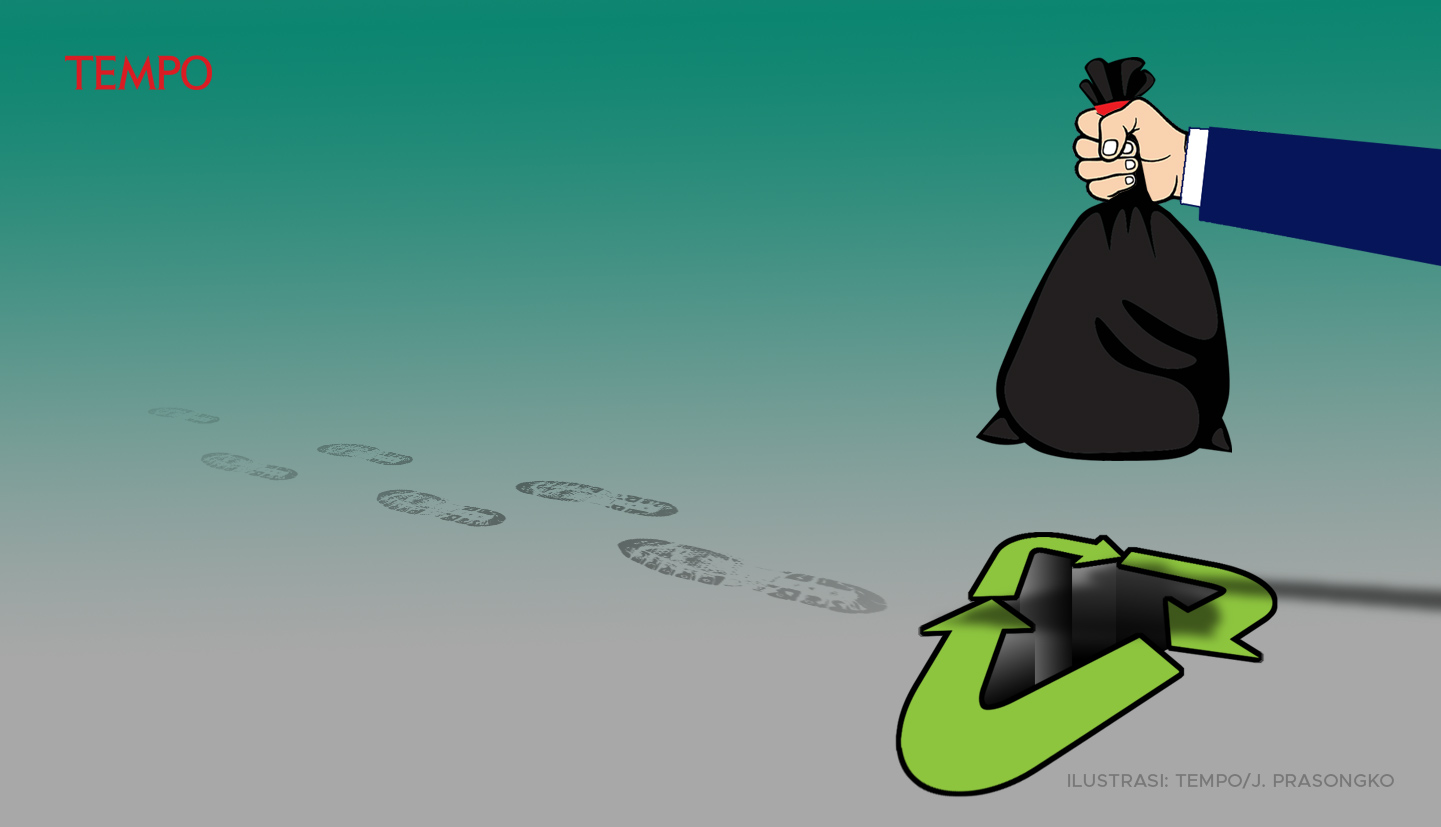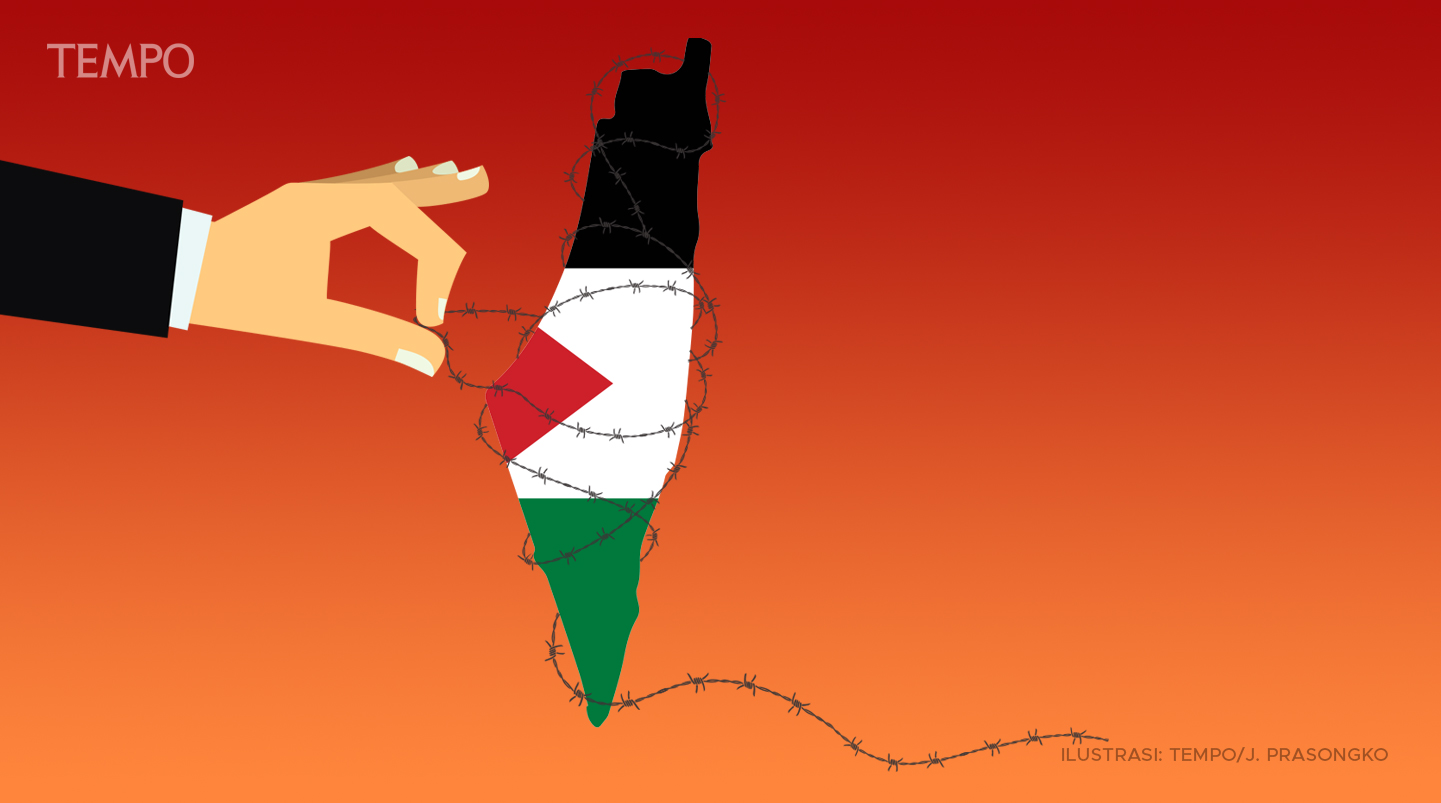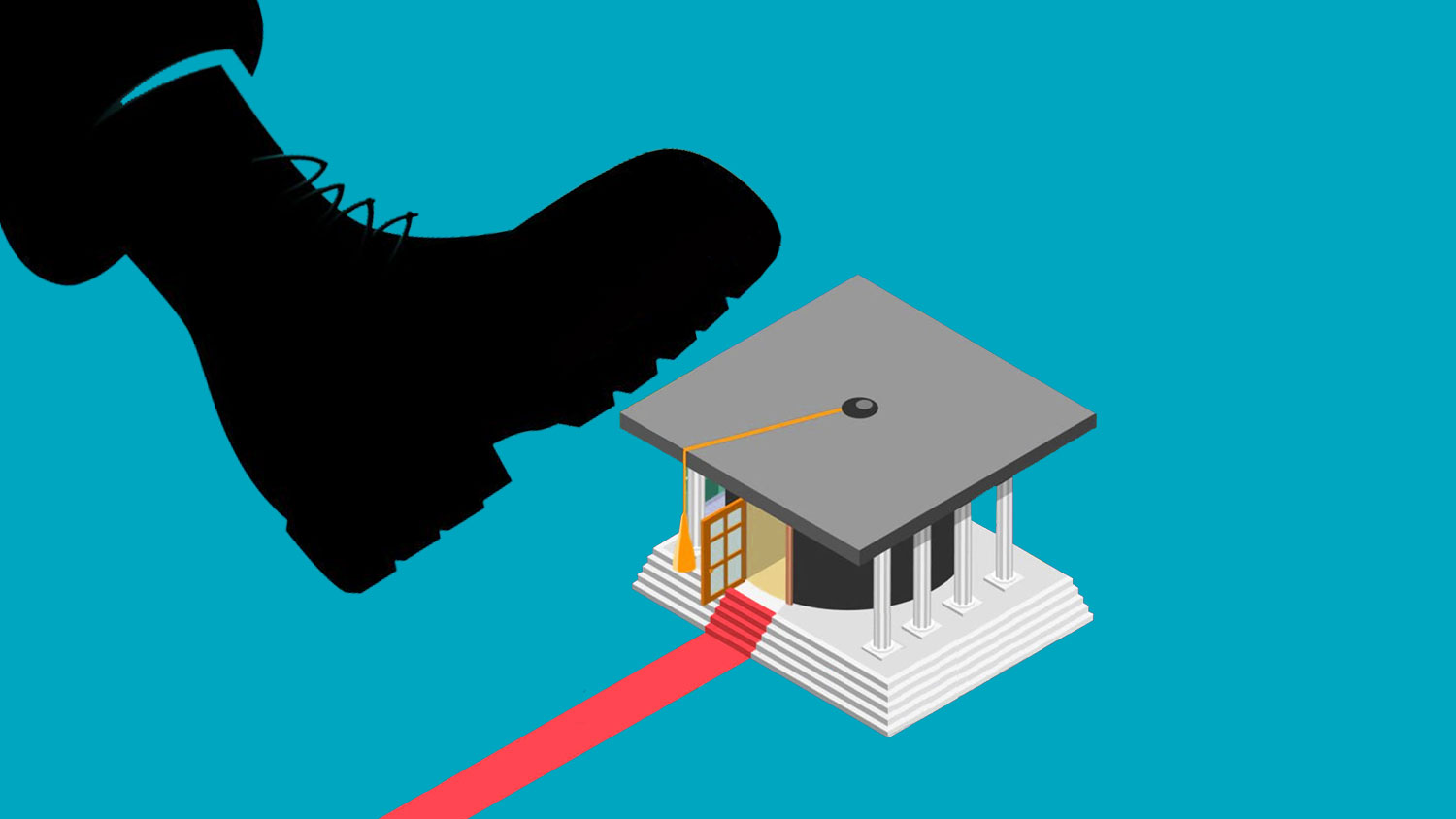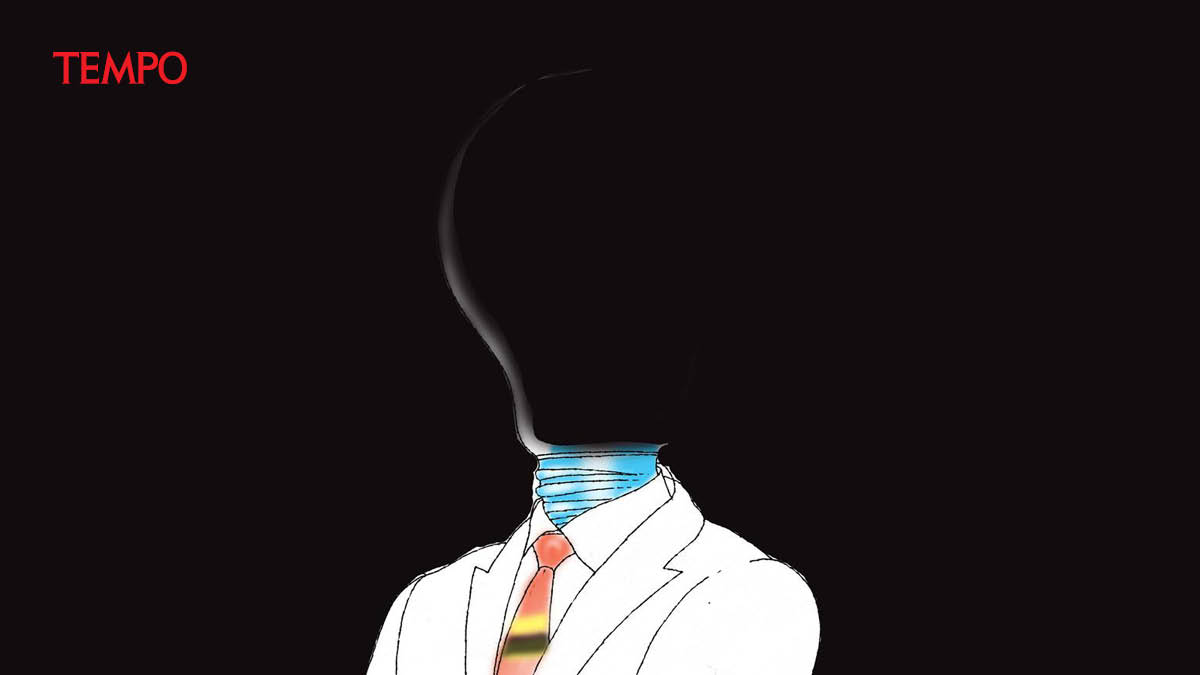Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ikhsan Yosarie
Peneliti Setara Institute for Democracy and Peace
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Perbedaan mendasar Orde Baru dan pasca-reformasi terletak pada relasi negara dan warga negara (civil society) yang berada di posisi seimbang dalam konteks politik. Pemerintah, selaku representasi negara, membuat kebijakan, sementara warga negara memiliki kebebasan untuk berkomentar dan memberi kritik, yang salah satu keluarannya berpotensi membatalkan atau mengubah kebijakan yang tengah dirancang oleh pemerintah. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa keseimbangan kekuatan politik tersebut bersifat positif dalam konteks negara demokrasi dan sebagai benteng atas potensi kembalinya otoritarianisme.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Gerakan masyarakat sipil yang masif akhir-akhir ini menyikapi pelbagai isu, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi cerminan bahwa demokratisasi tetap terjaga dan terus berlangsung. Gerakan masyarakat sipil menjadi salah satu upaya untuk menciptakan checks and balances dalam relasi negara-rakyat. Keseimbangan relasi ini harus terus dijaga karena jika salah satu pihak lebih kuat, implikasinya destruktif terhadap demokrasi.
Namun cara pandang pemerintah terhadap fenomena masifnya gerakan masyarakat sipil ini berpotensi menciptakan roh otoritarianisme dan melahirkan neo-otoritarianisme. Perbedaannya, sementara pada rezim Orde Baru pendekatan dan cara pandangnya adalah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, pada era neo-otoritarianisme, yang dilakukan bersifat lunak, yakni pendekatan dan cara pandang yang menganggap gerakan masyarakat sipil sebagai upaya perlawanan terhadap pemerintah sehingga pemerintah tidak boleh kalah. Cara pandang seperti ini berpotensi menimbulkan pengabaian dan delegitimasi aspirasi publik karena menganggap dan membenturkan pemerintah dengan masyarakat sipil.
Cara pemerintah merespons persoalan demikian memang belum memakai aspek-aspek kekerasan dan alat negara layaknya Orde Baru. Namun respons yang diberikan berupa praktik demokrasi prosedural karena nilai-nilai, norma, dan prinsip dasar demokrasi tidak terpenuhi, terutama pada aspek aspirasi dan partisipasi publik. Kualitas demokrasi turun pada zona ini.
Kedua pendekatan tersebut bertemu pada satu titik, yakni pengabaian terhadap aspirasi publik, baik dilakukan secara keras maupun lunak. Pada ujungnya, relasi yang tercipta mengarahkan negara menjadi Leviathan, seperti dalam bayangan Thomas Hobbes. Leviathan adalah sejenis makhluk raksasa penguasa lautan yang selalu mengancam keberadaan makhluk lain sehingga dia ditakuti dan perintahnya dituruti.
Pandangan yang menganggap gerakan masyarakat sipil tersebut sebagai bentuk perlawanan membuat persoalan mengerucut ke arah pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat sipil. Ini mengakibatkan sempitnya keluaran dan gengsi persoalan menjadi menang atau kalah, sehingga pemerintah beranggapan, jika kehendak sipil dituruti, itu artinya kekalahan. Padahal, dalam konteks demokrasi, gerakan masyarakat sipil tentu menjadi vitamin dan penyangga demokratisasi.
Perimbangan kekuatan negara dan sipil memunculkan sebuah konsolidasi antara negara dan masyarakat sipil yang melahirkan relasi positive-sum (Huntington, 1995). Perimbangan kekuatan itulah yang nantinya memungkinkan dijalankannya checks and balances atau pengawasan masyarakat sipil kepada pemerintah.
Lebih dari itu, dalam konteks elemen bernegara, gerakan masyarakat sipil juga menjadi penyeimbang antara pemerintah dan sektor swasta. Gerakan masyarakat sipil menjadi tameng untuk mencegah terjadinya kongkalikong di lingkup internal pemerintah, antara pemerintah dan sektor swasta, atau bahkan kuasa "pemodal-predatoris" yang implikasinya berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Melalui hal-hal demikian, peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial masyarakat sipil terpenuhi.
Apa yang dikhawatirkan Denny J.A. (2006) terjadi. Transisi politik pasca-Orde Baru merupakan transisi yang permanen dan tidak tuntas. Masa transisi ini memang tidak membawa kita mundur ke belakang, tapi tidak juga membawa kita maju ke depan untuk menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya.
Pelbagai manuver politik eksekutif dan legislatif menambah kerumitan dinamika politik yang sudah kusut. Revisi Undang-Undang KPK serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disepakati dan dibahas dalam waktu yang tidak jauh berbeda tanpa melibatkan partisipasi publik. Aspirasi dan partisipasi publik dipinggirkan untuk kepentingan-kepentingan para oligarki. Pada titik ini, kita dapat memahami bahwa praktik-praktik otoritarianisme dan demokrasi prosedural dilakukan untuk melancarkan kepentingan para oligarki kekuasaan ini. Dengan demikian, logislah bila gerakan masyarakat sipil itu harus ada dan terus ada.