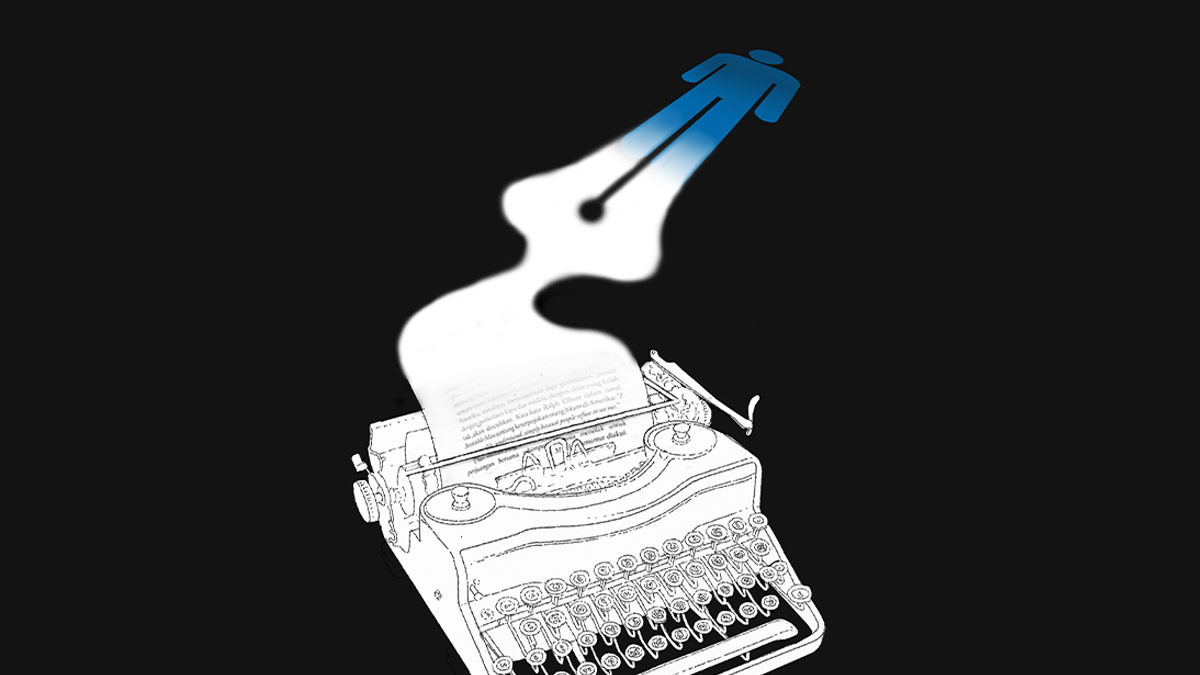Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

SUDAH lama saya tertarik pada soal kecil di toko-toko buku di negara-negara maju. Jika kita ke toko buku besar di London, seperti Waterstone (yang terbesar di Piccadilly Street dan Gower Street) dan Foyles di Charing Cross Road, atau serangkaian toko buku kecil di area Bloomsbury, kita tak akan menemukan rak “literary novel” atau “novel sastra”.
Kita akan menemukan karya-karya pemenang kusala Man Booker, Pulitzer, National Book Award, Orange (sekarang bernama Women’s Prize for Fiction), atau karangan para pemenang Nobel Sastra berada di rak “general fiction”. Sementara itu, novel-novel yang di dalam percakapan sastra kita biasa disebut “novel populer” atau “sastra populer” lazimnya ditempatkan di rak-rak novel bergenre tertentu. Misalnya novel-novel Agatha Christie dan P.D. James ada di rak novel “Thriller & Mystery” atau “Crime”.
Tentu ada rak untuk buku berkategori “Poetry”. Di rak buku puisi itu biasanya tak ada perbedaan antara buku puisi laris atau populer semacam karya-karya Rupi Kaur dan karya-karya kanon seperti puisi Emily Dickinson. Satu-satunya rak yang menyebut kata sepadan “sastra”, yakni “literary”, biasanya untuk rak buku nonfiksi “Literary Criticism” atau “Kritik Sastra”. Hal ini tampak juga di toko-toko buku seperti Shakespeare & Co. di Paris; toko-toko buku bekas di Chiang Mai, Thailand; Kinokuniya Tokyo dan Singapura; dan banyak lagi.
Pembedaan “sastra” dengan “bukan-sastra” rupanya lebih banyak dalam percakapan dan anggitan akademik atau kritik sastra. Itu pun, jika kita dalami, akan kita temukan misalnya kajian-kajian (ke-)sastra(-an) atau literary studies tentang novel-novel Agatha Christie yang dianggap bacaan populer. Dalam percakapan lebih luas, di dalam keseharian dan di media massa (dan kini di media sosial) serta penerbitan umum di Eropa dan Amerika Serikat, banyak pemikir dan penulis lebih berfokus pada ungkaian dan telaah tentang fiksi atau medium fiksi, seperti novel dan puisi.
Seiring dengan itu, saya juga berpikir soal kasus bahasa menarik seputar kata “sastra” ini. Ada pemberian apresiasi yang tinggi pada apa yang dianggap “sastra” ketimbang karya pustaka biasa. Salah satu dampaknya adalah pemberian status kultural dan kadang sosial yang begitu tinggi kepada para penulis “Sastra”. Kita menyebut mereka “sastrawan”. Di sini kasus bahasa lain menyergap perhatian saya lagi. Apa padanan kata “sastrawan” dalam bahasa lain? Kita, misalnya, biasa menyebut Gabriel García Márquez, Orhan Pamuk, dan Elena Ferrante sebagai “sastrawan”. Dalam bahasa Inggris, mereka lebih sering disebut sebagai “writer” atau “novelist” saja. Tak ada kata seperti “literary person”.
Untuk kasus seniman atau pengarang populer yang bekerja dengan medium bahasa, bahasa Inggris seakan-akan lebih lazim merujuk pada fungsi, bukan pada sebuah konsep abstrak. Sedangkan pemerian status istimewa, luhur, kepada “sastrawan” dalam bahasa Indonesia barangkali menyumbang pada kecenderungan diskursus publik yang lebih sering gaduh soal ad hominem, soal sesiapa, dalam ekosistem kesusastraan kita kini.
Sebetulnya ada banyak pembahasan berakar dari kata “sastra”, seperti tentang “kesusastraan”, “susastra”, dan “kesastraan”. Dalam penggunaan sehari-hari, kita sering salah kaprah mengartikan “kesusastraan” sebagai “perihal sastra”. Padahal, lebih tepat, “kesusastraan” adalah “perihal susastra”. Adapun perihal sastra, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebut “kesastraan”. Keterangan tambahan KBBI daring menyebutkan bahwa “kesastraan” lebih luas pengertiannya dari “kesusastraan”.
Sedangkan “susastra”, menurut KBBI daring, adalah “karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah sebagai sarananya sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi”.
Wah. Diam-diam, ada hierarki selain “sastra” dan “non-sastra”, yakni “sastra” dan “susastra”. Dalam pengertian demikian, apakah penulis seperti Rendra, Goenawan Mohamad, Ayu Utami, dan Eka Kurniawan, untuk menyebut beberapa, semestinya disebut “susastrawan”? Lalu siapa saja “sastrawan” kita? Siapa saja pengarang dan penyair yang bukan “sastrawan”?
Kepusingan ini sebetulnya bermuara pada semacam dambaan untuk mengurangi hasrat membuat hierarki dalam wacana tentang sastra Indonesia. Mempertahankan cara pikir “sastra” dan “bukan-sastra”, juga “sastrawan” dan “bukan-sastrawan”, hemat saya adalah sebuah kegagalan kategoris yang perlu diobati. Kita abai berpikir tentang bagaimana meningkatkan capaian-capaian para “penulis”, “novelis”, “cerpenis”, “penyair”, “dramawan”, “memoaris”, dan “esais”.
Keluhungan, toh, acap tidak diperlukan dalam penyusunan rak buku atau dalam mencapai sesuatu seperti “mutu”. Ia malah bisa jadi hambatan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo