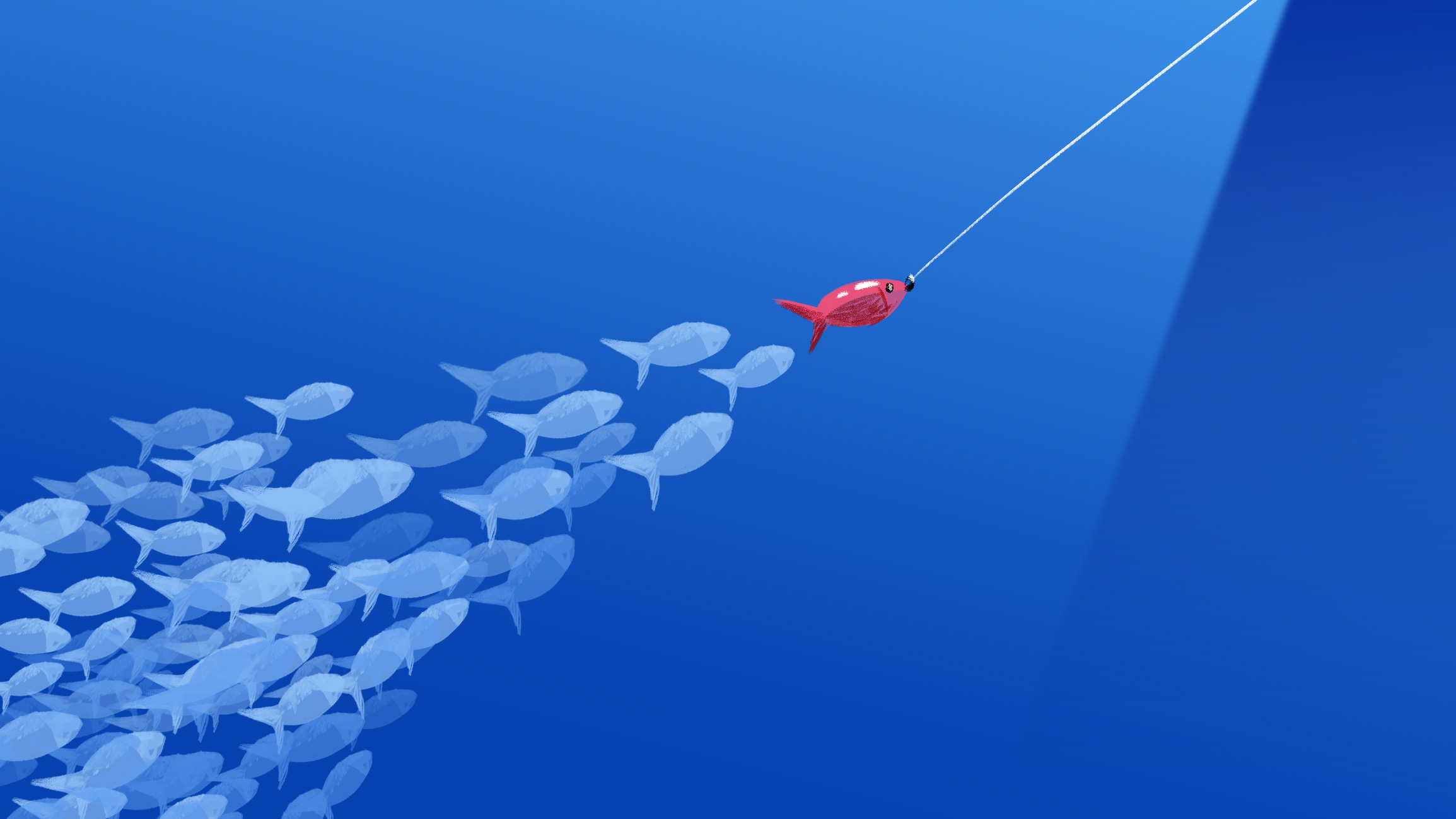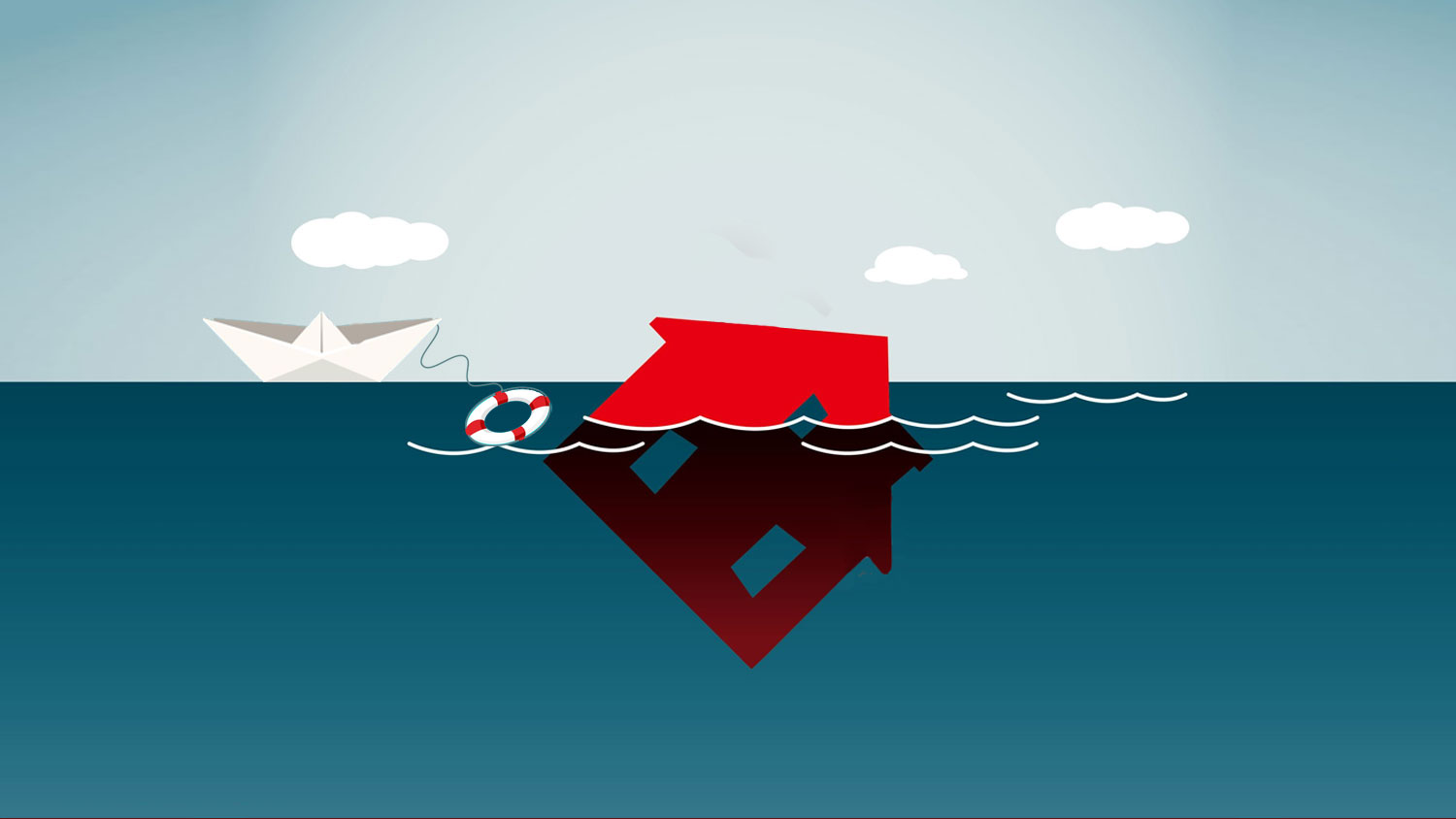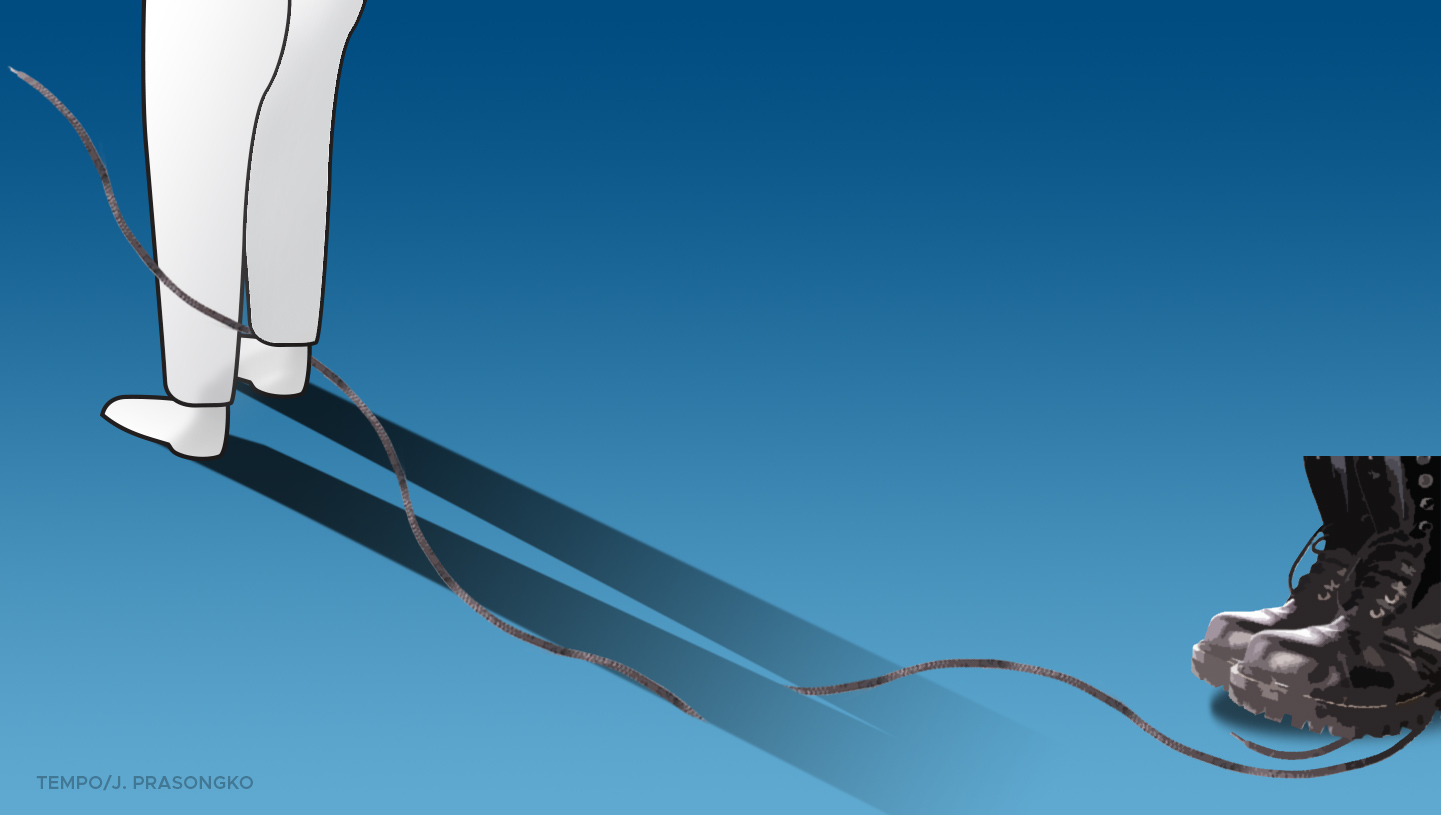Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BUKU Tyrant: Shakespeare on Politics (2019) menarik perhatian di antara karya-karya brilian profesor Harvard yang menempati rak-rak buku di Harvard Coop, Harvard Square, Amerika Serikat. Stephen Greenblatt, penulisnya, mengajar mata kuliah Shakespeare di Harvard University. Meskipun hidup lima abad silam, Shakespeare tetap menarik diperbincangkan kembali bukan sebagai pengagum monarki yang buta, melainkan sebagai sastrawan yang kritis pada praktik kekuasaan yang tiranis, di bawah kuasa para tiran.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo