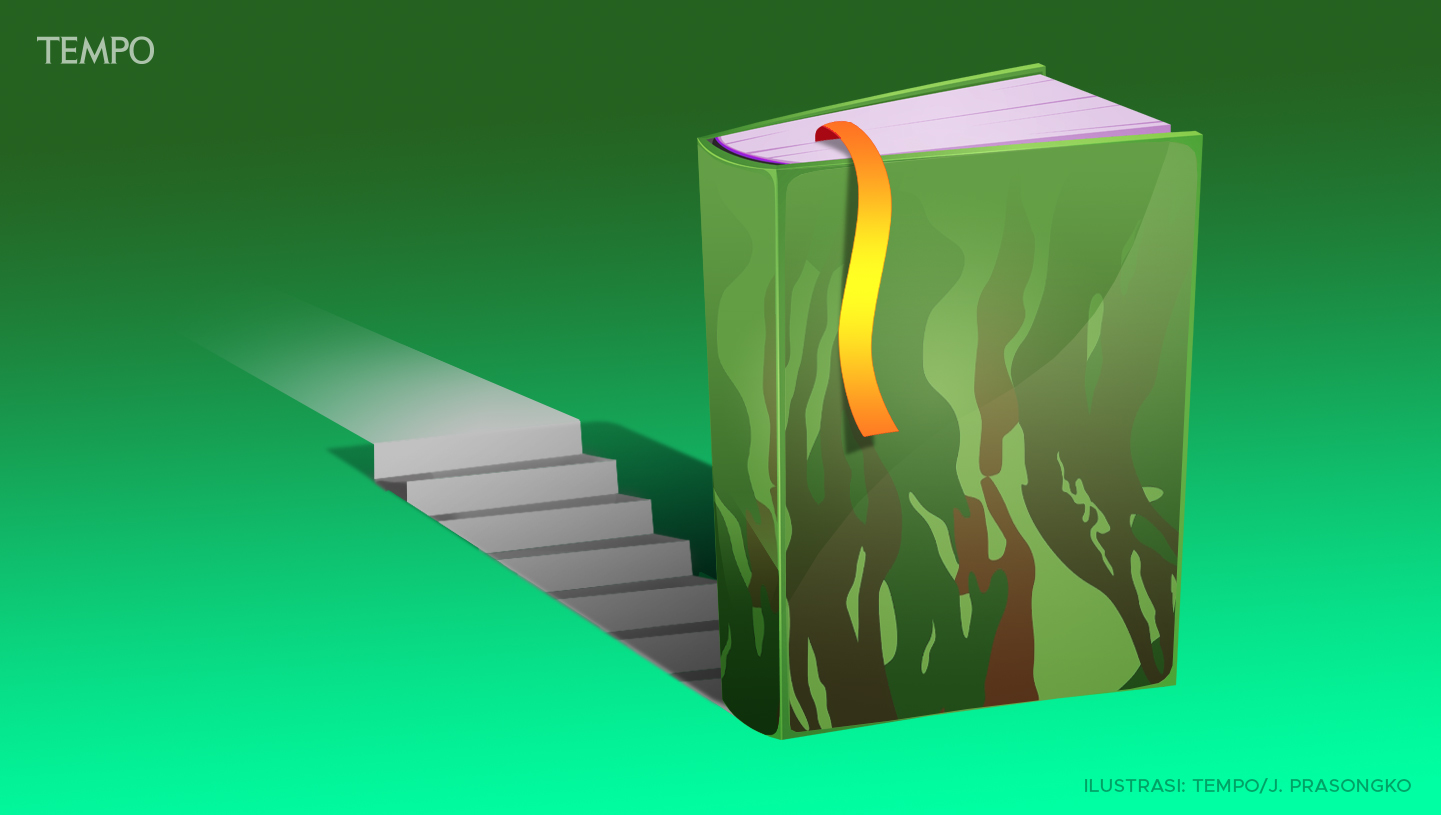Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
YANG sering terabaikan dalam daya hidup berbangsa adalah panduan keutamaan lewat keteladanan, laku, dan proses politik para elite di ruang publik. Ruang publik adalah tempat pendidikan warga negara yang terbesar. Hari-hari ini bangsa Indonesia sedang mengalami tragedi terbesar, yakni runtuhnya panduan nilai-nilai keutamaan di ruang publik.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo