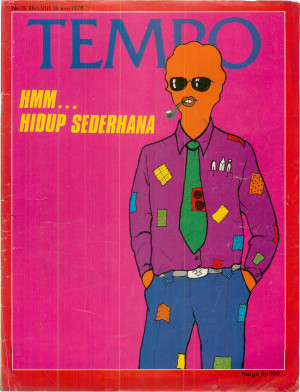EMPAT tahun yang lalu, beberapa hari setelah "peristiwa 15
Januari", pemerintah mencanangkan keharusan hidup sederhana --
terutama di kalangan pejabat tinggi. Kini seruan yang sama
terdengar lagi.
Mula-mula yang bicara adalah Dr. Emil Salim, dalam posisinya
sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup (PPLH). 27 Mei yang lalu, di depan anggota Perhumas,
persatuan para ahli hubungan masyarakat, dan para tamu lain di
salah satu ruang Hotel Hilton yang mewah, Menteri yang diminta
berbicara itu menarik perhatian karena seruan hidupsederhananya
itu.
Datang terlambat lebih dari setengah jam, Emil Salim yang baru
bertemu dengan Presiden mengungkapkan bahwa ada instruksi Kepala
Negara buatnya. Yakni, agar ia menjabarkan pengertian "pola
hidup sederhana", untuk mencari patokan guna melakukan tindakan
dan sanksi bila terjadi penyelewengan.
Sudah dapat diduga, bahwa reaksi pertama terhadap pernyataan itu
paling sedikit bersifat angkat bahu. Apalagi ketika Emil Salim
menyatakan, bahwa hidup sederhana itu "bukan sok melarat",
melainkan "hidup yang wajar sesuai dengan lingkungan di mana
seseorang berada." Sebab soalnya: lingkungan yang mana? Ada yang
hidup di lingkungan daerah mewah seperti Kemang, Jakarta, ada
yang di daerah miskin seperti di Mangga Dua. Dan keduanya toh
sering ketemu di Jalan Hayam Wuruk.
Dengan kata lain, hanya dengan menyebut "sesuai dengan
lingkungan" saja, mana yang hidup sederhana atau mana yang mewah
masih kabur -- dan bisa ditafsirkan macam-macam, sesuai dengan
kebiasaan hidup seseorang. Seperti yang digambarkan oleh tokoh
harikatur harian Kompas pekan lalu:
Namun barangkali bisa diharapkan, bahwa pidato Presiden Soeharto
Senin pekan ini dapat menjadi sekedar pegangan yang lebih
jelas. Berbicara pada upacara pembukaan Seminar Nasional
Pengembangan Lingkungan Hidup 5 Juni 1978 di Istana Merdeka,
Jakarta, Presiden menandaskan: " . . . jelaslah, bahwa pola
konsumsi dan gaya hidup mewah di banyak negara-negara maju yang
tinggi pendapatannya tidak akan mungkin didukung oleh kemampuan
ekonomi Rakyat kita." Maka, kata Presiden, "menjadi sangat perlu
untuk mengendalikan dan membina gaya hidup dan pola konsumsi
yang lebih serasi dengan lingkungan hidup sosial rakyat
kita."
Dengan menyebut "rakyat", dan menyebut pula tingkat pendapatan
yang di bawah US$ 200 per jiwa setahun nampaknya bagi Presiden
itulah yang jadi tongkatpengukur. Lingkungan tempat kita hidup
dengan begitu bukan lingkungan "tingkat tinggi" yang cuma
sedikit itu, melainkan lingkungan luas yang jauh lebih melarat.
Agaknya dengan kesadaran ini Menteri Emil Salim menyatakan,
bahwa sasaran dari seruan (atau nanti tindakan juga?) pemerintah
adalah dari golongan 20% penduduk yang tertinggi penghasilannya.
Tapi toh tetap jadi pertanyaan, sejauh mana mereka yang
tergolong kaya itu akan diarahkan supaya "sederhana". Sampai
kini orang cuma dapat menduga-duga saja -- seraya agak ragu apa
pemerintah bisa benar-benar "mengatur" kelompok puncak itu.
Dengan kata lain, ukuran apa itu "sederhana" masih harus
dirumuskan, sebelum -- lebih sulit lagi -- diterapkan.
Namun ada tanda-tanda, bahwa perkara hidup sederhana itu akan
dikaitkan secara serius dengan kesadaran tentang terbatasnya
sumber-sumber alam. Pidato Presiden Soeharto di depan para ahli
lingkungan awal pekan ini menunjukkan kecenderungan itu. Kepala
Negara, setelah menyebut "pola konsumsi dan gaya hidup mewah,"
melanjutkannya dengan menyebut sumber-sumber alam "yang tidak
dapat dipulihkan kembali setelah habis dipakai." Misalnya gas,
minyak bumi, batu bara dan lain-lain. "Kita tidak dapat menambah
sumber alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa sesuka hati kita,"
kata Presiden.
Dapatkah kemudian diramalkan, bahwa rumusan pemerintah dengan
"hidup sederhana" adalah kurang-lebih "hidup yang tidak boros
sumber alam"? Mungkin begitu -- apalagi mengingat bahwa ada
faktor-faktor yang dapat diukur Secara obyektif dalam pengertian
"boros sumber alam" itu. Sehingga pengertian "hidup sederhana"
tidak terjatuh ke dalam ukuran yang aneh-aneh, misalnya pakai
baju tambalan atau ogah makan ayam goreng.
Dari kalangan yang sudah lebib lama menekum perkara lingkungan,
kecenderungan ke arah mengkaitkan "kesederhanaan" dengan
kehematan-makan-sumber-alam sudah pasti menggembirakan. Dr.
Aprilani Soegianto, Ketua Umum Himpunan Lingkungan misalnya
berkata: "Sudah lama kami sadari, bahwa cepat atau lambat bahan
bakar fosil kita akan habis."
Tapi tidak cuma itu saja. Dengan kesadaran akan keterbatasan
sumber alam yang bisa menyeleweng dari "hidup sederhana bukan
cuma orang seorang, tapi juga kecenderungan umum. Aprilani
misalnya melihat dengan cemas "cara-cara pembangunan seperti
sekarang".
Yang jelas misalnya adalah pembangunan perkotaan. Di Jakarta,
gedung-gedung didirikan ke atas, kian lama kian tinggi. Memang,
diakui bahwa gedung-gedung jangkung itu timbul sebagai jawaban
terhadap dilema antara persediaan tanah yang terbatas dengan
kebutuhan akan pemukiman dan perkantoran. Memang, seperti diakui
Aprilani, gedung-gedung itu menghemat "sumber alam yang utama,"
yakni tanah. Tapi banyak sumber alam lain jadinya diboroskan.
Misalnya keharusan adanya lift dan penyejukan udara -- yang
boros enerji itu (lihat: Teknologi)
"Sekarang ini," kritik Aprilani, "gedung bertingkat semakin
banyak berdinding tertutup kaca." Dari sudut enerji kata
Aprilani pula, penggunaan kaca sangat tidak efisien. Sebab panas
matahari di luar serta merta ditransfer ke dalam. Ini
mengakibatkan perlu lebih banyak enerji lagi untuk mendinginkan
gedung-gedung bertingkat itu. Seraya mengutip contoh Singapura
-- yang 30% tenaga listriknya habis untuk penyejukan udara saja
-- Dr. Aprilani Soegiarto menganjurkan pemerintah DKI
mempelajari penggunaan enerji matahari untuk pendinginan
gedung-gedung jangkung di Jakarta.
Namun rupanya konstruksi gedung-gedung jangkung di kota besar
Indonesia memang masih cenderung menggunakan model Amerika
Serikat atau Eropa sebelum negeri-negeri kaya itu dihantam
krisis enerji di awal 1970-an. Rumah-rumah mewah, yang dibangun
begitu rupa hingga musti pakai AC, dengan peralatan listrik
macam-macam juga telah menyedot enerji dalam porsi yang besar.
Tapi yang lebih kurang sedap adalah mobil pribadi.
Selama ini, pemerintah memang cenderung untuk tidak menggalakkan
pemilikan mobil pribadi. Misalnya dengan anjuran merger produsen
mobil disertai anjuran untuk mengalihkan produksi sedan ke jenis
kendaraan niaga. Juga sementara itu, kehendak untuk menerapkan
"hidup sederhana" dilakukan pula di situ. Ini terutama nampak
dalam peraturan yang keluar satu minggu setelah "peristiwa 15
Januari", ketika puluhan mobil (tapi cuma yang bikinan Jepang)
dirusak atau dibakar.
Meskipun demikian, peraturan-peraturan di atas nampaknya belum
dikaitkan dengan kesadaran yang didesak oleh terbatasnya
sumber-sumber enerji serta kebersihan lingkungan. Dalam
peraturan tahun 1974 misalnya dinyatakan larangan impor mobil
sedan jenis Mercedez Benz 300 ke atas, atau yang berukuran
silinder 5000 cc ke atas. Tapi, seperti dikatakan oleh seorang
ahli lingkungan, "apalah artinya jika seorang yang tak boleh
memakai Mercedez Benz 300, tapi sementara itu ia punya lima
mobil Mercy 200?" Dari segi pengotoran udara akibatnya bisa
lebih dahsyat. Makin banyak jumlah kendaraan bermotor dengan
bensin, makin besar pengotoran yang terjadi -- dan makin boros
enerji.
Mendesaknya suatu beleid yang lebih rasionil di bidang kendaraan
bermotor mungkin bakal disuarakan dalam Seminar Nasional pekan
ini. Setiap tahun, sejumlah 78 ribu mobil baru meluncur dari
bengkel perakitan di seluruh Indonesia. Semuanya terbagi atas 23
merek sedan dan 27 merek kendaraan niaga. Di Jakarta sendiri
jumlah kendaraan bermotor tahun lalu saja sudah mencapai
setengah juta, terdiri dari mobil dan yang beroda dua. Itu belum
termasuk mobil tentara dan korps diplomatik. "Jakarta," kata
seorang ahli, "sudah penuh dengan gas CO dan CO2, plus logam
timah hitam (Pb) yang tercampur dalam bensin."
BAGAIMANA cara mengatasinya? Para ahli lingkungan umumnya
menganjurkan untuk melihat tauladan Singapura, yang banyak
mendorong -- dengan peraturan yang ketat -- penggunaan alat
transpor umum seperti bis dan taxi, sehingga jumlah kendaraan di
jalanan jauh berkurang. Di Jakarta tindakan ke arah itu belum
nampak. Bahkan dilarangnya becak beroperasi di pelbagai tempat,
dengan alasan akan meruwetkan lalulintas, menyebabkan
kecenderungan bermotor meningkat. Padahal, seperti dinyatakan
oleh sementara pengritik, lalu lintas tidak berkurang ruwet
bagi mereka yang tak punya mobil.
Tapi toh eksplosi kendaraan bermotor itu tak terbatas di
kota-kota. Tak dapat dimungkiri bahwa peran transportasi
bermotor untuk umum, terutama Colt, banyak membantu perhubungan
dan kehidupan ekonomi. Di Jawa kini hampir tak ada desa yang
begitu terpencil, tak bisa di hubungi dengan cepat. Apalagi
perbaikan jalan memang nampak di mana-mana. Namun pembangunan
bukar saja memecahkan problim lama, tapi juga -- apa boleh buat
-- menciptakan problim baru. Dan akibat buruk permotoran adalah
salah satunya.
Yang lebih buruk ialah, tentu saja, bila gara-gara kepingin
seperti orang kota, anak-anak muda di desa mengikuti pola hidup
yang sebenarnya tidak sehat. Dewasa ini sangat sering
disinyalir, meskipun belum sampai diselidiki, banyaknya para
pemilik tanah di pinggiran yang menjual sebagian besar miliknya
kenapa para orang kaya di kota -- untuk menghadiahi anak
laki-laki mereka dengan sepeda motor. Disinyalir pula bahwa
dengan makin terbatasnya tanah, para petani undur ke
hutan-hutan, serta menebangi kayu. Dalam hal itu, terjadi pula
kerusakan lingkungan.
Namun di pedesaan itu, kecenderungan lain untuk
boros-sumber-alam terjadi di samping kian gundulnya hutan-hutan.
Menurut Dr. Aprilani Soegiarto, itu merupakan akibat dari
penggunaan bibit unggul. "Kerakusannya akan pupuk sintetis,"
kata Aprilani, "serta keharusan kita untuk melindunginya dengan
pestisida yang juga berasal dari industri petro-kimia,
menyebabkan pertanian akan sangat tergantung pada bahan bakar
fosil pula."
Oleh Aprilani kemudian diambil hasilpenelitian Lembaga Pusat
Penelitian Pertanian di Bogor. Dari penelitian itu, dilihat
bahwa "tingkat keborosan enerji seperti yang terjadi di
Amerika, juga akan tercapai di Indonesia. Di Amerika, kata
Aprilani, perbandingan antara enerji yang dimasukkan dengan
enerji yang keluar tinggal 12. Di Indonesia masih 10. "Ini
relatif lebih baik," kata Aprilani, "tapi jangan lupa hanya
lima tahun sampai 10 tahun yang lalu angka yang sama tercatat
di Amerika."
Kiranya itulah sebab mengapa Lembaga Pusat Penelitian Pertanian
sudah mulai bereksperimen kembali dengan pertanian gilir-tandur
atau crop rotation. Metode ini tak terlalu tergantung pada
pemasukan enerji dari luar -- salah satu cara pertanian yang
menghemat enerji. Misalnya dengan penanaman kacang-kacangan,
secara bergiliran dengan padi. Atau pemeliharaan ganggang di
sawah yang dapat mengikat nitrogen secara alamiah, seperti yang
pernah diusulkan oleh Dr. Gunawan Satari dari Universitas
Padjadjaran.
Tentunya konsekwensi saran semacam itu ialah mengubah orientasi
yang selama ini terarah kepada naiknya produksi padi melalui
monokultur padi unggul -- satu hal yang dikritik oleh sementara
ahli lingkungan. Dan memang, seperti di negara-negara lain,
kesadaran akan lingkungan, akan kelestarian sumber alam, mau tak
mau bisa meninjau kembali pandangan hidup dan beleid kita yang
semula.
Namun barangkali tidak mengapa. Seluruh dunia nampaknya tengah
menyadari ini dengan akut dan was-was -- dan mau tak mau
pengaruhnya bisa sampai pula ke Indonesia. Di Jepang misalnya,
di negeri yang melahirkan Honda dan Toyota itu, Ketua Lembaga
Penelitian Lingkungan Tokue Shibata berkata "Otomobil, yang
dulu merupakan lambang peradaban modern dan lambang status, kini
berubah menjadi sebuah lambang tragedi yang seperti setan."
Seperti halnya kini dua anak merupakan lambang fikiran maju,
sepeda pun -- yang terlihat di Eropa dan Amerika -- demikian
pula. Kemewahan rumah sakit kini digantikan dengan ketekunan
berolahraga untuk kesehatan, dan makanan kalengan kini terasa
memualkan, tak sebanding dengan sayur yang langsung dipetik dari
halaman rumah.
Hidup kembali "melarat"? Barangkali tidak. Kesederhanaan
tiba-tiba menjadi persoalan hidup sehat, dan masuk akal. Sikap
itu juga menyangkut apa yang disebut Presiden Soeharto sebagai
"ikatan solidaritas antara generasi sekarang dengan generasi
nanti." Dengan kata lain, suatu sikap "untuk tidak menghabiskan
sumber-sumber alam hanya untuk keperluan sekarang ini, atau
kebutuhan generasi masa kini." Presiden menyebut kata
"solidaritas".
Di Amerika pun akhir-akhir ini pernah terlihat orang memasang
stiker atau huruf-huruf tempel: "Live simply that others may
simply live" Hidup sederhana agar orang lain bisa hidup juga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini