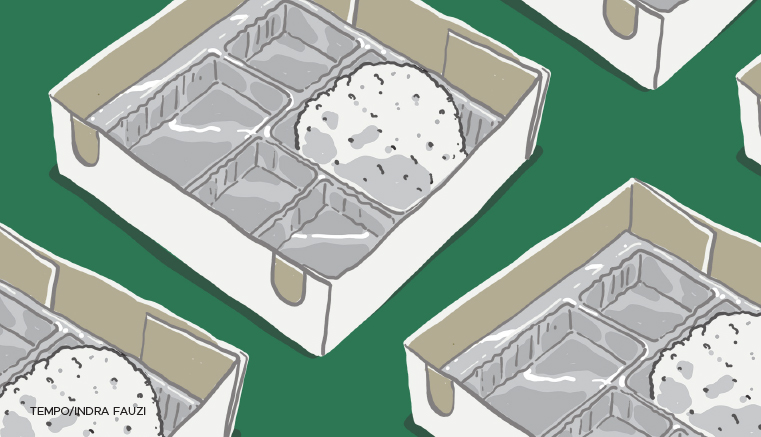Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Sirius sebenarnya punya jadwal terbit. Pada Februari-Maret, jika cuaca bersahabat, penduduk bumi bisa menikmati sinar bintang paling terang dalam rasi Canis Major ini dengan mata telanjang di malam hari.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo