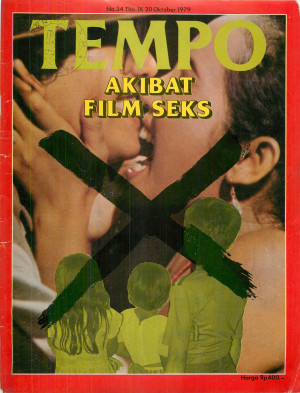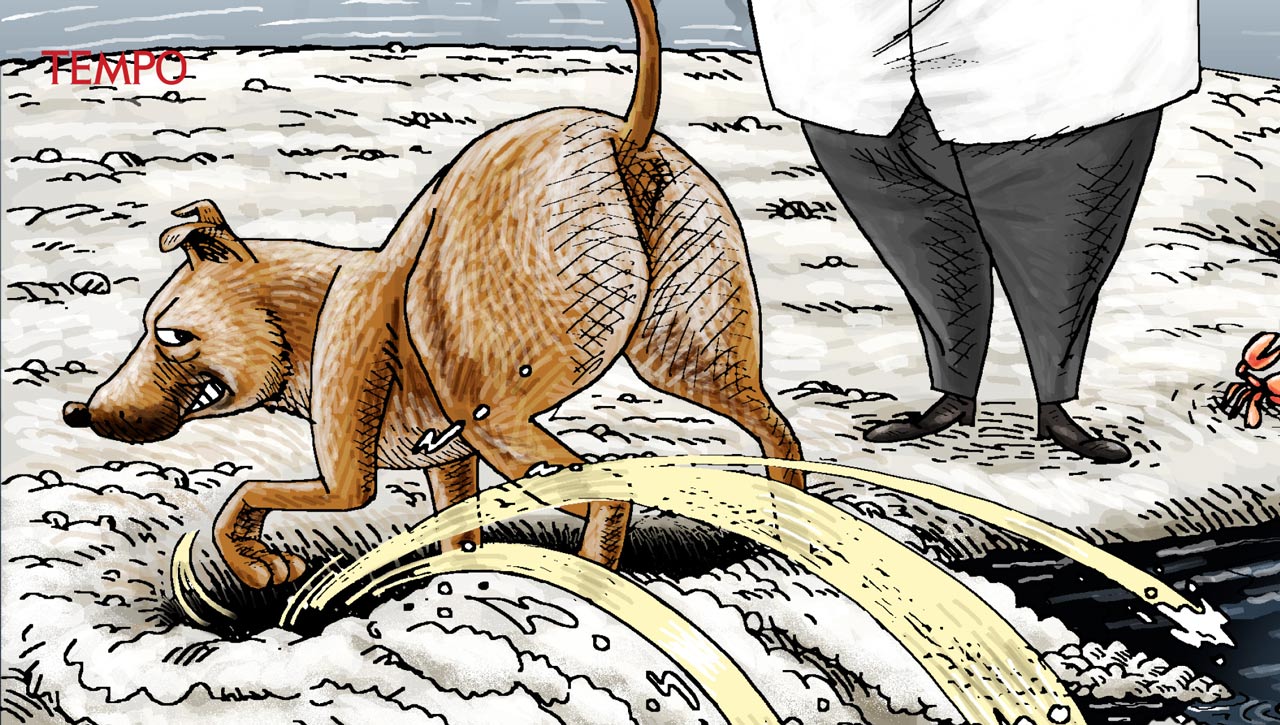MULUT terkatup dan berbicara adalah tabu. Tapi tangan terus
bekerja. Sebab, kalau ada yang bersuara, apalagi berteriak,
tempayan, kuali atau pasu yang sedang dibakar di perapian,
langsung akan terkejut. Dan kejutan ini akan mengakibatkan
retakan, bahkan pasu yang sedang di perapian bisa terbelah tanpa
sebab.
Larangan berbicara di tempat pembuatan gerabah (kerajinan dari
tanah liat) di Berru--salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan
telah mentradisi sejak puluhan tahun yang lalu. Kerja macam ini
juga tabu bagi kaum pria. Sehingga hanya dikerjakan oleh wanita
saja. Bahkan kaum pria juga dilarang berada di sekitar tempat
pembuatan gerabah itu. Tak heran jika, para ibu di sana hanya
menurunkan kepandaiannya ini kepada anak perempuan. Demikian
tulis Dr. R.P. Soejono Kepala Bidang Pusat Penelitian Purbakala
dan Peninggalan Nasional yang sedang menyelidiki lokasi Berru.
Tanah liat yang berasal dari Berru berwarna kuning
kecoklat-coklatan. Penduduk di sana menamakannya samaoling.
Setelah disaring dari batu-batuan samaoling kemudian dibubuhi
air sedikit dan siap dibentuk untuk berbagai macam gerabah.
Pembuatannya tidak begitu beda dengan cara pembuatan gerabah
umumnya. Yaitu dengan perbot (istilah di Jawa) yang terdiri dari
tali dan roda berputar Dari ketrampilan kaki yang memutar
silinder tali, terbentuklah berbagai gerabah yang masih menjadi
prasarana kehidupan sehari-hari penduduk desa.
Kendi sebagai alat tempat minum, mereka namakan panombong,
sedangkan tempat nasi bernama pabareseng. Kuali yang diberi
kaki, dinamakan katuang Semua itu mereka hias dengan zat cair
merah. Pengerasan lewat matahari atau dibakar di perapian di
tempat terbuka dengan kayu atau daun kering.
Sistim pembakaran yang sederhan inilah, yang menjadikan gerabah
itu berkwalitas rendah. Artinya mudah pecah karena kurang
matang. Seperti juga misalnya para pembuat gerabah di Desa
Bumijaya, sekitar 15 km dari Banten Lama (Jawa-Barat). Karena
kayu mahal dan sulit didapat di Pulau Jawa yang padat ini,
pembakaran dilakukan dengan jerami. Perapian jerami ini hanya
bisa mencapai panas sekitar 300 derajat C.
Dari 2.600 jiwa penduduk Desa Bumijaya hampir tiga perempatnya
membuat gerabah. Di sini tak berlaku berbagai pantangan seperti
di Berru, Sulawesi Selatan. Menurut Jajuli Kepala Desa Bumijaya,
segumpal tanah seberat kirakira 20 kg, mudah diperoleh dengan
harga Rp 20. Kalau dijadikan gerabah, bisa mencakup 20 buah
jenis barang.
Pembuat gerabah di Bumijaya menjual sebuah pasu atau kendi
dengan harga Rp 50. Sampai di pasar, tengkulak melegonya dengan
harga dua kali lipat. Masam, laki-laki yang kini mencapai usia
80 tahun, telah membuat gerabah ini sejak berusia 20 tahun.
Penghasilannya setiap hari rata-rata hanya Rp 500. Sejak dulu
tidak ada pilihan bagi Masam untuk memindahkan sumber hidup ke
bidang lain.
Biasanya, pembuat gerabah hanya bekerja sekitar 6 bulan saja
setiap tahun yaitu dikala hujan tidak pernah menyentuh tanah.
Sebab tungku perapian tidak pernah mereka miliki.
Proyek BIPIK.
Apakah pembuatan gerabah tradisional sepeti: di Berru,
Bumijaya, atau Kampung Gunung Tangkil di Leuwiliang (Bogor)
akan musnah karena serangan barang-barang plastik yang anti
pecah?
Padahal misalnya di Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Selain gerabah tradisional seperti kendi, kendil, pengaron atau
layal. Kasongan telah banyak menarik pencinta pottery
(pecahbelah). Karena mereka juga membuat celengan dari berbagai
bentuk binatang. Plered, Purwakarta (Jawa Barat) kini sering
dijadikan tempat kunjungan pelancong yang ingin melihat
pembuatan gerabah tradisional.
Dachlan, Kepala Dinas Perindustrian Purwakarta mengatakan bahwa
kini daerahnya telah memiliki 75 unit industri gerabah dengan
tenaga kerja 1.000 orang. Selain itu, Plered juga mempunyai 40
unit industri bata dengan tenaga kerja 500 orang dan 185 unit
industri genting dengan tenaga kerja 5.000 orang.
Kawasan ini mempunyai sebuah pilot proyek yang bernama BIPIK
yaitu "bimbingan dan pengembangan industri kecil khusus untuk
golongan ekonomi lemah". Proyek ini dikelola oleh Balai
Penelitian Keramik Bandung. "Hasilnya, para pengrajin menjadi
semakin kreatif," ujar Sudarto petugas di Balai tersebut.
Naik Gengsi
Kini di Plered sedang dilatih 8 orang pengrajin dengan alat-alat
modern. Selama 8 jam sehari, mereka diwajibkan kerja dalam
ruangan 10 x 30 meter, tempat pembakaran dengan tungku yang bisa
memuat gerabah seluas 2 meter kubik. "Tungku kami memakai bahan
bakar solar," ujar Sudarto, "dan ini 30% lebih murah dari pada
bahan bakar lain." Tanah liat juga disediakan, dan tanpa
pengawasan ketat, para pengrajin itu diwajibkan untuk membuat
segala macam barang pecah belah menurut ilham dan kepandaian
mereka.
Di Plered penghasilan para pengrajin tanah liat agak lebih baik.
Kepala tukang bergaji Rp 900/hari, tukang Rp 750/hari dan
pembantu Rp 500/hari. Pak Wirta yang telah membuka pabrik
sendiri kini telah berhasil menggaji 8 orang pengrajin dengan
gaji seorang Rp 1.000/hari. Beberapa sistim tradisional masih
dipakainya, tetapi untuk pembakaran digunakan solar dengan suhu
sampai 900 derajat C. Sebetulnya sebuah gerabah sudah dianggap
baik kalau dibakar pada panas 400 derajat C.
Di Plered sekarang, kian banyak industri gerabah dengan mutu
yang lebih baik. Dalam waktu dekat, BIPIK akan membangun sarana
industri percontohan lengkap dengan biaya Rp 23 juta. Telah
disiapkan juga tanah cadangan seluas 32 hektar sebagai sumber
bahan baku. Sebab di Plered bahan kian menipis, paling
tidak--menurut penyelidikan--tidak sampai 50 tahun lagi, akan
berbentuk jurang yang cukup dalam.
Gerabah dari Plered kian naik gengsi karena beberapa hotel
internasional di Indonesia juga telah memajangnya di atas meja
makan atau di sudut-sudut ruangan sebagai pot bunga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini