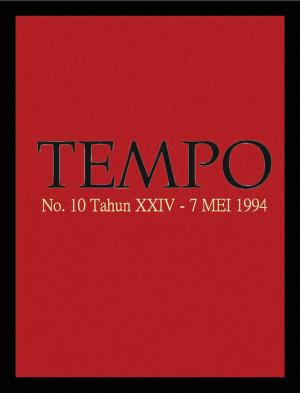MENJELANG pameran tunggalnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tahun lalu, pelukis Agus Djaya sempat melemparkan teka-teki: "Kode SS 101 itu, tahu apa maknanya?" Sambil tersenyum, ia memberi isyarat agar Staniah, sang istri, tetap diam. Istrinya pun menyunggingkan senyum. "Bukankah itu kode lukisan S. Sudjojono?" jawab saya. "Kamu pintar dan kritis," lirih suara Agus Djaya. Ia berdeham dan batuk, "Wah, masih kurang lengkap jawabanmu." Saya menyerah karena hanya sebatas itu pengetahuan saya mengenai kode lukisan S. Sudjojono, selain karya-karyanya yang tersohor sebagai cap Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia). Giliran Bu Aisah Staniah menambahkan, "SS 101 itu kode selimut Sudjojono ketika Bapak dan Sudjojono berada di Sukabumi, tahun 1950-an." Dari obrolan gayeng di rumahnya setahun lampau itu, tampak ia mampu membangkitkan seluruh ingatannya mengenai pengalaman berkesenian dengan sesama tokoh seangkatan, termasuk petualangannya dengan Sudjojono. Ia juga berkomentar, tak ikut ramai-ramai ke Yogyakarta waktu itu, ketika ibu kota republik pindah. Agus Djaya, yang aktif mengetuai Keimin Bunka Sidhoso di Jakarta, berjuang di Jakarta dan Jawa Barat. Ada alasan prinsipil kenapa ia pada tahun 1940-an hingga 1950-an menetap di Jakarta. Selaku guru MULO dan Ketua Persagi, si ahli gambar ini ingin melawan arus atas, yang datang dari pelukis-pelukis Belanda. Ia menegakkan nasionalisme, menekankan betapa pribumi juga fasih memegang palet dan kuas. Kepercayaan yang diberikan Jepang kepada pribumi untuk mengelola Keimin Bunka Sidhoso menjadi pelecut eksistensi seniman-seniman Indonesia zaman itu. Apalagi waktu itu Agus Djaya mendapat kepercayaan pula dari sesama tokoh pergerakan nasional, termasuk Ir. Soekarno, untuk berkiprah ganda: seni dan politik. Mungkin ini surprise. Tahun 1940, kelompoknya, Persagi, bisa berpameran di gedung Bataviasch Kunstkring, dan 1941 di Rijck Museum Nederland. Usaha sang ahli gambar itu memberi impresi sejuk bahwa pribumi toh kampiun. Koran Parool Vrij Nederland (sampai kini masih top) memuat berita besar seniman Indonesia tersebut saat itu. Ini pula yang membuat seniman-seniman Belanda di Jakarta tidak lagi jumawa. Hofker, Bonnet, Dake, Desence, dan Straser memperoleh tandingan setimpal. Yang jelas, dari keberadaan seniman-seniman Indonesia yang dipelopori oleh Persagi dan Agus Djaya selaku ketuanya pada tahun 1940-an, cita-cita nasionalisme dalam seni lukis terwujud. Persagi membuahkan kesadaran kreatif dalam konstelasi perjuangan nasional melawan penjajah negeri. Sebagai kolonel infanteri saat itu, Agus Djaya harus memantapkan pilihan hidup: menjadi duta besar wilayah Eropa atau seniman. Dasar cinta dan aliran darahnya seni, Agus memilih melukis. Tawaran Bung Karno untuk menjadi diplomat ditolaknya. Tapi, dalam prinsip hidup disiplin, ia memiliki naluri prajurit. Ia tangkas menentukan sikap. Perwira yang mengantongi tiga anugerah perjuangan (Gerakan Militer I, II, III dan Satyalencana Peristiwa Perang Kemerdekaan) itu hingga akhir hayatnya, Ahad pekan lalu, tetap konsisten dengan jiwa kesatrianya. Hari-hari bahagia dan tahun penuh bunga adalah ketika almarhum menetap di Bali. Itu dirintis tahun 1953 (semula mondar-mandir Jakarta--Bali) dan ia menetap hingga 1970. Kembali mudik ke Jawa Barat setelah Bali direguknya puluhan tahun sungguh merupakan pilihan rasional ketika seni lukis mulai marak. Agus Djaya pun tampak sistematis dan hidup terprogram. Harus mengartikulasikan keadaan yang kapitalistis itu dengan cara yang sakelek. Itulah, maka ia harus semakin hemat dan teliti. Karya-karya yang tersisa dari kebakaran di Bali tahun 1966 diinventarisasi dan disimpan rapi. Rak penyimpan tetap sederhana, tapi ia hafal betul posisi dan letak karyanya dari tahun ke tahun. Yang termasuk disayang ia taruh di paviliun agar jauh dari air kali yang terkadang naik di rumahnya. Pada umumnya, karya yang menyimpan tema kerakyatan atau yang berbau legenda adalah yang paling disayang dan terkadang dilukis berulang-ulang. Sebuah yang masih bertengger di dalam rumahnya di kawasan Pamulang, Ciputat, adalah Ratu Kidul -- digambarkan secara utuh, berdiri dengan sekujur atributnya. Lukisan ini dalam dominasi warna hijau kekuning- kuningan. Lukisan ini bersanding dengan karya besar sepulang ia pergi haji yang melukiskan umat manusia mengitari Kabah dalam doa. Ciri khas lukisan Agus Djaya dibandingkan dengan tokoh seangkatannya adalah kenaifannya menggarap objek. Ia emoh berspekulasi, apalagi dengan objek yang tak dikenalnya secara harfiah. Terbatas pada, misalnya, Jaka Tarub dan Bidadari, Ande-Ande Lumut, Petruk Dadi Ratu, atau berbagai objek lain tentang jelata di Bali. Pewarnaannya pun terkesan tak ada duanya. Melihat sekelebat, siapa pun tahu bahwa pelukis pembuat warna itu adalah Agus Djaya. Seronoknya postur perempuan sedang mandi sempat mengilhami banyak seniman lain, termasuk yang dilukis di slebor becak di wilayah Solo--Yogya. Semua itu tentu berpulang pada peran Persagi. Jika melukis bidadari, Agus Djaya tak bakal menggambarkannya seperti dewi yang bersayap mirip lukisan Leonardo da Vinci. Paling pol, dengan selendang tipis bergerai- gerai. Acuan-acuan melukis seperti itu tampaknya memang mengalami masa luruh. Apalagi tatkala kepiawaian teknik dan elaborasi gagasan mulai melanda seniman sesudah Agus Djaya. Namun, hal- hal yang dirasa tetap penting hingga saat almarhum wafat, tanggal 24 April 1994, pukul 17.30 WIB -- dalam usia 81 tahun -- adalah cita-cita dan semangat nasionalisme ke dalam gerakan seni lukis Indonesia yang terpatri dalam bingkai sejarah seni rupa kita. Itu jangan dilupa!Sri Warso Wahono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini