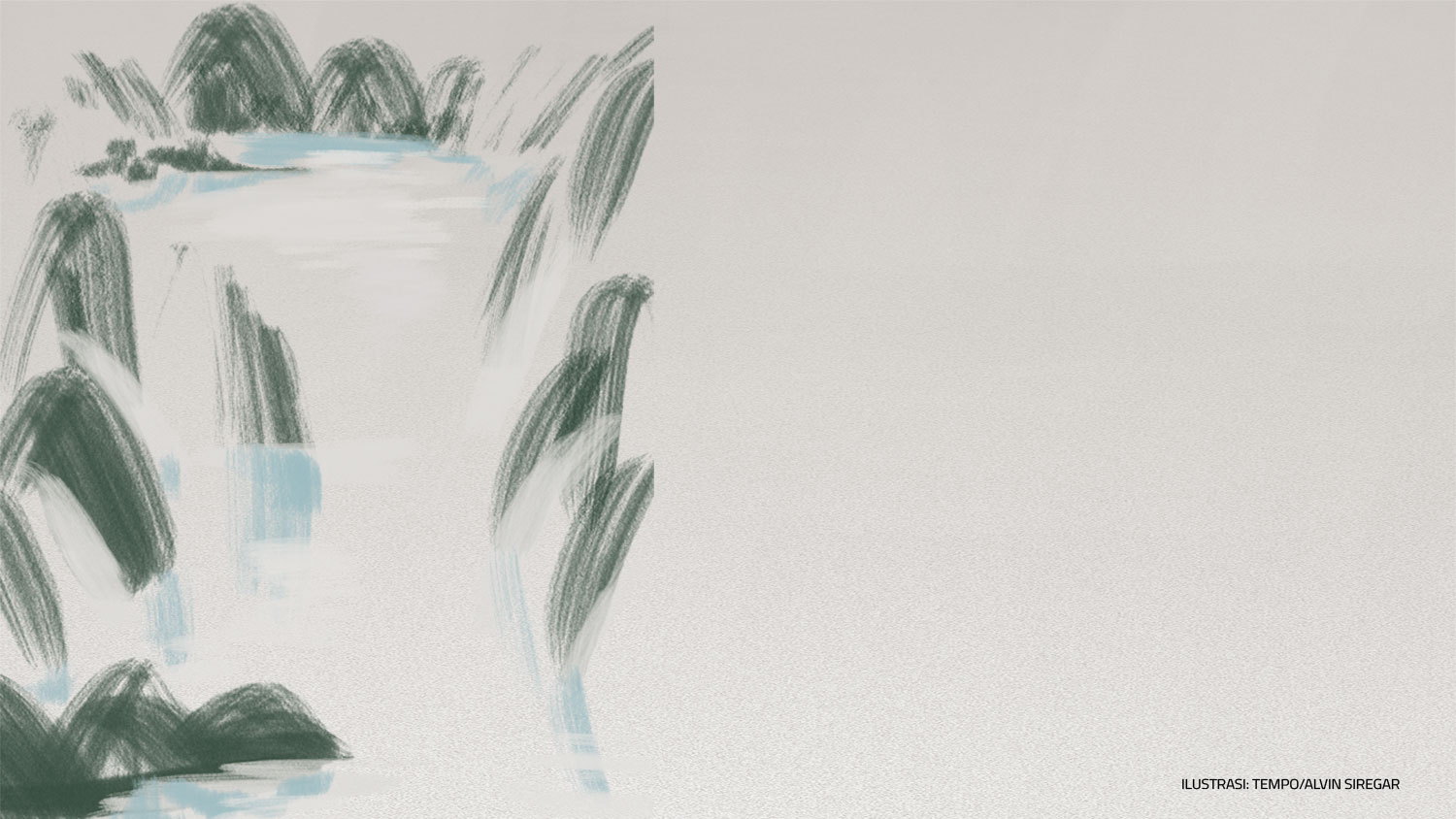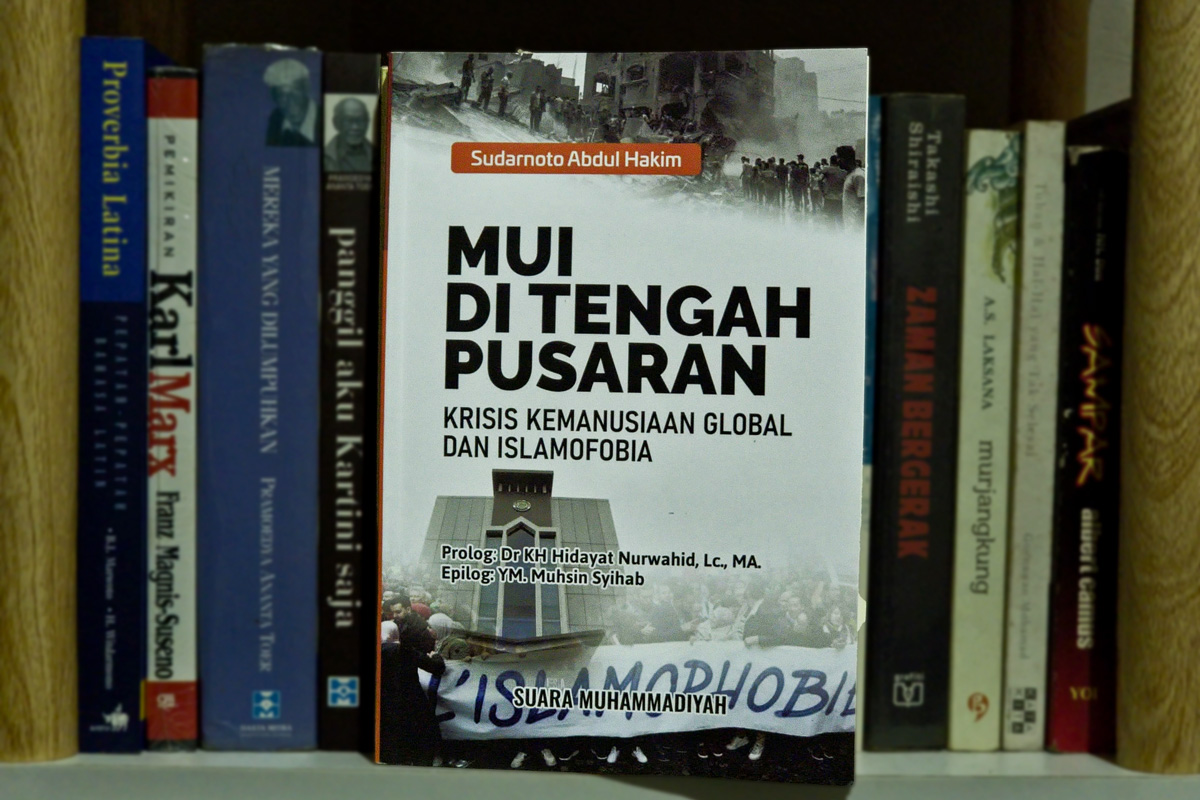Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Festival We Are One membuat kategori untuk film tentang orang kulit hitam.
Ada delapan film yang masuk kategori Black Voices.
Selain menyoroti diskriminasi ras, Black Voices menayangkan film tentang Afrika.
HIDUP dan mati, sebelum di tangan Tuhan, ada pada pengendara ojek darah atau blood rider bernama Joseph. Tugasnya mengantar darah dengan sepeda motor dari bank semacam Palang Merah Indonesia ke rumah sakit ibu dan anak di Lagos, Nigeria. Walau julukan profesi itu mentereng, tak sembarang orang di Lagos mau menjalaninya. Sebab, telat sedikit saja berabe akibatnya. Tak jarang nyawa ibu yang baru melahirkan melayang karena Joseph terhalang kemacetan lalu lintas sehingga terlambat tiba di rumah sakit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Walhasil, Joseph, seperti terungkap dalam film dokumenter Blood Rider, tak lepas dari beban dosa yang meneror pikirannya. Ia kerap merasa bersalah bila penerima darah keburu meninggal. Emosi gelap Joseph berjumpa dengan realitas sosial yang tragis, karena ojek darah tak ubahnya memperdagangkan nyawa sendiri untuk keselamatan jiwa lain. Kombinasi itu terasa dalam film berdurasi 17 menit yang disutradarai Jon Kasbe tersebut. Dua dari sederet dokumenter Kasbe sebelum ini, When Lambs Become Lions (2018), menang di Tribeca Film Festival, sedangkan Heartbeats of Fiji menjadi juara Emmy Awards 2015.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Karena pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, Blood Rider tayang perdana di We Are One: A Global Film Festival, yang mengudara di YouTube mulai 29 Mei hingga 7 Juni lalu. Di festival itu, Blood Rider dikurasi menjadi salah satu dari delapan film yang masuk kategori Black Voices atau suara orang kulit hitam. Selain Blood Rider, ada film pendek seperti Traveling While Black, Tapi!, Atlantique, Parsi, dan Pelourinho, They Don’t Really Care about Us. Adapun dari film Black Voices di festival daring (online) ini, Ar Condicionado yang berdurasi panjang, lebih dari satu jam.

Adegan dalam film dokumenter Blood Rider./Youtube
Kategori Black Voices relevan dengan #BlackLivesMatter. Tanda pagar itu kembali menjadi isu global setelah George Floyd, orang kulit hitam, mati di tangan polisi di Minnesota, Amerika Serikat, 25 Mei 2020. Sehari setelahnya, gelombang protes muncul di berbagai kota Amerika. Floyd menjadi simbol perlawanan. Para demonstran mengutuk laku brutal polisi Minnesota dan diskriminasi rasial yang kerap diterima orang kulit hitam di sana. Bahkan, puluhan hari setelah Floyd tiada, aksi mengecam rasialisme tetap menguat, termasuk di media sosial.
Konteks itu membuat keberadaan film-film tentang kulit hitam di festival We Are One menjadi aktual. Menahbiskan diri sebagai ajang film global, We Are One tak hanya memberi ruang untuk festival film dari negara berkembang. Festival itu juga memperkuat perjuangan kaum minoritas, dalam hal ini kulit berwarna, lewat kurasi ratusan filmnya. Yang menarik, permasalahan orang kulit hitam di sini lebih beragam, tak hanya berkutat di konstruksi soal diskriminasi rasial. Blood Rider, misalnya, menjadi lensa yang menangkap kondisi sosial, kesehatan, dan ekonomi di Nigeria yang mayoritas penduduknya adalah kulit hitam.

Adegan dalam film dokumenter Blood Rider./IMDB
Menurut Jon Kasbe, penting kiranya melihat lebih banyak perspektif orang kulit hitam melalui beragam media, termasuk film. Ia sendiri, sebagai keturunan Australia-India, terinspirasi oleh perjuangan itu. “Saya berharap perubahan (perlawanan terhadap diskriminasi berbasis ras) langgeng bahkan di seluruh dunia, karena rasisme sangat mengakar, berbahaya, dan destruktif,” katanya kepada Tempo melalui surat elektronik, 11 Juni lalu.
Setelah menyoroti komunitas dan kelompok terpinggirkan di film-film sebelumnya, dalam Blood Rider Kasbe merekam kondisi Nigeria yang memiliki tingkat kematian ibu tertinggi keempat di dunia. Sulitnya ibu melahirkan mendapatkan darah di rumah sakit menjadi salah satu faktor. Di negara itu, hasil donor lebih banyak disimpan di bank darah ketimbang rumah sakit. Menjadi pelik karena jarak bank darah ke rumah sakit kadang amat jauh, sehingga butuh waktu hingga 24 jam untuk mengantarkan darah kepada pasien. Belum lagi kemacetan lalu lintas yang menghambat pengantaran.

Poster film dan adegan dalam film Traveling While Black./Imdb
Latar belakang itu membuat Blood Rider terasa humanis tapi juga menegangkan karena dituturkan dari sudut pandang Joseph sebagai pengendara ojek darah. “Kombinasi itu sesuai dengan etos saya dalam membuat film. Yang menonton When Lambs Become Lions tentu paham karena di film itu saya menyorot negara Afrika lain, yakni Kenya,” ujar Kasbe.
Selain Blood Rider, ada Atlantique (2009) yang dikurasi Film Festival New York. Karya sutradara Mati Diop ini menceritakan perjalanan ilegal anak-anak muda Senegal saat bermigrasi dengan perahu. Diop adalah sutradara kulit hitam pertama yang berkompetisi untuk Palme d’Or di Festival Film Cannes. Oleh Diop, Atlantique menjadi dasarnya dalam menggarap Atlantics (2019), yang tayang di Netflix. Atlantics mengangkat cerita tentang perempuan bernama Ada (diperankan Mame Bineta Sane) dan pacar gelapnya, Souleiman, yang dibumbui kasus serangan hantu.
Namun Atlantics tak mengarah pada plot mistik yang klise. Film ini juga menyembulkan isu soal perbedaan kelas, antara Ada yang tajir dan tinggal di Dakar, ibu kota Senegal, dan Souleiman, pekerja bangunan yang miskin. Kepelikan yang dihadapi Ada ialah pertunangannya dengan Omar, seorang pebisnis. Beda cerita dengan Souleiman yang seperti banyak buruh bangunan lain di sana, terkatung-katung karena telat mendapat bayaran.

Poster film dan adegan dalam film Traveling While Black./Youtube
Lain halnya Traveling While Black, yang juga ada di kategori Black Voices. Film berteknologi 360° virtual reality ini merekam sejarah kolektif orang kulit hitam Amerika dari dekade ke dekade. Basis narasinya adalah Green Book, kitab acuan orang kulit hitam Amerika untuk bepergian secara aman. Cara bertutur film sutradara Afro-Amerika Roger Ross Williams ini membuat kita seperti tengah masuk ke museum virtual lengkap dengan audio penjelasan. Selain diisi suara narator yang empuk, film berdurasi 19 menit ini disertai wawancara dengan sejumlah narasumber. Penjelasan itulah yang menemani penonton melompat dari masa ke masa.
Gamblang dijelaskan bagaimana orang kulit hitam sejak dulu menelan diskriminasi lewat sejumlah larangan saat bepergian. Jadi, walau mobil sudah ada di garasi sekalipun, hotel dan restoran belum tentu bisa diakses. Belum lagi ancaman pembunuhan yang tak pandang bulu, yang pernah menewaskan seorang bocah kulit hitam. Sebuah perjalanan saja, tak ayal, menjadi begitu rumit dan berbahaya; ironi yang melukai kebebasan dan hak asasi manusia.
ISMA SAVITRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo