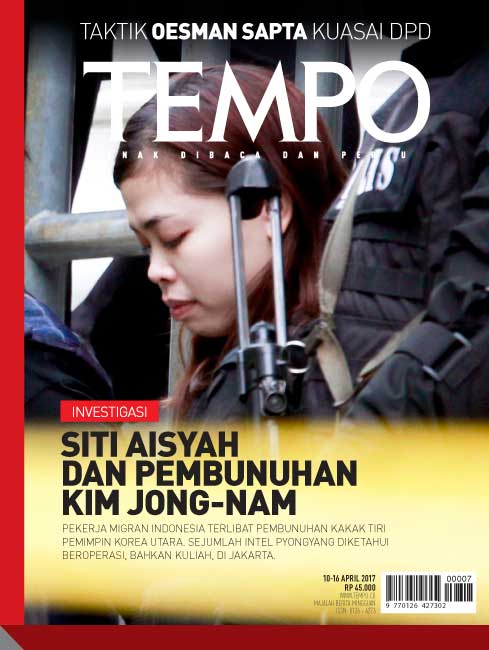Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETELAH menjadi Cinta, Dian Sastrowardoyo mengganti baju, menyanggul rambut, dan menjadi Kartini. "Ini hanya peran," kata Dian, yang sehari-hari adalah ibu dari dua anak dan istri dari Indra Maulana. Selesai menjadi Kartini, Dian memangkas rambutnya sependek mungkin, mengenakan celana panjang, dan belajar silat dari tim Iko Uwais karena dia berperan sebagai Alma dalam film terbaru laga Mo Brothers. Berikut ini adalah perbincangan Dian dengan Moyang Kasih Dewimerdeka dari Tempo di sela-sela kegiatan pemotretan di selatan Jakarta.
Apa hal pertama yang terlintas di kepala Anda saat mendapat tawaran peran sebagai Kartini?
Saya selalu memandang diri sebagai feminis. Mama saya juga seorang feminis. Dia pembaca karya Virginia Woolf dan saya pengagum Kartini. Walaupun, memang, pengetahuan saya tentang beliau masih terbatas. Jadi, pertama kali mendengar ada film Kartini, saya sudah pengen ikutan walaupun cuma jadi supporting. Ketika Mas Hanung meminta saya mencoba menjadi Kartini, saya merasa mendapat jackpot banget. Saya tahu harus banyak riset.
Apa saja buku yang dibaca untuk riset?
Buku pertama Panggil Aku Kartini Saja oleh Pramoedya Ananta Toer. Lalu Habis Gelap Terbitlah Terang Armijn Pane. Ada juga buku tentang surat-surat Kartini yang lain dari Belanda. Setelah itu, berbagai rangkuman pemikiran Kartini yang isinya kutipan penting. Semua saya lahap pelan-pelan seperti akan membuat skripsi. Kan, saya sudah dua kali menulis skripsi, masak enggak bisa? Dicicil terus. Ada anak, tunggu anak tidur dulu, baru saya membaca lagi. Lama-lama pengetahuan terbatas tentang Kartini semakin berkembang dan membentuk pengetahuan tentang Kartini. Saya mulai membayangkan Kartini sebagai manusia. Ternyata Kartini bukan orang yang pendiam. Dia buandel sejak kecil. Ini yang kurang diketahui masyarakat Indonesia. Panggilannya saja Trinil.
Bagaimana perubahan pandangan Anda tentang Kartini sebelum dan setelah membaca bukunya?
Ternyata dia perempuan yang tingkah lakunya masih muda. Tentu, sebagai orang Jawa, dia harus menahan emosi. Jadi, walaupun dia di luar kamar, tetap menunduk aja. Di dalam dirinya ada banyak gejolak. Tapi penonton harus tahu Kartini sebetulnya. Saya harus belajar bagaimana merasakan perempuan yang terkekang dengan budaya Jawa. Terus terang, Kartini adalah film pegel karena semua emosi harus ditahan.
Bagaimana pendapat Anda tentang film Kartini Sjuman Djaya?
Saya pernah menonton waktu kecil. Tapi terus terang, setelah mau memerankan Kartini, saya sengaja menghindari. Ngeri terjebak. Tapi saya ada memori tentang filmnya, di mana pembawaan Kartini di sana lebih reserved (pendiam-red), sementara di dalam film ini dia badung banget.
Untuk persiapan peran, Anda memakai kain terus ke mana-mana. Lalu bagaimana persiapan bahasa Belanda dan Jawa?
Salah satu pendalaman karakter saya memang mengenakan kain karena orang Jawa di masa lalu memiliki tradisi jalan yang berbeda, kan? Cara kita berjalan dan berinteraksi dengan orang lain sangat berbeda, sehingga Mas Hanung sejak tiga bulan sebelumnya meminta kami mengenakan kain setiap hari. Ya sudah, akhirnya saya meeting pun mengenakan kain. Soal bahasa, masing-masing sudah ada gurunya yang disediakan Mas Hanung, baik guru bahasa Jawa maupun bahasa Belanda. Tentu saja bahasa Belanda lebih susah karena saya tidak mengerti artinya. Kalau bahasa Jawa, saya masih paham karena Mama dan Eyang masih menggunakan bahasa Jawa.
Dari sekian banyak kutipan Kartini, mana yang paling mengena pada diri Anda?
Aduh, banyak banget! Salah satunya: "Saya putus asa: saya hanya boleh menulis yang bukan-bukan saja; hal yang sungguh-sungguh tidak boleh saya singgung." Kartini sebetulnya tergelitik sekali pada persoalan ketidakadilan. Kaum pribumi dijajah kaum Belanda dan kaum pribumi menengah-abangan dijajah kaum feodal bangsawannya. Melihat ketidakadilan itu, Kartini ingin mengkritik kaum bangsawan yang egoistis dan gila hormat. Dia mengkritik Belanda, kalau saja Belanda memperlakukan kaum pribumi dengan sejajar, setidaknya Anda akan mendapat partnership dan kontribusi pekerjaan dari kaum pribumi yang diberdayakan. Dia ingin mengkritik itu, tapi tak dibolehkan. Saya melihat Kartini sebagai pejuang yang menjadi tonggak perubahan dari perjuangan fisik menjadi perjuangan pemikiran. Setelah Kartini, lalu ada Boedi Oetomo dan seterusnya. Tapi sayangnya, karena dia perempuan, kesannya pemikiran dia menghina kaum laki-laki saat itu yang berego besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo