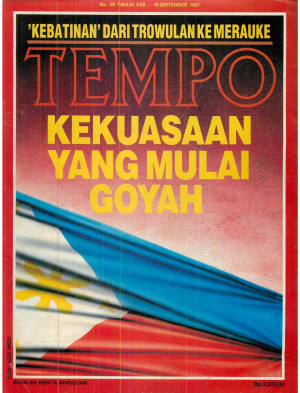"AKU pengin bunuh diri," pikir wanita gemulai itu. Sebagai pelayan apotek, tak susah baginya mencomot berbutir-butir pil tidur, yang teronggok di depan hidungnya. Keputusan untuk menyelesaikan kesepiannya lewat pil penenang itu muncul ketika hari sudah mendekati tengah malam. Lalu, selesai. Dan Niniek L. Karim, 38 tahun, si gemulai itu, turun panggung, menebar senyum. Selama tiga malam, pekan lalu, ia memerankan sosok wanita Batak -- bisa bernama Duma -- yang jadi bagian dari masyarakat urban di kota besar. Tampaknya lebih tepat Jakarta. Lho, kok wanita Batak? Padahal, ceritanya berdasarkan karya penulis Jerman Franz Xaver Kroetz, 40 tahun, yang praktis tak pernah terdengar namanya di sini. Naskah yang kemudian diadaptasikan itu berjudul Wunschkonzert, lalu dilokalkan jadi Pilihan Pendengar. Penjelasan datang dari Manuel Lutgenhorst, 39 tahun, sutradaranya. "Ini namanya pelibatan dan pertukaran budaya," katanya. Pilihan Pendengar merupakan komoditi teater yang ia jajakan dalam program keliling ke beberapa kota Asia. Juni tahun lalu main di Madras (India), kini Jakarta, segera menyusul Tokyo, dan barangkali juga Seoul atau Hong Kong. Di setiap kota, Manuel bekerja sama dengan aktris setempat untuk peran wanita kesepian itu. "Dengan warna dan penghayatan lokal. Karena wanita Indonesia, misalnya, reaksinya tentu berbeda dengan wanita India atau Jepang di saat ia terimpit perasaan asing," katanya. "Dan saya tidak membawa teori-teori. Karakter berkembang sesuai dengan penafsiran dan penghayatan aktris bersangkutan." Tapi kok Batak, bukan Jawa atau Padang misalnya? Niniek, peraih Citra sebagai aktris pemeran pembantu terbaik dalam Ibunda (1986), giliran bicara. "Karena hanya wanita Batak yang memiliki kecenderungan bekerja dan hidup sendiri di Jakarta. Lainnya tidak," tuturnya. Kesimpulan ini diambil setelah Niniek, pengajar di Fakultas Psikologi UI itu, melakukan riset selama tiga bulan dan berkonsultasi dengan rekan-rekannya sesama dosen. Wanita Bali, yang juga punya kecenderungan begitu, pernah jadi pilihan. "Tapi saya merasa kurang mengenal wataknya," tambahnya. Mula-mula pemegang peran tunggal, yang melakukan monolog atau barangkali dialog (dengan diri sendiri, lho) sepanjang pertunjukan selama 100 menit ini, setahun lalu ditawarkan kepada Tuti Indra Malaon. Aktris ini urung, konon oleh ketidaksesuaian konsep. Maka, dialihkan ke Niniek. "Saya tertarik karena ini eksperimen. Ada studi perbandingan sosial, mengingat ceritanya dipentaskan di berbagai lokasi dengan latar budaya dan sosial berlainan. India, Indonesia, lalu Jepang. Unik," kata Niniek. Kecuali itu, "Saya juga terdorong rasa khawatir. Gejala alienasi mungkin akan meningkat di sini dan jadi cermin kita di masa datang." Maka, baginya, peran itu menantang. Terutama karena sosok Duma sungguh bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya sehari-hari. "Sejak kecil hidup saya selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangi dan melindungi saya. Sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara, saya dimanja oleh kakak-kakak saya," tuturnya, sembari mengepulkan asap rokok dari bibirnya yang ... hmmm. Di lain pihak, bagi Manuel, orang Jerman yang menetap di New York dan lebih dikenal sebagai perancang panggung, perjalanan ke sini membuahkan pengalaman yang mungkin saja turistlk. Misalnya, ketika membuat seting panggung yang mirip pavilyun betulan dengan biaya Rp 800 ribu. Warga kampung -- tetangga Silke Behl, pemilik rumah Jalan Langgar, yang jadi pentas -- datang membantu. Bahkan Pak RT mengadakan selamatan. Ini menggembirakan Silke Behl, wanita Jerman asli yang kini menjadi dosen di UI. "Saya jadi lebih akrab dengan lingkungan saya," katanya. Teater macam apa ini -- yang menyedot uang pribadi Manuel US$ 25 ribu untuk studi dan keliling ke berbagai negeri? "Ini realitet," kata Rendra, yang menonton pada malam terakhir. Jadinya, memang tak ada greget, karena tidak tersedia bingkai dan aksentuasi, yang bisa membantu pemirsa. Mohamad Cholid, Laporan Yudhi Soerjoatmodjo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini