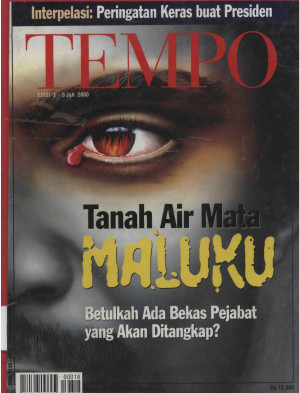Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| LAPENDOZ | ||
| Karya | : | Agung Kurniawan |
| Tempat | : | Lembaga Indonesia-Prancis, Yogyakarta |
| Waktu | : | 3-21 Juli 2000 |
ENAM kaki yang kukuh menyangga tubuh bongsor seekor serangga raksasa. Tubuhnya yang dibalut dengan warna-warna yang mengirim citra keriangan itu bak tubuh yang melata dengan susah payah untuk mengusung tiga kepala manusia. Pada salah satu kepala itu tumbuh kepala-kepala yang berukuran lebih kecil. Pada badan makhluk imajinatif ini terdapat sederet tombol yang salah satunya dihubungkan dengan selang karet ke sebuah tabung gas, yang menghadirkan suasana tegang. Ketegangan itu seolah menebar ancaman yang bisa terjadi setiap saat, ketika ada kebocoran gas yang dapat meledakkan tubuh tambun monster itu.
Inilah salah satu ilusi yang ditawarkan Agung Kurniawan dalam tiga bagian karya patung yang dibentuk dari bahan fiberglass di dalam pamerannya. Di sekitar sebuah monster serangga itu, sebuah patung manusia melayang-layang dengan kaki menjinjit. Seluruh permukaan tubuh telanjang itu penuh dengan tusukan jarum, mata terkatup, tangan setengah merentang dengan posisi ujung ibu jari bertemu dengan ujung jari telunjuk, bak orang sedang bersemadi. Sebuah selang karet tertancap pada bagian kelamin, menghubungkannya dengan ekor monster serangga tadi. Patung manusia ini menyiratkan aura kontemplatif yang bersifat individual, di balik ancaman masif yang setiap saat bisa meledak dari tubuh monster serangga. Bagi Agung, paradoks dua makhluk ini adalah sebuah metafora tentang saat-saat terakhir riwayat kritik sosial seniman lewat karya seni, yang sebenarnya sudah tidak efektif lagi ketika perubahan politik secara telak telah mengembalikan fungsi media massa dan perangkat demokrasi lainnya sebagai medium kontrol terhadap kekuasaan. Pada saat itulah, menurut Agung, seniman harus kembali ke dalam dirinya, mengkritik dirinya pada saat ada kecenderungan orang gemar menghamburkan sumpah-serapah dan kritik ke orang lain, tapi melupakan dirinya yang sebenarnya selama ini adalah sumber masalah.
Agung Kurniawan, perupa yang memutuskan tidak menyelesaikan kuliah seni rupa di ISI Yogyakarta itu, adalah satu dari sedikit perupa yang mulai jenuh dengan trend tema sosial-politik yang merebak dua tahun belakangan ini.
Kejenuhan itu tak hanya didorong oleh kenyataan bahwa tema sosial-politik mulai terjamah dan diperlakukan sebagai komoditi, tapi lebih dari itu ia merasa risi ketika begitu banyak orang kini mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari arus besar reformasi, padahal sesungguhnya merekalah yang memberi kontribusi untuk melanggengkan kekuasaan represif selama tiga dekade. Agung meminjam idiom "lapendoz" (lelaki penuh dosa), sebuah idiom prokem yang populer pada 1970-an, untuk menggambarkan pengakuan yang jujur terhadap dosa kolektif yang pernah dilakukan. Sebaliknya, hanya segelintir orang di masa lalu yang berani mengambil resiko melawan arus menentang rezim, baik secara diam-diam maupun terbuka.
Pada karyanya yang lain, Agung memberi sugesti tentang pilihan sikap dalam merespons perkembangan masyarakat saat ini. Ada dua patung telanjang tanpa lengan dan kaki, dengan tubuh penuh onak dan tangan-tangan mungil yang menggapai. Di hadapannya muncul tiga patung kepala yang mulutnya dibekap sepotong tangan, bagian atas kepala yang ditekan dengan sepotong tangan, dan sepasang mata yang ditutup dengan dua potong tangan. Pilihan simbolisasi ini mirip dengan simbolisasi pembungkaman ekspresi oleh rezim otoritarian, seolah Agung ingin mengatakan: bungkamlah dirimu untuk melihat dirimu sendiri. Artinya, orang harus menzalimi dirinya sendiri agar bisa bersikap lebih arif terhadap masyarakat. Ini tentu sebuah tafsir dari sekian tafsir yang bisa muncul dari karya Agung Kurniawan. Bahkan, tak menutup kemungkinan ada penonton yang tidak memahami bahasa metafora yang muncul dalam karya ini, ketika semua karya dan pernyataan serba terbuka pada saat ini. Sebuah pilihan yang demokratis dan sekaligus berisiko dalam berkesenian.
R. Fadjri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo