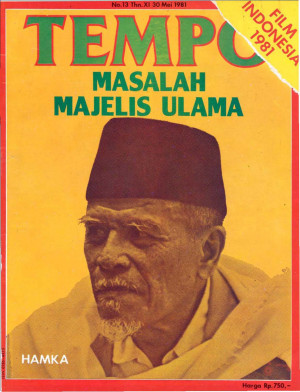SEJUMLAH artis film sudah sebulan menyiapkan kabaret Nostalgia
10 November. Dalam Festival Film Indonesia di Surabaya (25 - 30
Mei), kabaret itu dipagelarkan sebagai puncak acara. Dengan
biaya Rp 200 juta, panitianya berusaha menyelenggarakan panggung
hiburan gratis, malah sampai ke Kota Bangkalan (Madura), Gresik
dan Sidoarjo. Semua acara itu "untuk rakyat," kata Acub Zainal,
Ketua I FFI.
Kecuali Arifin C. Noer, semua sutradara kawakan (termasuk Teguh
Karya, Wim Umboh, Nva Abas Akup, Sjuman Djaja, Asrul Sani dan
Ami Prijono) kali ini menyertakan film karya masing-masing.
Selama 24 hari, tujuh juri (diketuai Sjamsoe Soegito), telah
menilai 54 film cerita dan 10 film dokumenter. Atau rata-rata
tiga film mereka nilai sehari - suatu kerja berat dan tentu
saja, dengan tergesa-gesa.
Tanpa berusaha mempengaruhi juri TEMPO berikut ini menurunkan
pilihan dan penilaiannya, bersama tulisan Yudhistira A.N.M.
Massardi (Bukan Sandiwara, Usia 18 dan Perempuan Dalam Pasungan)
dan Eddy Herwanto (Gadis, dan Dr. siti Pertiwi Kembali Ke Desa).
Sayang TEMPO belum sempat kali ini mengulas Di Bawah Lindungan
Ka'bah, film Asrul Sani, dan Seputih Hatinya Semerah Bibirnya,
film Slamet Rahardjo. Keduanya mungkin layak dibicarakan .
BUKAN SANDIWARA
Terbadap temanya, inseminasi degan sperma donor, saya merasa
sangat syuuur. Ini suatu problema baru dan aktual. Di Barat,
banyak orang bikin film tentang produk teknologi. Tapi mereka
lebih tertarik pada aspek suspense, misteri dan horror-nya.
Bukan manusianya. Nah, saya bisa bilang, inilab film pertama
yang bicara tentang konflik manusia dengan teknologi secara
kejiwaan. Secara manusiawi.
-- Sjuman Djaja
DIA mungkin benar. Tapi secara sekilas -- sesudah ia menggarap
fi Kabut Sutra Ungu (diangkat dari novel Ike Soepomo) yang laris
dan kini Bukan Sandiwara (dari novelet Titie Said) -- terkesan
bahwa sutradara Sjuman Djaja tengah berubah. Orientasinya tak
lagi pada masyarakat kelas bawah seperti dicerminkan filmnya
terdahulu, misalnya, Si Doel Anak Betawi (1972) dan Si Mamad
(1973). Atau Yang Muda Yang Bercinta (1977), yang sarat dengan
protes sosial.
Sebab KSU maupun BS (karyanya yang ke-10 dan 11) bercerita
tentang keluarga elite. Ia dicurigai telah bersekongkol dengan
pasar -- sengaja membuat film hiburan supaya laku. Dan ia marah.
"Saya tidak kompromi dengan siapa pun. Nggak ada itu kompromi
dengan pasar ataupun selera publik," katanya tegas.
Sjuman Djaja, 48 tahun, lulusan Moskow beranak 3 yang sampai
sekarang masih menduda, menegaskan bahwa ia tak pernah berubah.
Kalau toh ada, katanya, barangkali pada cara ia menyampaikan
pikirannya lewat film. Sesudah sukses KSU secara komersial,
dialah sutradara termahal saat ini.
Dengan biaya sekitar Rp 250 juta, digarap dalam waktu 4 bulan,
Bukan Sandiwara ternyata bukan film diskusi tentang teknologi
yang kering. Sebab -- menurut pengarangnya, Titie Said
--ceritanya yang "75% berdasarkan kisah nyata" itu pada dasarnya
sebuah melodrama biasa.
Hendro (Roy Marten), diplomat yang bertugas di Jepang, ternyata
lelaki mandul. Perkawinannya bertahun-tahun dengan Pia (Yenny
Rachman) tak menghasilkan anak. Kerinduan akan anak itulah yang
akhirnya mendorong pasangan itu bersepakat mencoba upaya
teknologi baru. Mereka datang ke Prof. Tsushiro (Wahyu
Sihombing), meminta sperma lelaki yang tersedia di sana.
Berhasil. Pia mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan .
. . Jepang. Meski udah diberitahu sebelumnya oleh Tsushiro,
Hendro tak sanggup menghadapi kenyataan itu. Ia terpukul dan
malu harus jadi ayah seorang anak yang ternyata berasal dari
sperma orang Jepang.
Sejak kelahiran anak itu -- bernama Rani -- Hendro kehilangan
keseimbangan. Bahkan ia jadi impoten dan hendak membunuh Rani.
Dan ia menuding istrinya sebagai biang keladi seluruh
keguncangan itu. Konflik itu terus berlarut sampai ketika mereka
kembali ke Indonesia. Hendro, juga Pia, tak tahan lagi hidup
bersandiwara terus. Yaitu di depan orang lain bermanis-manis,
sementara pasangan tak rukun lagi.
Frustrasi Hendro makin menjadi-jadi setelah secara kebetulan
suami istri itu melihat inseminasi benih unggul pada
kerbau-kerbau di sebuah peternakan. Untunglah kedua mertua Pia
(Maruli Sitompul dan Nani Wijaya) tak peduli pada asal-usul
Rani. Kehadiran anak itu sebagai cucu diterima mereka dengan
lapang, penuh kegembiraan.
Ketika Hendro terang-terangan tak mau mengakui anak itu, kedua
orang tua itu hanya tersenyum sambil berjalan-jalan bersama
menantu dan cucunya. Film yang panjangnya hampir 3 jam itu pun
berakhir -- menyarankan suatu happy ending.
Tak pelak lagi, dengan film ini Sjuman telah memamerkan
ketrampilan penyutradaraan yang hampir sempurna. Visualisasi
yang kuat dengan kecermatan ada detil -- yang semula hanya
tampak pada film Teguh Karya -- menegaskannya.
Sjuman menunjukkan kemahirannya mengolah konflik. Sehingga,
meskipun panjang, filmnya tetap memikat. Ritmenya terjaga.
Editingnya yang tangkas banyak membantu terpeliharanya segi
dramatik.
Eksperimen dalam pengambilan gambar yang dicobanya dalam Kabut
Sutra Ungu membuahkan hasilnya di sini. Dengan kata lain,
gambarnya -- di samping artistik berkat pencahayaan yang cermat
sangat efisien, berhasil memberi tekanan pada cara pengucapan
sutradara.
Hanya musik dan rias para pemainnya yang barangkali sedikit
menggangu. Dan, sebagaimana diakui Sjuman sendiri, ada beberapa
adegan yang mengingatkan orang pada film lain. Misalnya, ketika
tokoh Pia berbaring di tempat tidur dengan kepala tengadah di
bibir ranjang. Gambar itu dipadu (dalam disolve) dengan adegan
kilas-balik diiringi suara gemuruh kereta api. Itu sangat mirip
dengan adegan dalam Apocalypse Now.
Bagaimanapun, Bukan Sandiwara-lah yang rasanya paling layak
memperoleh predikat yang terbaik. Begitu pula permainan Yenny
Rachman. Dan -- ini penting juga -- Sjuman tak kehilangan
kekhasannya. Ia tetap peka dan kritis menghadapi lingkungannya.
Helikopter jatuh, mobil baru mogok, telepon rusak. Cemoohannya
terhadap teknologi itu muncul dalam filmnya secara kocak.
GADIS
Saya selalu memihak kaum bawah (underdog). Di film Inem Pelayan
Sexi, dan Rojali dan Juleha sikap itu bisa dilihat. Mengapa?
Saya melihat mereka sering diperlakukan sewenang-wenang dan
teraniaya. Tapi saya tidak mengingkari di antara mereka pun ada
pencuri dan perampok. Dan dalam film Gadis, hal itu saya
ceritakan dengan mengambil bentuk tontonan ketoprak. Saya sadar
bahwa upaya baru (ketoprak) tersebut beranjak dari selera
publik.
-- Nya Abas Akup.
GAGASAN sutradara kawakan itu ternyata belum tertuang dengan
kental -- sekalipun para pemeran Gadis sudah didandani busana
zaman Hindia Belanda. Mereka memang bermain dalam pengadeganan
gaya ketroprak, tapi tanpa jiwa matang.
Dalam film itu Jaka (Ray Sahetapi) dikisahkan diam-diam jatuh
cinta pada Rini (Cici Suryokusumo), anak Raden Mas Renggo (Dedy
Sutomo). Pada perkembanan berikut, Jaka -- anak ningrat itu --
ternyata lebih menyukai kepolosan Gadis (Dewi Yull). Ketika
itu Gadis berstatus sebagai babu di rumah denmas Renggo.
Terpaksa ia jadi babu karena ibunya, ibu Titik (Titiek Puspa),
menghilangkan seperangkat pakaian milik keluarga Renggo yang
dicucinya. Ibu Titiek, bekas istri seorang ningrat, hidup
bersama ketiga anaknya sebagai buruh pencuci.
Dan Rini, yang tak diindahkan itu, diam-diam bermain cinta
dengan Andi, teman Jaka, sampai hamil. Sementara cinta kedua
pasangan remaja itu berkembang, masyarakat di sekitar mereka
resah. Pemerintah Belanda, lewat Renggo, berniat mengambil alih
tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan. Kaum bawah yang
tertindas tadi, sambil menyimpan dendam, ramai-ramai mengungsi
ke rumah ibu Titik. Dan suatu malam, dengan parang dan tombak,
massa rakyat itu berusaha menghabisi Renggo.
Dalam perjalanan ke rumah Renggo itulah, seorang rakyat tanpa
sengaja membunuh Andi. Ketika itu, Jaka tengah berupaya
mengantar Rini dan Andi melarikan diri ke kota. Dan pada adegan
berikutnya Nya Abas tak lupa menyisipkan kritiknya.
Diperlihatkannya bahwa kaum bawah pun memiliki jiwa culas, tak
segan merampok dan menghabisi nyawa orang. Tapi berkat nasihat
ibu Titik, rakyat tidak jadi merampok dan membunuh Renggo Mereka
secara beramai-ramai malah berusaha membunuh seorang pejabat
Belanda, atasan Renggo.
Gadis ditutup dengan suatu kejutan, ditambahi teks (atas desakan
Badan Sensor Film), yang menyebabkan film itu brakhir di luar
harapan sutradara (lihat box). Adalah keliru jika mendekati
Gadis sebagai bentuk tontonan realisme. Hampir seluruh
percakapan dan pengadeganan di dalamnya, menurut Nya Abas Akup,
merupakan bentuk pengubahan gaya (stylize). Dengan cara itu, ia
berusaha menafsirkan kembali media film dalam konsep ciri
kebudayaan Indonesia -- seperti tontonan ketoprak Setting dalam
cerita film itu bukan merupakan soal pokok. "Soal feodalisme
(seperti dikemukakan Gadis) bisa terjadi di mana saja dan kapan
saja," katanya.
Tapi sebagai konsekuensi pengetoprakan film itu, para tokohnya
digambarkan secara hitam putih. Renggo merupakan cermin kaum
feodal, wakil kepentingan (penguasa) Belanda. Sedang ibu Titik
dan rakyat berada di seberangnya. Dalam gaya komedi (ciri Nya
Abas) dan stylize kesewenang-wenangan kaum feodal dan penguasa
ditonjolkan. "Dengan film itu, saya berusaha membicarakan
sebagian besar rakyat desa," kata Nya Abas.
DR. SITI PERTIWI KEMBALI KE DESA
Hampir setiap hari orang bicara soal pembangunan. Tapi banyak
orang lupa bahwa hal itu juga menyangkut perubahan nilai dan
mental. Dalam Dokter Siti Pertiwi Kembali Ke Desa, saya ingin
mengemukakan bahwa soal pembaharuan itu merupakan hasil benturan
nilai tradisional dan nilai modern. Untuk memperoleh resep
pembangunan, saya kira, kaum intelektual harus lebih banyak
mengenal lingkungannya.
-- Ami Prijono
KAUM intelektual (modern) dalam film Dokter Siti Pertiwi Kembali
Ke Desa diwakili Siti Pertiwi (Christine Hakim). Sementara Atuk
Raja (Maruli Sitompul), dukun tradisional dan Daying Madani
(Ikranegara) murid Atuk Raja, berada di pihak seberang.
Benturan nilai tradisional dan modern itu terjadi di Desa
Menggala, Lampung, tatkala Siti Pertiwi diterjunkan ke sana
sebagai dokter Inpres. Pada mulanya kelompok Atuk Raja menolak
konsep pengobatan modern. Dengan bekal pengetahuannya, Siti
Pertiwi berusaha meyakinkan Atuk Raja bahwa ilmu kedokteran
modern merupakan suatu alat ampuh .
Ketika Desa Menggala dilanda wabah muntaber -- karena sumur dan
sungai diracuni Daying Madani -- barulah Atuk Raja mau membantu
dokter itu mengatasi wabah. Sementara Siti dan Atuk sudah
melunakkan sikap, Daying Madani memisahkan diri secara sepihak.
Di situ sutradara Ami Prijono berusaha menunjukkan bahwa konflik
justru melahirkan suatu perkawinan harmonis kedua nilai itu.
Ditunjukkannya Atuk Raja justru tewas di tangan Daying Madani
sendiri. "Di film itu saya ingin menunjukkan bagaimana
sesungguhnya peranan kaum intelektual sebagai ujung tombak
pembangunan," ujarnya.
Dibanding filmnya terdahulu Jakarta-Jakarta, kali ini filmnya
lebih tangkas bertutur. Dengan pedas, Ami mengolok-olok sebagian
kelompok masyarakat tradisional yang keburu maju -- digambarkan
dalam sosok Kustiyah (Joice Erna). Didukung permainan para
pemeran yang bagus, film ini menawarkan suatu gagasan dan
wilayah baru. Setidaknya ia bukanlah film melodrama dengan
deraian air mata.
PEREMPUAN DALAM PASUNGAN
Dalam hidupnya, perempuan itu selalu terpasung. Film ini adalah
potret tentang perempuan Indonesia sebenarnya. Sederhana, lembut
dan penurut. Tapi kemudian retak dan rapuh karena diberi bingkai
yang terlalu kuat.
-- Ismail Soebardjo
PEREMPUAN Dalam Pasungan sebagaimana dikatakan sutradara itu
memang bercerita secara kilas balik tentang kesewenang-wenangan.
Tapi, Ismail Soebardjo, 37 tahun, sutradara dan penulis
skenarionya, tak terjebak oleh sentimentalitas yang
meletup-letup. Nadanya tetap rendah dan juga tak menggurui.
Fitria (Nungky Kusumastuti) -- oleh ayahnya, Prawiro (D.
Djajakusuma) - disangka gila. Perempuan itu memang sedang
terguncang jiwanya oleh perasaan berdosa: merasa membunuh Marni
(Rini S. Bono), sahabatnya.
Ia dipasung dan disekap dalam kamar di rumah ayahnya di sebuah
kampung di Yogyakarta supaya tidak bikin malu keluarga. Tapi
rahasia itu lantas diketahui seorang wartawan Jakarta (Dorman
Borisman). Sang wartawan mencari Andi (Frans Tumbuan), suami
Fitria, yang berada di Jakarta, dan meyakinkannya bahwa istrinya
tidak gila. Andi -- bersama Tini, anaknya, dan wartawan itu-lalu
datang menengoknya.
Meskipun memang tidak gila, ternyata Fitria menolak kehadiran
suaminya yang telah membiarkannya dizalimi begitu. Pun Tini,
yang menghambur ke arahnya sambil menangis, tak diindahkannya.
Sikap itu barangkali menunjukkan protesnya yang keras dan getir
terhadap kesewenang-wenangan keluarga - atau lingkungannya.
Film ini banyak kelemahannya dalam detil . Mungkin karena
sutradaranya terlalu terpaku pada temanya yang dramatis.
Meskipun begitu, film ini menunjukkan juga kemajuan Ismail
sebagai sutradara. Sehinggga boleh pula ia diperhitungkan.
USIA 18
Saya hanya mengetengahkan persoalan yang 'biasa'. Memang, saya
ingin mengatakan sesuatu. Tentang para remaja. Tapi dengan cara
sederhana saja.
-- Teguh Karya
EDO (Diyan Hasri), 18 tahun, ditinggal mati ayahnya. Ia
terpaksa berhenti kuliah dan bekerja di bagian mesin di bengkel
kereta api -- pekerjaan yang sama dengan pekerjaan mendiang
ayahnya. Sebab ia harus membantu ibu dan ketiga orang adiknya.
Adalah Ipah (Yessy Gusman) -- gadis sebaya, pacar Edo -- yang
menyebabkan si cowok tetap memiliki semangat. Untuk suatu ketika
bisa kuliah lagi.
Ayah Ipah (Zaenal Abidin, duda) adalah kawan ayah Edo. Sebagai
orang mampu -- direktur sebuah biro perjalanan - ia ingin
membantu Edo. Tapi entah bagaimana juntrungnya, tiba-tiba Edo
digambarkan sangat tersinggung oleh uluran tangan itu.
Rasa sakit hati -- yang tak jelas -- itu kemudian ternyata
menjadi sebagian dari konflik yang ingin dikembangkan Teguh
Karya, sutradara dan penulis skenario film Usia 18 itu. Karena
itu, kurang meyakinkan. Di samping, pada dasarnya ceritanya tak
memiliki konflik yang berarti yang bisa membangun situasi
dramatik. Mudah dibayangkan, bagaimana jadinya sebuah cerita
tanpa konflik.
Tak usah disangsikan, Teguh Karya adalah sutradara yang sudah
terbukti memiliki banyak kelebihan. Kekurangannya agaknya hanya
satu itu -- sebagaimana juga terlihat dalam filmnya terdahulu
November 1828. Ia tak bisa menciptakan konflik dalam cerita
bikinannya sendiri.
Sehingga yang muncul hanya sekedar kerapian dan potret
meyakinkan dari suatu ketrampilan kerja teknis saja. Apa yang
ingin dikatakan Teguh lewat kedua remaja itu pun jadi kabur.
Yang menonjol malah suasana percintaan bagai dalam mimpi
pubertas. Indah, damai dan penuh kesetiaan.
Sayang. Padahal, dalam film terbarunya ini, Teguh masih terlihat
sanggup memberi pengarahan akting yang hidup pada para
pemainnya. Sofia WD misalnya yang memainkan tokoh nenek dalam
film ini cukup patut diperhitungkan untuk sebuah Citra.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini