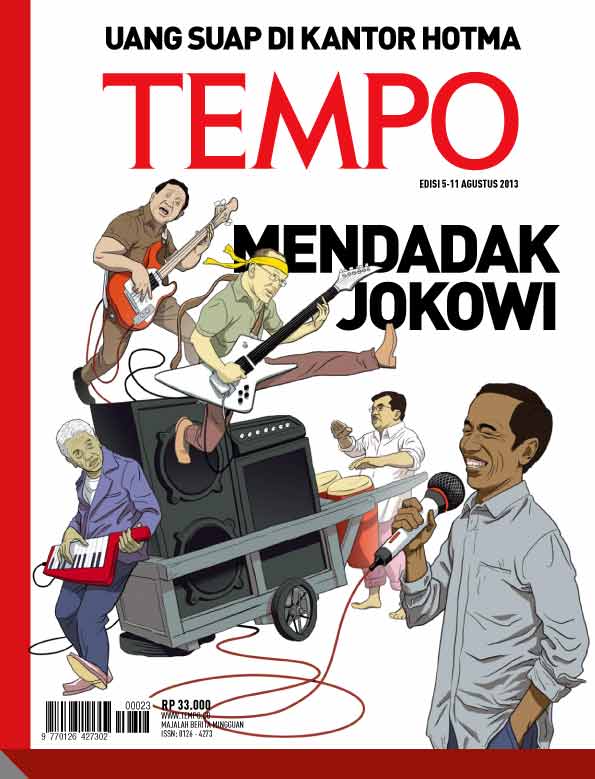Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang Menunggu dengan Payung
Penulis: Zelfeni Wimra
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Cetakan: I, Maret 2013
Tebal: 148 halaman
Kisah-kisah dalam kumpulan cerpen Yang Menunggu dengan Payung karya Zelfeni Wimra berdenyut di ruang penantian. Kendati yang dinanti tak bakal datang, iman penantian justru kian teguh. Inilah lelaku Rahma dalam cerpen yang dipilih sebagai judul buku.
Saban hari ia menanti kedatangan Ayah dan terus meyakinkan Ibu bahwa pada suatu hari yang hujan, dari ujung jalan, ia akan menuntun ayahnya pulang dengan payung. Juga menunggu Rahman, yang berjanji segera pulang dari rantau untuk menikahinya. Tapi, sebelum kedatangan Ayah, sebelum Rahman tiba, kampungnya diguncang gempa. Ratusan orang tertimbun reruntuhan, termasuk Rahma dan ibunya. Penantian Rahma terbawa sampai mati.
Penantian selanjutnya: lelaki pembuat gula merah dalam Suara Serak di Seberang Radio. Saat nira mendidih, ia selalu menyalakan radio dan tak pernah pindah gelombang dari acara Kotak Pos. Suara serak penyiar membacakan kartu pos dari pendengar telah menjadi kegemarannya. Yarman mengirim dua kartu sekaligus. Satu untuk dibacakan, satu lagi khusus untuk penyiar bersuara serak. Tapi acara itu kemudian tak mengudara lagi. "Orang-orang lebih suka mengirim pesan singkat dengan telepon genggam" (halaman 37).
Penantian Yarman adalah perjumpaan dengan penyiar bernama Ratna. Lagi-lagi adalah soal penantian tak bermuara. Namun, hanya dengan lelaku penantian, Yarman riang dalam sendiri. Ratna juga sedang menanti sesuatu: kesempatan berkunjung ke sebuah dangau di hulu Batangmaek, tempat Yarman lapuk digasak sepi. Siapa sesungguhnya yang menanti? Keduanya telah menjadi subyek sekaligus obyek penantian. Perjumpaan Yarman-Ratna tak pernah terjadi, tapi bukankah hidup akan lebih berdenyut bila ada sesuatu yang dinanti?
Lain pula dengan penantian Nining, perempuan tunarungu dalam Layang-layang Bulan (halaman 57). Ia menanti perjumpaan dengan kawan masa kecil, Gugun, teman bermain layang-layang di sebuah terminal regional yang telah berubah menjadi mal. Nining menapaktilasi puing kenangan dan ingin berjumpa kembali dengan Gugun. Tapi Gugun sudah pergi dari kampung. Lelaki dambaan Nining itu bahkan dikabarkan telah menjadi liar. Hidupnya tergadai pada seorang perempuan yang membiayai sekolahnya, hingga ia harus mengabdi pada perempuan itu. Tak ada lagi cerita tentang layang-layang masa kecil, tapi Nining tiada henti menanti.
Ungkapan-ungkapan prosaik Wimra melenting-lenting, bahkan dalam beberapa bagian terasa tegang. Cerpen Di Atas Dipan Penantian, misalnya. Gadis yang terbaring sakit terasa seperti orang sehat berstamina prima. Alih-alih soal ringis kesakitan, yang mengemuka justru kelisanan yang menyala-nyala. Bila sebuah cerita dapat diamsalkan dengan ikan dalam kuali, ada kalanya ia digoreng tak terlalu garing, agar bumbu meresap sempurna. Ungkapan yang melenting-lenting ibarat menggoreng ikan terlalu garing, hingga berisiko menjadi kerupuk ketimbang ikan.
Wimra akrab dengan simbol terminal, tempat orang-orang datang, singgah sejenak, untuk kembali pergi. Bukan hanya terminal spatiotemporal, melainkan juga terminal artifisial. Cerpen Terminal Dua Kepulangan, misalnya, tentang imam masjid terminal yang meninggal tanpa dihadiri sanak-saudara. Ya, "terminal" dalam cerpen itu bermakna ganda: pulangnya seorang manusia ke alam baka, dan pulangnya seorang anak setelah mendengar kabar ayahnya meninggal.
Wimra merancang alegori: dunia sebagai terminal. Semua hasrat penantian menjadi perhatian pokoknya, seperti orang-orang yang menunggu di terminal. Hanya menunggu orang-orang singgah, bukan yang sungguh-sungguh pulang. Setelah mampir, mereka menyandang ransel untuk berangkat kembali.
Di Payakumbuh—kampung halaman kepengarangan Wimra—bila seorang perantau mudik, pada hari pertama ia akan disambut gembira, di hari kedua diajak berbicara dan disuguhi segala macam hidangan, tapi pada hari ketiga biasanya akan ditanya, "Kapan balik ke rantau?" Padahal, lantaran rindu atau karena sulitnya hidup di negeri orang, belum tentu ia akan kembali. Lama dinanti, tapi bila sudah tiba, lekas ditanya kapan bakal pergi kembali. Maka yang dinanti-nanti sesungguhnya tak pernah datang. Kalaupun tiba, bukankah ia akan pergi kembali? Kampung halaman telah beralih rupa menjadi terminal belaka.
Damhuri Muhammad, esais, penyuka fotografi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo