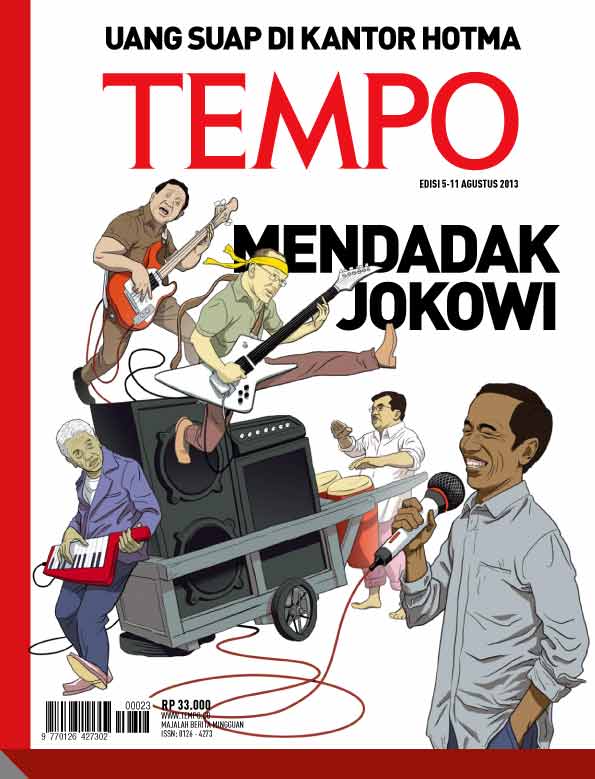Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pameran "Kuota" dari Langgeng Art Foundation, pada awal penyelenggaraannya, memposisikan diri menampilkan karya-karya terbaik seniman Indonesia selama kurun satu-dua tahun terakhir. Proyek pertamanya dapat dikatakan sukses dengan mempresentasikan capaian—baik visi artistik maupun konsep dan isu karya—dari seniman Indonesia, terutama, pada waktu itu, di tengah ingar-bingar pasar yang sedemikian dominan.
Mencapai empat tahun penyelenggaraannya, bahkan dimulai semenjak serinya yang ketiga, Kuota tampaknya sedikit mengubah haluan dengan memperdalam observasinya terhadap kecenderungan tertentu dalam karya dan pameran yang dibuat seniman Indonesia. Dengan memberikan pembacaan terhadap kecenderungan ini, proyek Kuota dengan sendirinya menjadi punya semacam bingkai tema dan tawaran diskursus, alih-alih menampilkan "semata-mata" karya terbaik para seniman.
Kurator pameran Kuota, Hendro Wiyanto, pada periode 2011-2013 melihat bahwa para seniman gemar mengulang, memecah, membuat seri bentuk, memodifikasi, atau mereproduksi bentuk-bentuk tertentu, sehingga karya-karya itu terlihat sebagai "kepingan". Untuk menunjukkan kecenderungan ini, Hendro memilih karya dari delapan seniman, yaitu Agan Harahap, Albert Yonathan Setiawan, Anang Saptoto, Aminudin T.H. Siregar, F.X. Harsono, Maria Indria Sari, Nasirun, Theresia Agustina, dan Tromarama. Pameran dibuka pada 3 Juli lalu dan berlangsung hingga akhir Juli 2013.
Memasuki ruang pamer Langgeng Art Foundation di Yogyakarta yang lapang, pengunjung langsung dihadapkan pada modus display yang bersih dan teratur, sehingga pamerannya terkesan rapi dan cantik. Ini sangat berbeda dengan pameran Kuota #3, yang lebih terasa bermain dengan bentuk dan tata ruang, ketika Hendro Wiyanto pada waktu itu justru menyajikan beberapa karya yang terpotong atau tak utuh.
Karya F.X. Harsono, Monumen Bong Belung, seperti menyambut pengunjung dalam ruang pamer, langsung masuk ke suasana yang kontemplatif dan ajakan untuk menelusuri masa lalu. Karya ini sebelumnya dipamerkan dalam Pameran Indonesian Contemporary Arts di Museum of Contemporary Arts Roma (MACRO), Italia. Karya ini berfokus pada kisah pembunuhan massal orang-orang Tionghoa di Blitar pada periode 1947-1948, sehingga dalam instalasi ini kita bisa menemukan nama-nama mereka yang menjadi korban. Dalam karya Harsono, strategi mengulang tampaknya menjadi cara untuk membangkitkan teror ingatan, menggugah kembali apa yang telah dilupakan.
Sama-sama membicarakan ingatan dan sejarah, karya Tromarama, Ons Aller Belang, mengambil pendekatan artistik yang lebih ringan. Menelusuri sejarah Kota Bandung, terutama berkaitan dengan lanskap kota, ia mencetak kepingan masa lalu dalam 30 piring keramik bermotif kolonial dan kemudian di pusat komposisi piring yang melingkar itu mereka menampilkan video stop motion. Citra gambar Tromarama kali ini lebih bersifat fotografis, sehingga lebih punya asosiasi pada yang nyata tentang kota pada masa itu.
Theresia Agustina menampilkan tiga seri gambar terbarunya yang menggunakan teknik cetak, dipresentasikan dalam bentuk buku yang terbuka, digelar di atas meja. Dua seri gambar merupakan bentuk semacam sketsa dari perahu—proyek panjang Tere tentang perahu Nuh—dan satu seri lagi menampilkan sketsa figur manusia. Cara presentasi Tere memberi kesan instalatif pada karya dua dimensi, pada saat yang sama juga memungkinkan karya gambar memiliki kesan puitis.
Pesan puitis yang sama bisa ditemukan pada karya Maria Indria Sari, Postpartum Syndrome 2: Dijemur, yakni sebuah instalasi terdiri atas sembilan boneka kain dengan jubahnya yang memberi asosiasi pada tubuh perempuan, menarasikan trauma tubuh perempuan atas pengalaman melahirkan. Menurut Hendro Wiyanto, strategi repetisi ini digunakan Maria untuk "menampilkan situasi kedirian yang traumatik", atau dengan kata lain menceritakan kisah personal secara berulang untuk keluar dari situasi itu sendiri.
Sedangkan Nasirun dan Aminudin T.H. Siregar menyuguhkan karya yang berbasis pada humor kritis, bahkan lebih cenderung sinis, tentang fenomena-fenomena seni hari-hari ini. Karya Nasirun, Uwuh Seni, sebelumnya dipamerkan di Galeri Salihara, terdiri atas 186 kepingan gambar dalam pigura yang merupakan gambar dan kolase dari ribuan undangan pameran yang datang setiap hari. Bagi kebanyakan orang, undangan-undangan seperti ini dengan segera masuk ke tong sampah, atau bagi yang lain masuk sebagai bagian dari arsip. Nasirun melihatnya sebagai sesuatu yang bisa merujuk pada praktek berkeseniannya, menjadi material baru yang penuh dengan tanda dan sejarah.
Adapun Aminudin T.H. Siregar aka Ucok memajang karyanya, Seni Rupa Idiot, yang memainkan simbol gambar dari sampul buku terkemuka, seri Introduction for, yang gampang diingat banyak orang. Sebagaimana tulisan Ucok yang bertebaran di media massa, dalam karya ini kita pun melihat bau sinisme Ucok terhadap pola relasi kekuasaan dalam dunia seni rupa, ketegangan antara seniman, sejarah, pasar, dan sebagainya.
Sebagaimana yang sempat saya singgung di awal tulisan ini, tampilan visual pameran ini memang tampak bersih dan cantik. Karya-karya para seniman, mungkin berangkat dari kecenderungannya yang repetitif, membuat kita melihat pola perulangan tertentu, dengan variasi di sana-sini, dan mengarahkan bingkai pameran ini ke persoalan bentuk (meskipun bukan melulu formalisme yang sedang ditunjuk Hendro). Tentu saja, berkaitan dengan wacana soal repetisi, kepingan dan reproduksi ini telah menjadi bagian penting dalam wacana seni rupa kontemporer. Tapi, pada satu sisi, menikmati pameran ini saya merasa kurang dientak oleh isu yang ditampilkan para seniman.
Barangkali, dengan mengulang, membagi dalam kepingan, dan mereproduksi, para seniman ini menjadi lebih terpaku pada soal produksi itu sendiri ketimbang memperkuat diskursus karyanya, atau memang dengan strategi repetisi ini "konten" seperti diredam. Kita digiring untuk menikmati kepingan narasi, kadang terpotong dan acap saling berkait, tapi karya-karya ini cenderung dingin dan kurang daya untuk menyampaikan gagasan dasarnya.
Alia Swastika, kurator
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo