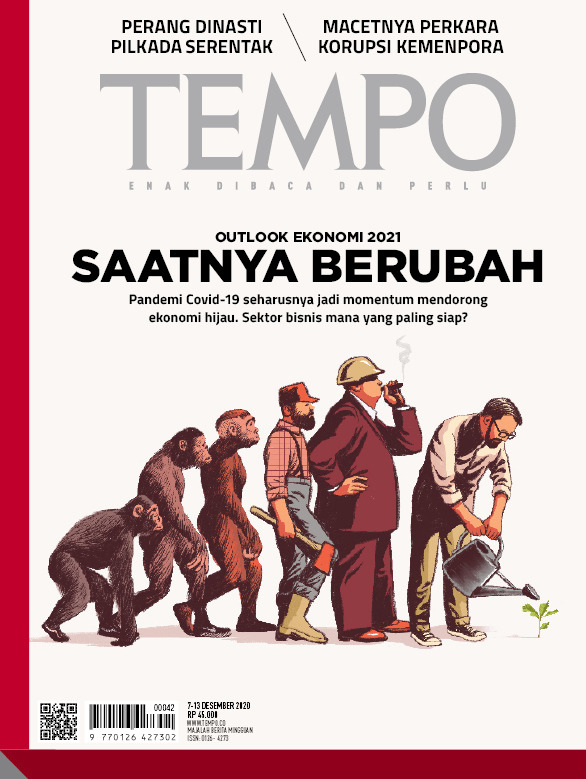Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NAMA? Umur? Warna favorit? Apakah kamu makan gula? Garam? Partai politik? Menjadi anggota organisasi? Apa yang kamu lakukan tadi pagi? Di mana kamu kemarin? Kebangsaan? Serentetan pertanyaan itu dicecarkan interogator kepada warga Uruguay yang dicurigai rezim militer dalam naskah drama Waktu Tanpa Buku karya Lene Therese Teigen. Jawaban yang ditulis Teigen atas bombardemen pertanyaan itu bisa apa saja, tergantung tempat naskah dimainkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nama Lene Therese Teigen, dramawan Norwegia kontemporer, mendadak muncul di jagat teater kita. Bila saja Faiza Mardzoeki tak menerjemahkannya, pengetahuan kita akan naskah Norwegia masih berhenti hanya pada Henrik Ibsen, dramawan realis Norwegia abad ke-19 yang karyanya sudah banyak dipentaskan di sini. Naskah Waktu Tanpa Buku baru dibuat pada 2017. Faiza mendapat kepercayaan Teigen untuk menerjemahkan dan memanggungkannya. Naskah ini bercerita tentang masa ketika Uruguay dikuasai junta militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini


Sosok anak yang ditampilkan dalam Waktu Tanpa Buku yang ditafsirkan sutradara Ruth Marini dari naskah drama karya Lene Therese Teigen. Dokumentasi Ruang Kala/Institut Ungu Media
Rezim diktator militer di Uruguay dimulai tatkala Presiden Juan Maria Bordaberry memerintah pada 1973. Jendral Gregorio Álvarez, yang amat berperan dalam kudeta militer 1973, selanjutnya menggantikan Bordaberry selama 1981-1985. Pada masa pemerintahannya, terjadi banyak penyiksaan dan pembunuhan. Ribuan orang dipenjarakan karena alasan politik. Ratusan aktivis diculik. Bahkan pada 1978 Álvarez mengeksekusi para aktivis kiri Uruguay yang ia asingkan di Argentina. Pada zaman Álvarez, banyak pelarian Uruguay yang mencari suaka ke Norwegia. Lene There Teigen mewawancarai mereka. Naskah ini berisi kolase kenangan buruk mereka akan lorong-lorong penjara, sel-sel, dan ketidaktahuan generasi muda milenial masa kini mengenai peristiwa keji itu. Naskah ini berat karena seorang aktor dituntut memerankan karakter berbeda-beda, bahkan bisa sampai empat karakter.
Faiza memilih lima sutradara teater perempuan dan memproduseri mereka untuk membuat teater-film. Jarang ada satu karya yang sama ditafsirkan oleh lima sutradara sekaligus dalam satu pertunjukan. Ternyata gagasan ini menarik karena mampu menimbulkan keberagaman pendekatan. Di tangan sutradara Ruth Marini, naskah sepenuhnya menjadi sebuah film. “Tatkala membaca naskah Teigen, saya langsung membayangkan sebuah film,” ujar Ruth. Ruth menghasilkan sebuah film yang pekat tapi dalam. Demi keutuhan dan kesolidan, Ruth “merombak” struktur naskah Teigen agar sesuai dengan logika sebuah film. Dia tidak menampilkan naskah secara persis benar.

Waktu tanpa buku yang disutradarai Heliana Sinaga bersama Mainteater Bandung, dari naskah Waktu Tanpa Buku karya Lene Therese Teigen. Dokumentasi Mainteater Bandung/Institut Ungu Media
Adegan dimulai dengan seorang perempuan yang pernah mengalami siksaan menulis di hadapan mesin tik, menumpahkan ingatan-ingatan buruknya (dimainkan Ruth sendiri dengan rambut pendek). Di meja, terhampar foto korban lain. Ada suara detak jam. Kemudian kolase monolog. “Saya menghadirkan montase-montase peristiwa di antara adegan satu dan adegan lain agar penonton secara visual tidak terputus,” ucap Ruth. Dan itu diisi kilatan-kilatan tubuh yang meringkuk di dalam jeruji dan narasi ketikan.
Maryam Supraba memainkan dua karakter, dua penampilan yang sangat berbeda. Menjadi Sofia, ia mengenakan wig; menjadi Lydia, ia mengurai rambutnya. “Saya ingin Maryam tidak hanya mengubah suara atau gestur. Namun secara fisik penampilannya berubah,” ujar Ruth. Sebagai Sofia, ekspresi Maryam penuh kegugupan, ia seolah-olah diburu ketakutan akan suara-suara pintu yang ditutup. Tiba-tiba ia berteriak ketika mendengar pintu berderit. Sedangkan sebagai Lydia dia mengenang bagaimana mengajak anaknya menjenguk ayahnya di penjara dengan membawa boneka teddy bear.
Bagian interogasi disajikan secara tak terduga. Ruth menampilkan interogator berupa sesosok anak kecil perempuan—sesuatu yang tak ada dalam naskah. Mula-mula kamera menampilkan langkah seseorang perempuan bersepatu merah dengan hak tinggi. Tak, tak, tak. Ternyata itu suara kaki seorang bocah kecil (Luna Allegra). Ia membawa pot dengan setangkai bunga. Ia lalu meletakkan pot itu di depan lelaki yang ditangkap. Ia duduk di kursi yang terlalu besar untuknya—dan mulai mengajukan pertanyaan.

Faiza Mardzoeki. Dokumentasi Pribadi
“Saya membayangkan siksaan mental yang paling berat adalah jika interogator mengancam akan membunuh anak dan keluarga dari sosok yang tertangkap. Karena itu, untuk sosok interogator, saya tak menghadirkan polisi atau tentara yang kejam, tapi anak kecil,” tutur Ruth. Menurut Ruth, anak itu merupakan alegori, seolah-olah pertanyaan datang dari batin aktivis sendiri. Adegan interogasi membuat film terasa sublim, estetis, dan tak hanya jatuh seperti dokumentasi pengakuan. Ruth bersama Teater Ruang Kala—lembaga studi akting untuk aktor dewasa dan anak-anak yang dipimpinnya di bilangan Blok M, Jakarta—membutuhkan 39 menit untuk durasi pementasan. Pada adegan akhir, kita melihat siluet tiga orang dengan kepala dikudungi digantung di balik jeruji.
Akan halnya Heliana Sinaga bersama Mainteater, Bandung, membutuhkan waktu dua jam. Heliana memainkan naskah secara lengkap. Baik struktur maupun dialognya persis seperti dalam naskah asli. Heliana mempertahankan unsur auditorium. Kita melihat sebuah panggung dengan lantai penuh serakan koran dan properti berupa boks tempat duduk. “Naskah Lene sebenarnya tak membahas persoalan Uruguay secara verbal. Dia bersifat universal. Dari situlah saya berpikir bagaimana memunculkan peristiwa yang terjadi di sini melalui tanda-tanda, tanpa didramatisasi,” kata Heliana.
Dan tatkala kamera sedikit men-zoom koran-koran, kita bisa membaca surat kabar (berfungsi sebagai tanda) itu menampilkan berita tentang kasus orang hilang sampai demonstrasi 1998. Segera kita tahu bahwa pemaknaan hal yang dibicarakan di panggung mengarah ke sejarah kita sendiri. Cara Heliana menyajikan monolog Maria menarik. Maria dalam naskah adalah sosok yang saat ditangkap digelandang melewati lorong-lorong dan melihat tubuh-tubuh perempuan telanjang digantung seperti binatang.
Pada bagian pertama, tatkala Maria bercerita bagaimana ketika lari ia tinggal di asrama bersama perempuan-perempuan tua, Heliana menyajikannya dengan mengetik seolah-olah memberikan kesaksian lewat tulisan. Gelisah, dengan berkali-kali mengisap rokok kuat-kuat, apa yang ditulisnya ditayangkan di layar. Dan tatkala ia mengisahkan bagaimana Maria setelah dicokok berjalan menuju sel melewati kamar-kamar penuh mayat perempuan, di belakangnya ada tiga sosok perempuan bergaun putih dengan posisi digantung. Heliana bayak bermain dengan semiotik. “Semiotik adalah hal penting tinimbang hal-hal teknis,” ucapnya.
Sementara pada karya Ruth dan Heliana terasa ruang seperti sebuah ruang klaustrofobik—ruang sempit yang gelap mencekam—Agnes Christina, sutradara Yogyakarta, memilih adegan-adegannya berlangsung di ruang lapang terbuka hijau. Sebuah keluarga—ayah, ibu, anak, dan tante—diperlihatkan menggelar kain, duduk-duduk bertamasya di rerumputan nan segar. Suasana yang awalnya hangat berubah ketika ayah-ibu dan tante mendengar sang anak baru saja membeli barang dari pusat belanja. Pusat belanja itu dulu adalah penjara tempat menyiksa mereka—dan sang anak tak tahu. Jamaludin Latief, yang berperan sebagai ayah, tampil mengesankan. Apalagi ketika ia muntab menjawab pertanyaan anaknya. Siapa namamu? Jamal. Pekerjaan? Seniman. Seniman favorit? Affandi. Sering olahraga? Dua kali seminggu. Christina memadatkan banyak dialog dari naskah dalam adegan tamasya itu. Regina Gandes Mutiary sebagai tante menampilkan monolog Maria secara berbeda dengan aktris lain. Ia berbaring di rerumputan. Menerawang ke atas. Tertawa-tawa sendiri. Setengah sinis, getir mengingat tubuh-tubuh telanjang yang dibunuh.
Sebagaimana Heliana, pentas Ramdiana dari Aceh dan Shinta Febriany dari Makassar memilih bentuk panggung. Karya Ramdiana dimulai dengan lantunan ratapan seperti didong—kesenian rakyat Aceh. Bagian interogasi langsung mengingatkan kita pada masa-masa Aceh di era Daerah Operasi Militer. Seorang janda mengenakan kerudung diinterogasi suara anonim. Alamat kamu? Status? KTP Merah Putih punya? Tadi pagi di mana?
Sedangkan Shinta menggabungkan performance, gerak, dan dramatic reading. Beberapa kursi ditata di sebuah ruang yang cenderung putih steril. Di samping ada semacam bar dengan boneka-boneka. Para aktor membacakan teks monolog sembari bergantian berdiri-duduk-jatuh. Cara Shinta mengelola ritme adegan duduk, berdiri, dan jatuh ini tak membosankan. Klimaksnya adalah tatkala mereka menari tango bersama. Dalam naskah asli, tango ditampilkan dalam pembicaraan akhir antara Rita dan Maria tentang kematian sembari mengingat adegan orang tua mereka di masa mereka kecil sering berdansa. Dalam karya Heliana, adegan tango ditampilkan sebagai penutup selintas—fade out dan menghilang. Sedangkan dalam pertunjukan Shinta, tango menjadi akhir yang artistik tapi getir.

Waktu Tanpa Bukua karya Lene Therese Teigen yang diterjemahkan Faiza Mardzoeki.
Dibanding terjemahan novel Amerika Latin seperti karya Gabriel García Márquez dan Mario Vargas Llosa, naskah teater bertema Amerika Latin masih jarang di sini. Beberapa tahun lalu, Teater Satu Lampung mementaskan terjemahan Death and the Maiden karya Ariel Dorfman yang mengisahkan pemerkosaan para aktivis di zaman junta Augusto Pinochet di Cile. Pada 1970-an, W.S. Rendra pernah menyajikan Paraguay Tercinta karya dramawan Austria, Fritz Hochwälder (judul asli: The Strong are Lonely), yang mengisahkan perlawanan para Jesuit di Paraguay terhadap kolonialisme—sebuah naskah yang tak pernah lagi dimainkan di sini sesudah Rendra.
Sekarang hadir sebuah terjemahan baru, naskah mengenai Uruguay. Kita tahu, dalam satu perjanjian yang diberi nama Plan Condor, penguasa di Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Brasil, serta Bolivia bertukar informasi tentang orang-orang yang dicari dan diburu untuk dibunuh pada 1970-an dan 1980-an. Dan kini, dengan membayar tiket Rp 50 ribu, selama 1-10 Desember 2020 kita bisa mendapat kiriman buku terjemahan Waktu Tanpa Buku dan menyaksikan sekaligus lima pertunjukan teater online yang kisahnya bertolak dari pakta keji itu.
SENO JOKO SUYONO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo