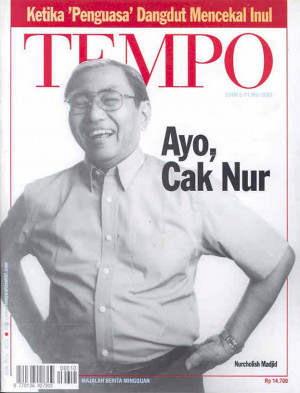Media Dan Konflik Ambon
Penulis : Eriyanto
Penerbit : Kantor Berita Radio 68H
Cetakan : Pertama, Februari 2003
Tebal : xiii + 190 halaman
Membaca buku ini, Anda akan menyadari compang-campingnya pengelolaan media massa dan keterbatasan kemampuan jurnalistik para wartawan di daerah konflik. Mereka terseret: jadi korban, bahkan secara tak sadar jadi "pelaku" konflik —sehingga konflik itu sendiri jadi lebih lama dan lebih banyak korban. Barangkali inilah pesan dan refleksi yang dapat ditarik dari buku telaah media dan konflik di Maluku ini.
Konflik tersebut berkepanjangan empat tahun dan menewaskan puluhan ribu orang. Ada rasa solidaritas dan dukungan yang harus disampaikan untuk para wartawan yang rumahnya terbakar, yang anak-istrinya mengungsi, atau yang saudara dan kampungnya diserang. Tapi itu semua membuat mereka tak sanggup meletakkan diri dengan baik di tengah konflik. Apa boleh buat, kini dibutuhkan lebih banyak lagi untuk membangun kembali media andal, tahan, dan mahir menghadapi konflik berdarah dalam sebuah masyarakat plural. Apalagi harapan kerap ditimpakan pada media massa.
Ada argumen tentang ketidakmampuan mengambil jarak (hlm. 35) atau ketidaksiapan menghadapi konflik yang begitu cepat memisahkan warga Islam dan Kristen (hlm. 187) untuk menjelaskan sikap wartawan. Tapi efek bentrokan semakin buruk. Pada tahap lanjut, media lokal tak tahan lagi melawan konflik batin para wartawannya. Secara efektif, dalam arti luas, mereka sudah jadi "pelaku konflik". Wartawan tak meliput ke lapangan, tapi menulis, memberitakan secara emosional, sepihak, tanpa check-recheck, tak bisa diverifikasi kebenarannya, sumber tidak kredibel, dan sumber fiktif (Bab VII).
Perang berita berkobar. Kesenjangan informasi yang bertahan sepanjang konflik semakin memperuncing situasi. Pada kenyataannya, pembaca dan pendengar sulit membedakan peran buruk media dalam konflik dari segi jenisnya. Efek media tulis tak sehebat media elektronik. Suara Perjuangan Muslim Maluku (SPMM) milik Laskar Jihad adalah contoh media yang menaikkan produksi hormon adrenalin pendengarnya—tak hanya warga Kristen, tapi juga muslim. Menyebut terbelahnya Suara Maluku dan Ambon Ekspres jadi koran Islam dan Kristen sebagai "perpecahan (internal)" tentu melalaikan kenyataan bahwa perang berita di antara para wartawan itu adalah "konflik yang serius".
Perjanjian Malino II untuk penyelesaian konflik Maluku juga menunjukkan problematik dan prospek media lokal. Dari 10 poin, tak ada satu pun yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, pemberitaan, peranan media. Lalu, kalangan media sendiri tak jadi peserta proses menuju perjanjian. Padahal jelas pula, tanggung jawab publik media tak hanya merupakan tugas pekerja media, tapi sebenarnya juga tugas pemerintah. Alih-alih mendukung, pemerintah darurat sipil malah lebih sering mengancam bredel.
Risiko menggunakan tolok ukur ini adalah bahwa media menegaskan subordinasinya pada penguasa, lupa akan fungsi kontrol terbuka. Orientasi ini dapat mengaburkan kepada siapa sebenarnya tanggung jawab media massa ditujukan. Hak masyarakat atas informasi dan keseimbangan kekuatan mereka seharusnya jadi ukuran utama memandang peran media massa, apalagi dalam konflik. Setidaknya keseimbangan ini selayaknya jadi pedoman sinergi kinerja para pekerja informasi dan pengetahuan publik.
Sebagai alat bantu terakhir, buku ini membandingkan praktek media di Maluku dengan kejadian di Rwanda dan Yugoslavia. Tapi komparasi ini jadi meleset karena hanya persamaan jenis konfliknya yang jadi dasar (konflik etnis), belum lagi memperbandingkan dengan faktor agama yang lebih kuat dan lebih condong dipandang sebagai "tak dapat ditawar-tawar" (unnegotiable). Menyamakan kulit jeruk dengan kulit durian, misalnya, bukan pandangan yang tepat. Salah-salah kita akan berpendapat bahwa tragedi kemanusiaan di Maluku masih dapat ditoleransi.
Di satu sisi, memandang kenyataan pahit dengan kacamata kritis tak kurang juga provokatif dan tampaknya kurang menyemangati untuk maju. Tapi buku yang merupakan refleksi laku surut ini menjadi secercah harapan bagi kemajuan media lokal di kawasan konflik. Yang tak belajar dari sejarah akan dikutuk karena mengulangnya. Dan media bagaikan napas masyarakat, selayaknya didukung. Jika tidak, pelajaran praktek media dari Maluku ini tampaknya masih menggantung dan belum tuntas.
Prasetyohadi, pemerhati berbagai konflik di Tanah Air
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini