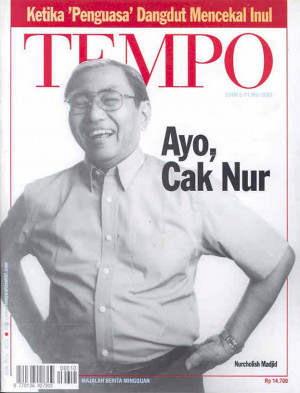Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari ini saya teringat Samadi, seorang laki-laki kurus yang kini mungkin sudah tak ada lagi, karena 16 tahun yang lalu itu umurnya 60, dan ia miskin, dan ia terdesak.
Sebenarnya ia punya sepetak pekarangan dan sepetak sawah di Desa Nglanji, di Kecamatan Kemusu, Boyolali. Tapi pada tahun 1987 itu ia harus melepaskan miliknya. Ia hidup di wilayah Kedung Ombo.
Sejak 1969 Negara telah memutuskan, sebuah waduk besar akan dibangun di wilayah itu. Sungai Serang, 90 kilometer di tenggara Semarang, harus dibendung. Petani yang bertahun-tahun hidup di wilayah seluas 37 desa di tiga kabupaten itu harus dipindahkan. Mereka tak akan disia-siakan, kata Negara, sebab ada ganti rugi. Wilayah baru juga disediakan.
Tapi Samadi menolak. Ia salah satu dari 1.700 kepala keluarga yang ingin bertahan.
Bertahan, melawan—kata itu sama, sebab di masa itu kehendak pemerintah tak bisa dibantah. Presiden sendiri menyebut sikap Samadi dan para tetangganya yang tak bersenjata itu ambaléla, memberontak. Sebab, Negara berniat baik, kata presiden sampai para lurah. Negara ingin memperbaiki sistem pengairan sawah ladang di wilayah itu, yang miskin, yang tanahnya kuning berkapur, dan hasil padinya hanya empat ton tiap hektare.
Tapi Samadi menolak.
Di atas, orang bertanya, kenapa. Saya ingat ada seorang penduduk yang menjawab, "Karena para petugas kelurahan memaksa kami." Para petugas itu datang ke rumah-rumah, dan para petani disuruh cap jempol menyatakan setuju menerima uang ganti rugi dan siap pergi bertransmigrasi. Kalau tidak, mereka dibentak-bentak, bahkan dipukuli.
Juga Samadi. Ia mencoba menolak untuk menerima uang ganti rugi, tapi pada suatu hari ia digiring ke kantor Koramil. Di hadapan camat, muka orang tua itu digampar. Laki-laki berumur 60 tahun itu menyerah. Ia membubuhkan cap jempol persetujuan, dan melepas pekarangannya yang seluas 2.700 meter persegi untuk ditukar uang Rp 1,5 juta.
Ia memang masih menyimpan sepetak sawah dan sebuah gubuk yang tak diungkapkannya kepada orang-orang kelurahan. Di sanalah ia bertahan. Dan di sanalah dipasangnya sehelai Merah Putih di tiang setinggi 10 meter. Tiap pagi ia memandang ke bendera itu. Dengan cara itu, katanya, "Saya masih bisa merasa mempunyai negeri."
Hari ini saya teringat bendera dan kalimat sedih petani miskin itu: "supados taksih ngrumaosi nggadhahi nagari". Ada tiga patah katanya yang penting: ngrumaosi (merasa), nggadhahi (mempunyai), nagari (negeri). Dengan kata lain, sebuah "negeri" tak pernah benar-benar hadir di depan kita—ia hanya dilambangkan dengan sehelai bendera—namun kita merasa perlu mempunyainya.
Untuk apa sebenarnya? Seandainya ia berada bersama mereka yang sekarang menentang "globalisasi", Samadi akan mengatakan, "Tidak, kita ternyata tak bisa hidup di dunia tanpa tapal batas." Pada setiap orang selalu ada kebutuhan untuk tergabung dalam sebuah komunitas, dan sebuah "imagined community" seperti dalam uraian termasyhur Bennedict O'Anderson tentang "nasion" bisa sangat berarti bagi hidup seseorang.
Saya teringat Samadi. Tiap pagi ia memandang ke arah Sang Merah Putih, dengan rasa sayu. Tapi saya tak bisa menduga, adakah ia seorang "nasionalis". Ia berbicara tentang "negeri", tapi pada saat yang sama ia menampik "Negara". Nasionalisme, setidaknya dalam sejarah Indonesia dan di seantero geografi Asia dan Afrika ketika melawan kolonialisme dan menang, berangkat dari ide kedaulatan. Kedaulatan ini ditegakkan di sebuah wilayah, dengan sejumlah warga dan sebuah kekuasaan yang disebut "Negara", untuk menjaga dan mengelola semua itu.
Maka kaum nasionalis tak selamanya ingin membedakan, apalagi memisahkan, "Negara" dari "negeri". Mereka cenderung mempercayai bahwa ada hubungan alamiah antara Negara ("kekuasaan") yang berdaulat di satu wilayah dan penghuni wilayah itu. Tapi Samadi membuktikan tidak.
Mungkin ia memang bukan seorang nasionalis, mungkin ia seorang patriot. George Orwell menggambarkan "patriotisme" sebagai pengabdian kepada satu tempat tertentu dan satu cara hidup tertentu yang dianggap yang terbaik di dunia, tapi hal-hal yang tak hendak dipaksakan kepada orang lain. "Patriotisme pada dasarnya defensif," kata Orwell. Sebaliknya nasionalisme "tak terpisahkan dari hasrat akan kekuasaan".
Saya kira Samadi ingat akan Kumbakarna. Kesatria bertubuh raksasa dan bertampang seram itu mempertahankan negerinya dari serbuan pasukan Rama, meskipun ia menampik Rahwana, yang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Alengka, tanah airnya sendiri. Kumbakarna tahu ia akan kalah—konon ia mengenakan pakaian putih sebelum berangkat perang—dan ia memang gugur. Tapi ia telah menunjukkan, seperti Samadi yang terpojok tapi mengibarkan bendera, bahwa kaum nasionalis bisa keliru. "Negeri", berarti wilayah dan penghuninya, dan "Negara" bisa berselisih tajam.
Itulah yang dicemaskan Bung Hatta pada tahun 1945. Ia menyarankan agar hak-hak warga negara dicantumkan dalam konstitusi. Sebab, seperti yang terjadi di Jerman di bawah "Nasionalisme-Sosialisme", Negara dapat mengekang warga, atas nama sebuah totalitas, atas nama persatuan dan kesatuan, dan bisa membentak, "Kalian ambaléla!" seperti hardik Presiden Soeharto ke arah para petani yang bertahan di Kedung Ombo
Ketika sejumlah orang membela Samadi dan kawan-kawannya dengan mengerahkan bantuan organisasi-organisasi di luar negeri, untuk membuat Bank Dunia menyimak protes di dusun-dusun Kemusu itu, seorang menteri juga menghardik, "Tuan-tuan bukan nasionalis!"
Antara ambaléla ,"memberontak", dan "bukan nasionalis" ada kaitan yang langsung: sebuah penolakan mutlak. Yang beda berarti "asing" atau "ganjil", sesuatu yang layak ditenggelamkan, seperti dusun Samadi di Nglanji itu, untuk menciptakan sesuatu yang kukuh, padu.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo