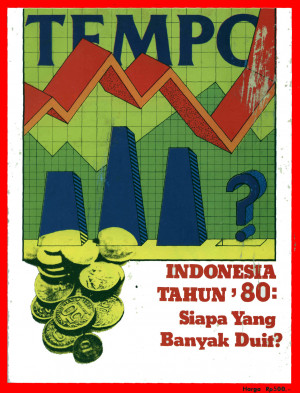INDONESIAN COMMUNISM UNDER SUKARNO: Ideology and Politics
oleh: Rex Mortimer, 464 halaman,
Oxford University Press & Cornell
University Press, 1974
REX Mortimer tak melihat matahari tahun 1980. Ia meninggal 31
Desember 1979. Harian The Sydney Morning Herald 2 Januari yang
lalu menulis obituari pendek untuknya -- menyebutnya sebagai
"tokoh berpengaruh dalam politik Kiri (Australia)" ini. Umurnya
53. Di Australia bulan November yang lalu saya sudah mendengar
ia dirawat karena kanker.
Saya bertemu dengannya di Sydney pertengahan 1978, diperkenalkan
oleh Herbert Feith, sarjana ilmu politik yang sangat
mengaguminya itu. Pembicaraan kami tak sampai dua jam, di sebuah
tempat sarapan di hotel. Tapi Mortimer adalah orang yang tak
mudah dilupakan bukan karena ia begitu cemerlang, tapi karena ia
begitu bersahabat.
Ia dianggap, seperti kata The Sydney Mornng Herald "pengaruh
yang terkemuka di masa sesudah perang dalam politik sayap kiri
Australia." Pagi itu yang saya hadapi di seberang meja dan
cangkir-cangkir kopi ialah seorang cendekiawan yang santai,
bercelana pendek, ramping schat dan necis, dengan kulit baru
terpanggang matahari liburan. Umurnya waktu itu sudah di atas 50
dan kepalanya tak kelihatan berambut lagi, tapi ia nampak sedang
menyenangi hidup. Ia bukan tipe "kiri" yang hanya bermodal
protes.
Mungkin ia seorang yang sudah jauh berjalan, dengan perubahan di
sana-sini. Ia bergabung dengan Partai Komunis Australia sejak ia
masih studi hukum di Universitas Melbourne, tapi di tahun 1968,
ketika ia berkunjung ke Yugoslavia, Uni Soviet menyerbu
Cekoslowakia. Ia mengundurkan diri dari Partai.
Itu tak berarti ia berubah dari dasar-nya. Buku Showcase State
(1973) yang ia susun dari tulisannya sendiri bersama empat orang
lain, adalah sebuah serangan atas Orde Baru dengan bertolak atas
premis Marxis. Tentu saja harus dicatat: di dalamnya ada usaha
untuk mempersoalkan konsep development (yang dalam bahasa
Indonesia diartikan "pembangunan", tapi tentu saja tidak tepat),
suatu diskusi yang tak sepenuhnya berciri Marxisme pra-1960-an.
Tapi Showcase State sungguh tak mengesankan. Setelah David
Ransom menulis dalam majalah Kiri-Baru yang mengkilap, Rampart
dan membuat terkenal kata the Berkeley Mafia sederet ulasan
Kiri-Baru tentang Orde Baru tak lagi baru: cuma pengulangan
sebuah tesis, dengan sedikit variasi.
Umumnya ditafsirkan bahwa Orde Baru kurang-lebih hanyalah
ciptaan kepentingan Barat, CIA, perusahaan multinasional dan
lain-lain sejenisnya -- suatu tafsiran sejarah yang amat
mekanistis dan juga mengandung kecongkakan. Sebab di sana
kekuatan sosial-politik di Dunia Ketiga digambarkan seakan-akan
cuma boneka, bukan sesuatu yang juga lahir dari pergulatan
impian dan kenyataan negeri itu sendiri. Seraya bicara soal dosa
orang kulit putih, tafsiran sedemikian sebenarnya pantulan lain
dari rasa supremasi kulit putih.
Sebab itulah para cendekiawan "progresif" dari Barat biasanya
(walaupun sering dikagumi) banyak yang terasa tak enak di hati.
Hidup dalam suasana kemerdekaan berpikir dan ketenteraman
sekitar, mereka berbicara dengan lancar tentang Dunia Ketiga --
tanpa secara eksistensial terlibat dalam keringat, lumpur dan
darah Dunia Ketiga itu sendiri. Mereka tak menanggung beban
sejarah yang di sini, pada kita, tak terelakkan.
Saya ingat Prof. Wertheim, sebagaimana dikutip dalam satu
wawancara dengan wartawan Salim Said yang diterbitkan di tahun
1970. Gurubesar Belanda ini, seraya mengecam Indonesia post
Sukarno, menganjurkan agar negeri ini menempuh saja jalan
pembangunan gaya RRC. Wertheim adalah seorang sarjana yang
martabat akademisnya tak usah diragukan lagi. Tapi adakah ia
mempertaruhkan dirinya untuk ide semacam itu, yang ia yakini
dengan penuh semangat, sebagaimana jutaan orang Indonesia harus
mempertaruhkan diri dan anak-anak mereka untuk memilih (atau
menolak) "resep" RRC-nya?
Mortimer, setidaknya dalam pembicaraan di tahun 1978, tak
berbicara tentang resep. Tahun 1978 bukanlah tahun yang baik
bagi para pembela revolusi di Asia. Pembunuhan besar-besaran
oleh kaum revolusioner Kambodia (lebih dari yang terjadi di
Indonesia 1965-66), berbaliknya RRC dari jalan Maois radikal,
makin absurdnya pemujaan terhadap pribadi Presiden Kim Il-sung
di Korea Utara, mulai mengalirnya "orang usiran" dari Vietnam,
dan konflik yang makin bengis antara kekuatan-kekuatan komunis
sendiri -- semua itu pasti membebani pikiran dan hati seorang
kiri seperti dia.
Tapi saya tak tahu pasti. Ia hanya mengesankan kepada saya
sebagai seorang yang redup. Ia bicara tentang periode ini,
tatkala masalah-masalah begitu besar dan ideologi (termasuk
Marxisme-Leninisme) begitu terasa lumpuh untuk menjawabnya. Ia
mungkin menyadari, bahwa buah pikiran terpenting tentang jalan
lain bagi masa depan manusia dewasa ini tak ada yang lahir dari
negeri-negeri sosialis. Ia pasti tahu bahwa gagasan radikal yang
sebetulnya kini justru lebih dekat kepada Gandhi ketimbang
kepada Lenin -- betapapun masih mentahnya gagasan itu.
Saya rasa bagi orang seperti Mortimcr kesadaran sedemikian bukan
mustahil. Biar pun Showcase State terasa klise dan agak
pretensius, Indonesian Communism Under Sukarno menunjukkan
Mortimer yang tajam justru dengan hati yang dingin. Ia bisa
menjaga jarak. Tentu karena buku ini bukan suatu pembelaan bagi
PKI, melainkan suatu evaluasi tentang kegagalan Aidit. Di
samping itu: juga karena Mortimer memang tak dogmatis.
Bagi Mortimer, masalah besar PKI menjelang kehancurannya,
sepanjang masa "Demokrasi Terpimpin" Bung Karno, adalah masalah
ideologis. PKI di bawah Aidit, sejak 1954 mengambil strategi
yang kemudian menimbulkan persoalan besar. Dalam bertumpu pada
front persatuan nasional, Partai tak begitu mengutamakan
"perjuangan klas" dan soal kepemimpinan kaum komunis dalam front
itu. Itu tak berarti PKI di bawah Aidit tak pernah mencoba
perjuangan klasnya sendiri. Tapi aksi sepihak 1964 di desa-desa
seperti sebelumnya usaha-usaha menggerakkan buruh di kota-kota,
praktis gagal.
Aiditisme
Dapat dibayangkan bahwa hal itu menimbulkan persoalan di antara
pimpinan Partai. Buku Mortimer mungkin buku pertama yang
menceritakan pertentangan lama antara tokoh seperti Njoto disatu
pihak (yang lebih menyukai sikap "jinak" dalam front persatuan)
dan tokoh seperti Oloan Hutapea, yang lebih menghendaki
independensi Partai, dari front persatuan dan pemerintah
Sukarno. Aidit sendiri mungkin tak sejauh Njoto, yang jadi
favorit Bung Karno, tapi ia toh pada akhirnya tak menyebabkan
Partai siap, dengan pilihan jalan lain, ketika saat yang
menentukan tiba.
"Aiditisme" mendapat kecaman, dari sisa-sisa pimpinan PKI.
Partai yang demikian besar (mengaku beranggota 20 juta) ini
memang kemudian bukan saja terbukti tak efektif, tapi juga Aidit
akhirnya melibatkan diri dalam apa yang disebut oleh sisa-sisa
PKI sebagai "adventurisme" petualangan yang berbentuk Gerakan 30
September. Yang juga tak disangka-sangka ialah bahwa Partai yang
punya organisasi baik ini juga dalam saat krisis
berlubang-lubang dengan tindakan saling mengkhianati antar
sesama kader.
Mortimer tak seluruhnya menyalahkan Aidit. In retrospect the
odds seem always to have been against the Communists even when
they were making they greatest advances. Yang perlu direnungkan
mungkin ialah kenapa demikian. Tidakkah ini mungkin karena
sejarah Indonesia dari 1945 sampai dengan 1965 telah berkembang
sedemikian rupa, hingga apa pun yang diusahakannya untuk menang,
sudah terlambat?
Bagaimana pun pemimpin mereka dibesarkan dalam ethos nasional,
lebih dari ethos klas, PKI tak kunjung berhasil memperoleh
legitimasi sehagai suatu kekuatan nasional. Perkembangan
masyarakat Indonesia dan riwayat hidupnya tidak menjadikan Aidit
seorang Ho Chiminh seorang bapak bangsa dan juga pemimpin partai
komunis.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini