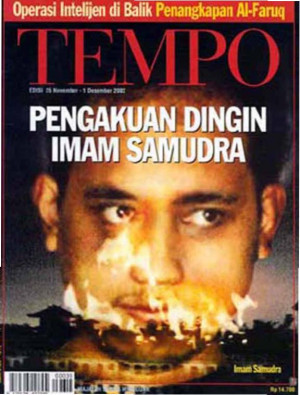SETELAH gesekan selo dan biola Gugur Bunga dipersembahkan syahdu bagi arwah tragedi Bali, trofi patung karya G. Sidharta diserahkan kepada para pemenang Indofood Art Awards 2002 di Museum Gajah, Jakarta, 8 November lalu, berbentuk deformasi Dewi Saraswati, lambang pengetahuan, dan Dewi Sri, lambang pangan. Di samping Philip Morris Award, itulah lomba seni rupa yang mencoba menjaring karya-karya terbaik.
Sesuai dengan pepatah Latin terkenalde gustibus non est disputandum—"memang demikian adanya, setiap hajatan memiliki selera tertentu"—dewan juri menentukan pilihannya. Mereka, Agus Dermawan T., Fuad Hassan, A.D. Pirous, Agung Rai, dan Edi Sunaryo, istilahnya, mencari karya yang mampu mengangkat realitas Indonesia dengan benak Indonesiawi. Para juri memberikan tempat luas bagi tema wayang, suasana pedesaan, perahu-perahu nelayan, panjat pinang, figur-figur anak, perempuan, elemen candi, tari tema-tema "konvensional" keseharian, serta gaya-gaya post-traditionalist, dekoratif, dan abstrak. Semua nominasi dipilih yang memberikan efek liris. Pun karya yang memakai bahan mix media. Karya yang memberikan efek problematik, mencekam, parodi hitam, atau permainan konseptual tak dipilih.
Para peserta lomba bertema "realitas sebagai ilham, warisan budaya sebagai acuan" ini beragam. Ada finalis yang pernah ikut Philip Morris Award. Misalnya Budi Ubrux, yang menang Philip Morris Award tingkat Indonesia tahun 2000. Seperti pada karyanya yang dulu, ia bermain dengan gambar imaji bungkusan koran. Atau Sudarwanto Budi Raharjo dan Yusuf Susilo Hartono, yang tahun lalu menjadi finalis Philip Morris Award. Beberapa perupa yang dikenal suka performance art berpartisipasi. Misalnya Nandang Gawe dari Bandung, yang mengirim kolasenya di atas kanvas. Ada yang dari angkatan tua seperti Kok Poo, pelukis realis, yang pernah belajar pada Dullah tahun 1950-an, atau Mulyadi W., pelukis dekoratif, bekas ilustrator majalah Kawanku tempo dulu itu.
Pada titik ini, karya salah satu pemenang utama, Sapto Sugiyo Utomo, Lorong Kebebasan, memang menonjol di antara finalis. Lukisannya memposisikan kita bagai menatap dari ketinggian. Ini lukisan tentang 13 anak dalam kardus menonton televisi. Mata kita seolah melihat dari atas, menyaksikan gundul-gundul mereka saja. Karya ini mengingatkan bahwa dalam seni rupa kita sedikit eksperimentasi dalam sudut pandang. Rata-rata mata penonton dihadapkan pada satu dimensi arah. Sementara itu, di Barat, Les Meninas, karya Diego Velasquez, 1656, misalnya, sampai mengundang diskusi filsafat persoalan representasi. Ataukah Sapto sadar akan hal itu atau karyanya sekadar kebetulan?
Beberapa finalis yang dikenal telah memiliki gaya dan mengembangkan tema khas masuk nominasi. Sebut saja Agung Mangu Putra, yang terkenal melukis pembusukan ikan-ikan. Karyanya di lomba ini adalah Ikan-Ikan dalam Kenangan. Juga I Wayan Asta, sang spesialis monyet, yang imajinasinya akan kera sangat hidup. Ia menampilkan lukisan "monyet": Tumbangnya Presiden Rahwana dan Rakyat Kebenaran pun Berpesta. Salim M., pelukis poster anak, mengajukan Peristiwa Kecil di Jalan Desa. Melodia, yang suka melukis becak dan sepeda, menampilkan karya "becaknya": Yang Terjebak di Antara Ruang Waktu. Lukisan mereka itu rasanya bukan karya terbaik—dibandingkan dengan pameran-pameran tunggal mereka sebelumnya—tapi dibuat tahun ini, sesuai dengan prasyarat lomba.
Tak terelakkan juga adanya seleksi yang longgar. Gusti Agung Wiranata, dengan karyanya Tajen Masih Ada—yang sangat bergaya Walter Spies—cukup mengherankan mengapa menjadi finalis. Toh, lomba ini menampilkan karya yang reflektif seperti Mengapa Harus Mencari Nada, karya Rahmat Subani Irfani, yang mengeksplorasi gelap-terang. Juga gambar dekoratif A.Y. Kuncana, Catatan Harian Seorang Pemburu, cukup segar. Menampilkan kotak-kotak—seperti ilustrasi atau komik buku anak—gambar ini berkisah tentang pemburu macan, dengan catatan teks: huruf hanacaraka.
Tak ada pemenang tunggal dalam award ini. Tapi ada tiga pemenang utama, yang style-nya berbeda-beda. Tahun depan diagendakan lomba ini akan lebih spesifik, dengan mengangkat tema "5 tahun mengendapkan perubahan (reformasi 1998-2003)". Itu lebih baik. Di sini akan terlihat jelas mana karya yang melihat politik secara klise dan mana yang sublim. Imajinasi, teknik, pemilihan tema, kedewasaan, dan ketenangan membaca politik dengan perspektif lain di sini dipertaruhkan. Tahun depannya lagi (2004) direncanakan lomba khusus patung. Tentu ini ada efeknya bagi seni lukis Indonesia (baca: pasar). Agaknya perhatian untuk kesenian seperti ini perlu diikuti (dicermati) terus.
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini