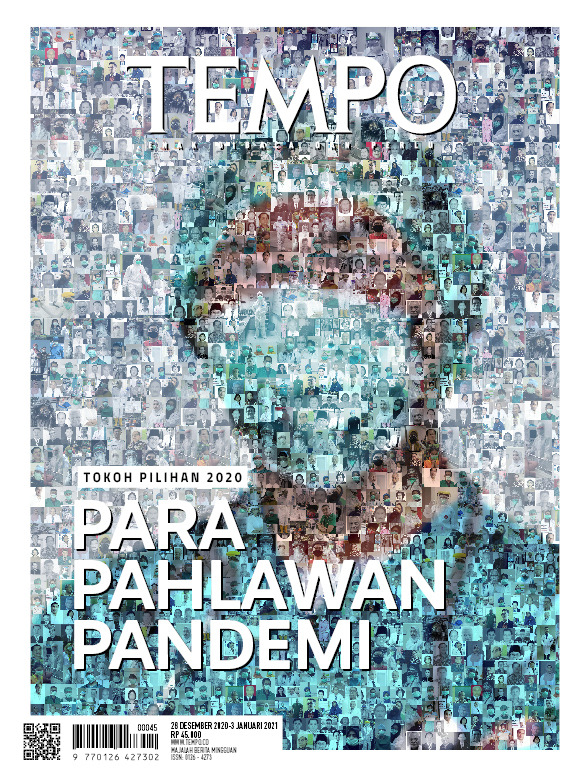Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

KRITIKUS sastra Marxis, Frederic Jameson, berpendapat bahwa filsafat mengidap obsesi kronis akan kesempurnaan (plenitude) dan penguasaan (mastery). Filsafat mengklaim diri bersifat self-sufficient dengan pelbagai perangkat yang saling mengunci dan otonom. Dengan itu filsafat memandang dirinya tak tersentuh usia. Teks-teks karya the great dead authors, seperti Plato, Aristoteles, Hegel, Kant, dan Nietzsche, dilihat sebagai sumber kebenaran yang lepas dari waktu dan konteks. Seakan yang mereka tulis untuk manusia di zamannya juga ditulis untuk manusia di zaman kita.
Di sini filsafat berbeda dengan teori dalam ilmu-ilmu sosial. Teori lekang oleh waktu, ia punya usia yang terbatas. Teori merasakan serangan, gugatan, dan kematian. Karena teori bisa mati, teori mengetatkan diri dengan disiplin, kekhususan, dan ketajaman. Herry Priyono memimpin Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, perguruan tinggi filsafat terbaik yang dimiliki Indonesia, dengan disiplin seorang ilmuwan sosial. Ia ingin menyembuhkan penyakit dan obsesi kronis filsafat akan kesempurnaan dan keabadian yang sering kali menjebak dan menjerumuskan. Ia punya alasan kuat.
Di Indonesia, filsafat identik dengan teks dan hal-hal abstrak biyang biying (dari bahasa Inggris being, konsep kunci dalam ontologi). Hal ini dianggap gagal memahami dan memberikan solusi atas masalah-masalah nyata. Filsafat dianggap “ilmu sulit” tapi sekaligus diremehkan sebagai “tanpa faedah”. Di sisi lain, barangkali karena merasa akrab dengan buku-buku klasik tentang prinsip-prinsip mengenai manusia dan dunia, mahasiswa filsafat sering kali merasa otomatis “langsung pintar” sehingga berani berkoar-koar menjelaskan segala soal di segala bidang: dari soal korek kuping hingga peredaran planet-planet. Mentalitas ini pula yang barangkali membuat banyak orang yang belajar filsafat suka menyebut diri filsuf bahkan sebelum skripsi dan tesis masternya tamat.
Herry Priyono mengubah dan menghancurkan klaim-klaim dan budaya semacam ini di Driyarkara. Filsafat mesti menjadi disiplin yang serius dan penuh komitmen, bukan deretan kata keren untuk memikat pembicaraan atau untuk menjustifikasi gaya bohemian yang longgar. Itu sebabnya Herry sebal terhadap budayawan. Baginya istilah itu menunjuk subyek yang bisa berbicara apa saja tanpa disiplin dan tanggung jawab sosial-politik yang ketat. Filsafat jangan sampai identik dengan “budayawan”. Sewaktu menerima saya masuk di program doktoral, pesan pertamanya: “Jangan jadi budayawan”, nomor dua, “Jangan terlalu terpesona dengan Heidegger”.
Ia menyukai kecermatan dan mendorong keunggulan dengan memprovokasi mahasiswanya berani high profile, tampil, dan terlibat dalam pelbagai urusan publik, tapi harus tetap rendah hati. Ia ingin filsafat—melalui para pelajarnya—berkontribusi konkret untuk republik ini. Itu pula yang mendorongnya membuka program program pascasarjana filsafat secara lebih luas tapi selektif. Di sini ia bekerja sama dengan Dr Karlina Supelli. Beberapa belas tahun lalu, kalau Anda menyebut belajar di Driyarkara, orang akan berpikir Anda sedang belajar teologi dan tengah bersiap-siap menjadi pastor Katolik. Mereka berhasil mengubah pandangan sempit ini. Kalau hari ini Anda ke Driyarkara, Anda akan bertemu orang dengan latar belakang profesi yang beragam.
STF Driyarkara bukan perguruan tinggi profesi, ia menawarkan Ex Philosophia Claritas! Dari filsafat muncul kejernihan. Filsafat menjadi alat bantu untuk menerangi dan mengurai benang kusut pelbagai masalah nyata dari pelbagai profesi dan bidang kehidupan. Ini mirip dengan apa yang dikemukakan sosiolog Amerika, C. Wright Mills, mengenai “imajinasi sosiologis”, yakni kemampuan untuk mentransformasi privatmillie menjadi public engagement. Hal serupa juga diinginkan dalam belajar filsafat: mencapai “imajinasi filosofis”, yakni kemampuan untuk merefleksikan dan mentransformasi pelbagai private milieu menjadi sesuatu yang berharga secara sosial. Berfilsafat bukanlah lamunan di kamar yang steril, berfilsafat adalah terlibat. Yang unik dari STF Driyarkara adalah, sekalipun punya karya dan kontribusi besar dalam bidang filsafat, semua dosen dan guru besarnya yang paling produktif dan dihormati selalu waras dan rendah hati. Mereka tidak pernah menyebut diri sendiri sebagai “filsuf”.
Herry berperawakan kecil tapi, seperti belati, ia keras, serius, dan tajam. Ia pastor Jesuit, tapi orang berbicara dengan dia bukan untuk urusan-urusan spiritual apalagi klerikal. Orang lebih sering ingin mendengar dia sebagai intelektual independen yang menyuarakan bahaya pendekatan pasar yang brutal dan belakangan tentang bahaya korupsi terhadap keutuhan republik. Herry belajar sosiologi dan dididik dalam tradisi empirisme Inggris. Ia menguasai filsafat ekonomi dan ekonomi-politik. Ini yang membuat dia lebih “konkret”dalam menjelaskan filsafat, sekaligus merefleksikan sikap intelektualnya terhadap keadilan.
Saya pernah mendengarkan ceramahnya tentang kota, disajikan dengan kejernihan filosofis plus sokongan data-data empirik yang detail dan rinci. Untuk menunjukkan ketimpangan di kota-kota, ia menghitung dan mengkontraskan, misalnya, data jumlah mal dan bank-bank besar dibanding jumlah koperasi rakyat dan BPR. Ekonomi-politik juga membuat dia memiliki pandangan lebih luas mengenai pluralisme, identitas, dan ekonomi. Ia berpandangan kaum intelektual dan civil society di Indonesia harus tetap memusatkan diri pada soal “politics of distribution” ketimbang terlalu terjebak dalam “politics of recognition”. Pada Oktober lalu, selepas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kami sempat bertukar pesan WhatsApp. Menurut dia, undang-undang itu hanya bisa cocok dalam dua kemungkinan: di sebuah negara kapitalis yang sangat maju (ketika hak-hak dasar warga sudah terjamin) atau di sebuah negara yang dijamin dengan gaya fasis Carl Schmittian.
Carl Schmitt adalah filsuf dan ahli hukum Jerman yang menolak demokrasi liberal. Bagi Schmitt, prinsip-prinsip liberal, seperti pluralisme, publisitas, keterbukaan, deliberasi, representasi, praktik pemisahan kekuasaan, dan prinsip mayoritarian dalam pemilihan, adalah kekeliruan dan berbahaya karena bisa melumpuhkan suatu negara modern. Prinsip-prinsip demokrasi liberal dinilai menghambat kemampuan negara untuk mengambil keputusan guna menjawab pertanyaan mengenai mana kawan dan mana lawan, lambat serta ringkih dalam mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan yang tiba-tiba. Menurut Schmitt, politik adalah urusan keputusan dan tetek-bengek demokrasi liberal menghambatnya. Karena itu, ia menganjurkan sejenis otoritarianisme guna menjamin semacam “homogenitas substansial”. Fasisme Carl Schmittian bertolak dari pandangan mengenai efisiensi dalam politik dan menganggap demokrasi cuma bikin repot. Peremehan terhadap demokrasi ditolak Herry Priyono.
Di masa Orde Baru, karya-karya para pengajar Driyarkara: Franz Magnis-Suseno, Sindhunata, dan Fransisco Hardiman yang berpusat pada teori kritis Mazhab Frankfurt banyak dibaca orang dan menyumbang tumbuhnya kesadaran kritis di kalangan aktivis dan generasi muda. Pada masa yang sama, Herry mengabdi sebagai wakil direktur di Institut Sosial Jakarta yang dipimpin sahabatnya, Sandyawan Sumardi. Ia bekerja untuk kaum miskin di Jakarta. Dalam pergolakan 1998, Sandyawan mengisahkan Herry yang sebenarnya bekerja keras merumuskan semua laporan tragedi Mei 1998. Laporan ini kemudian menjadi pegangan bagi Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei yang dibentuk pemerintah. Pada 2006, dalam kekhawatiran mengencangnya politik identitas, ia bersama banyak kaum intelektual mendeklarasikan Restorasi Pancasila. Di luar itu, ia kemudian memusatkan dirinya mengurus STF Driyarkara dengan dedikasi penuh.
Sebagai intelektual ia mendorong pentingnya tindakan kolektif. Baginya yang politis harus menjadi yang sosial karena hanya dengan itu keadilan menjadi mungkin. Sebagai pribadi boleh dibilang ia pemalu, kurang menyukai kumpul-kumpul dan lebih suka bekerja di kamarnya. Anthony Giddens, gurunya di London sana, pernah mengatakan bahwa, dalam modernitas, self mengalami privatisasi yang radikal, termasuk kematian. Namun, kalau dia masih hidup, Herry pasti sadar bahwa kematian—termasuk kematiannya pada Senin, 21 Desember lalu—tak pernah bisa bersifat individual. Dalam setiap kematian, yang kehilangan bukanlah si mati, melainkan masyarakat dan dunia sosial tempat ia berada. Tubuh individualnya mati, tapi tubuh sosial dan komunalnya justru menampakkan diri.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo