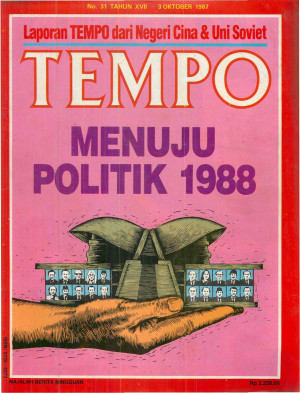SARAJEVO, di akhir tahun 1940-an tak banyak beda dengan kota-kota lainnya di Yugoslavia. Suasana suram Perang Dunia II masih menggantung di mana-mana, tapi Tito saat itu mulai melepaskan negerinya dari bayang-bayang Stalin (Soviet). Di masa transisi yang resah ini, beberapa anggota partai telah memanfaatkan situasi politik untuk kepentingan pribadi. Salah satu korbannya adalah Mesha, ayah dua anak. Suatu hari, Mesha (Miki Manojlovic) melontarkan tanggapan sarkastis terhadap sebuah sketsa politik yang dilihatnya di koran. Namun, sikap bebas yang ia perlihatkan di depan pacarnya justru membawa petaka. Ini tak lain karena cewek genit bernama Ankica (Mira Furlan), pacarnya itu, juga diincar oleh saudara ipar Mesha, yang anggota Partai Komunis Yugo. Setelah mengetahui kasus itu, sang ipar seakan mendapat angin. Maka, atas tuduhan melanggar hukum, Masha, yang bekerja pada kementerian perburuhan, dimasukkan ke kamp kerja paksa. Cerita bergerak melalui penuturan dan interpretasi Malik, anak bungsu Mesha, yang masih berusia enam tahun. Bagi Malik (Moreno D'E Bartolli) -- tokoh sentral film ini -- keberangkatan ayahnya ditafsirkan sebagai kepergian biasa di hari-hari kerja. Atau seperti cari angin keluyuran di saat-saat ayahnya menyambangi perempuan. Padahal, sang ayah berkutat di kamp kerja-paksa, sementara dalam pandangan si kecil Malik, semua itu sama saja dengan perjalanan bisnis. Dari sinilah dimunculkan judul film, When Father Was Away on Business (WFWAOB). Mengalir pelan -- melalui tingkah Malik yang lugu sekaligus jail -- cerita sepanjang 2 jam 20 menit ini menggelitik kita untuk tertawa sekaligus merasa getir. Pada suatu malam misalnya, sewaktu ayahnya hendak mencumbu ibunya, Malik dari kamar sebelah, mengganggu dengan membunyikan kelintingan. Pada puncaknya, ia bahkan kemudian menyusup ke ketiak bapaknya, yang langsung mendekapnya dan tertidur, sementara ibunya hanya bisa tersedu. Si nakal Malik -- diperankan dengan baik oleh Moreno Bartolli, bocah mungil berwajah bulat -- diceritakan suka berjalan dalam tidurnya. Emir Kusturica, sutradara yang ketika membuat film itu masih berusia 30 tahun (1985), tampaknya tak percuma memanfaatkan bakat Moreno, untuk menghadirkan potret multidimensi dari negerinya. Masa itu impian-impian Tito mulai tumbuh dan Yugoslavia seperti menyongsong horison-horison baru. Karya Emir -- dengan skenario dari penyair Abdulah Sidran -- yang kemudian meraih penghargaan Palme d'Or (Palma Emas) sebagai film terbaik pada Festival Cannes 1985, memang mewakili zamannya. Tetapi Emir menolak kalau produk dengan biaya total US$ 200 ribu dari Forum itu (salah satu produser pendukung new wave) dianggap sebagai kritik sosial. "Itu adalah sebuah ungkapan kepedihan hidup secara umum, tidak hanya dari sistem yang berlaku di negeri ini," katanya dalam sebuah wawancara. Sesudah merebut Palme d'Or, When Father Was Away on Business (Otac na sluzbenom putu) masuk nominasi Oscar untuk film asing terbaik, pada tahun yang sama. Hanya publik sinematek di Jakarta boleh kecewa, berhubung film Yugo terbaik itu tak ditampilkan dalam Pekan Film Yugoslavia di Taman Ismail Marzuki, 14-18 September lalu. BSF (Badan Sensor Film) melarang film itu diputar untuk umum, tanpa penjelasan terinci. Film-film yang boleh diputar -- kendati tetap karya-karya berkualitas -- kelasnya berada di bawah WFWAOB. Semuanya empat film: Balkan Ekspres, Season of Peace in Paris (Sezona Mira U Parizu), Heads or Tails (Pismo Glava), dan I Want to Live My Life (nocu Zivjeti). Kecuali Balkan Ekspres, yang tak menyentuh kendati warna perjuangan di masa pendudukan Jerman dijadikan latar belakang cerita -- film-film tersebut rata-rata bertemakan orang-orang yang patah menghadapi impian-impian dan lingkungannya. Kekecewaan karena tak berkesempatan menikmati WFWAOB cukup beralasan, kalau diingat bahwa sutradaranya telah menjadi duta angkatan baru di negerinya. Setelah melalui tahun 1970-an ketika industri film Yugo mengalami masa surut, Emir membuka lembaran baru sejak awal 1980-an. Dia lulusan Akademi FAMU, Praha (Cekoslovakia), sebuah pusat pendidikan perfilman yang prestisius di Eropa. Ia baru saja lulus dan mudik ke Sarajevo, sewaktu membuat Do You Remember Dolly Bell -- juga berdasarkan skenario Abdulah Sidran -- yang kemudian, 1981, beroleh penghargaan Golden Lion pada festival di Venesia. Sutradara seangkatan Emir, yang rata-rata lulusan FAMU, membuka tahur 1980-an dengan semangat dan keterampilan yang mengingatkan orang pada Francois Truffaut dan Jean Luc Goddard (Prancis) atau Frederico Felinni (Italia). "Mereka membuka era ketika tidak ada lagi tabu, tidak ada lagi kisah yang tak boleh diceritakan," tutur Jasmina Bosnic, Sekretaris Pertama Kedubes Yugoslavia di Jakarta. "Bahkan mereka menampilkan penafsiran mereka atas kebijaksanaan pemerintah, mengenai para pemimpin dan pergolakan orang-orang yang tertindas." Para sutradara muda (rata-rata berusia 30-an) ikut mengisi jumlah produksi negerinya -- 10 buah per tahun -- terutama di saat ekonomi lesu belakangan ini. Kebangkitan itu berkaitan erat dengan lembaga bernama Kinoteka, yang berdiri sejak 1955 dan tersebar di banyak kota besar. Di sini semua orang bisa menikmati karya-karya kelas satu, terutama yang lama, baik lokal maupun impor. Karya-karya empu sekelas Elia Kazan, Bergman, Fellini, sampai Akira Kurosawa bukan barang asing di sana. "Film memang merupakan salah satu seni yang mendapatkan perhatian besar di negeri kami," tambah Jasmina. "Kami lebih memilih ke gedung bioskup ketimbang nongkrong di bar-bar." Mohamad Cholid & Yudhi Soerjoatmodjo (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini