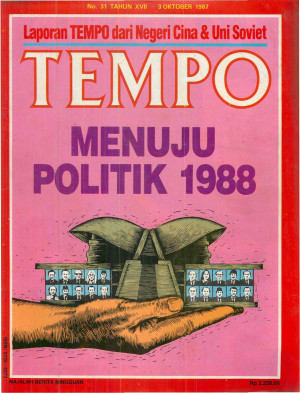INDONESIA perlu otomasi? Ya. Paling tidak, itu adalah pendapat Gustav Papanek, profesor ekonomi dari Universitas Boston, yang sedang dikontrak Bappenas. Ini memang lantas kedengaran seperti keterangan yang paradoksal. Mau dikemanakan para pekerja dan jutaan pencari kerja lainnya bila nanti otomasi menggantikan tangan-tangan mereka? Ternyata, ada kesalahan kesimpulan di sini. Didampingi asistennya, Prof. David Wheeler, Gus yang berbicara dalam acara makan siang di IPMI dua pekan yang lalu itu mengatakan, "Otomasi 'kan tidak selalu menggantikan atau menurunkan labor cost? Ia juga bisa instrumental untuk menurunkan material cost." Contohnya: industri pakaian jadi. Penjahitan akan tetap dilakukan oleh tenaga manusia sehingga ciri padat karya dapat dipertahankan. Tetapi pengguntingan bahan bisa memakai mesin-mesin otomat. Dengan cara ini penggunaan bahan yang mahal itu bisa dihemat. Artinya, otomasi sebagian (partial automatio) merupakan alternatif yang bisa dipertimbangkan. Tetapi ini bukan pemecahan yang mudah. Otomasi sebagian justru menuntut manajemen yang lebih baik untuk mengintegrasikan bagian yang diproses dengan sistem otomasi dan bagian yang diproses dengan tenaga manusia. Gus memastikan bahwa semiotomasi bisa menurunkan biaya bila dibandingkan dengan seratus persen padat karya, tanpa mengurangi kesempatan kerja bagi sumber daya manusia. Dengan contoh di atas: semakin cepat mesin otomasi menggunting bahan, semakin banyak tukang jahit diperlukan untuk menyelesaikannya. Gus juga mengatakan agar kita mulai melupakan mitos murahnya upah buruh di Indonesia. "Potensinya memang ada, tetapi sebenarnya 'kan tidak benar-benar murah ?" katanya. Kita harus ingat bahwa India, Pakistan, dan Bangladesh pun punya potensi yang sama di bidang ketersediaan buruh dengan upah murah. "Dan harap Anda catat pula bahwa bangsa-bangsa itu toh tidak statis. Mereka pun melakukan perubahan karena adanya perubahan peluang pasar," kata Gus. Memang, mereka sedang berubah. India, misalnya. Ekspor pakaian jadi dari India semula boleh dikata tak ada. Siapa, sih, yang mau beli tenunan kasar seperti itu? Ekspor pakaian jadi mereka pada 1972 hanya tercatat sebesar US$ 2 juta. Lima belas tahun kemudian, pada 1987, angka itu ternyata telah melonjak seribu kali lipat. Ekspor pakaian jadi mereka kini mencapai US$ 3 milyar. Dibandingkan tahun lalu, angka ini merupakan lonjakan pertumbuhan sebesar 50%. Para perencana di India kini berkeyakinan bahwa lima tahun mendatang ekspor pakaian jadi mereka akan meningkat tiga kali lipat, mejadi US$ 4 milyar setahun. Dalam artikel berjudul "Low Tech, High Growth" pertengahan September yang lalu, Time melaporkan bahwa pertumbuhan fantastis yang dialami sektor industri pakaian jadi India ini justru tidak dicapai dengan teknologi tinggi. Ini masuk akal bila diingat bahwa 80% dari 8.000 pengusaha pakaian jadi India adalah industri berskala kecil. Lalu, apa kiatnya? "Wah, kami 'kan punya kreativitas dan keterampilan berinovasi," kokok gagah seorang pengusaha pakaian jadi di sana. Contoh? Ini dia! Dunia kini sedang gandrung pakaian yang sebelumnya sudah dicuci dengan batu. Stone-washed. Itu memang bukan sekadar istilah. Betul-betul pakaian yang sudah jadi itu dicuci dengan batu, sehingga menciptakan warna belel yang -- katanya -- adem dipandang. Bahkan ada yang dicuci dengan es, ice washed. Di negara-negara industri seperti Korea atau Hong Kong, pencucian dengan batu atau es itu dipecahkan dengan teknologi. Tetapi, di India lain lagi. Pakaian itu dicuci di sungai, lalu diperas kuat-kuat -- dengan tenaga manusia, tentu saja. Dalam keadaan masih terpuntir itu pakaian lalu diinjak-injak dengan kaki. Seperti proses membuat tempe. Pakaian itu memang tidak lantas jadi tempe, melainkan jadi punya efek seperti stone-washed. Dan biarlah India tetap India dengan tidak mengatakan bahwa pakaian itu sebenarnya hasil foot-washed, tetapi tetap diaku stone-washed. Boleh saja dunia terkecoh. Tetapi, sudah lebih dari sejuta celana hasil injakan kaki orang India itu kini beredar di berbagai pasar Eropa. Dan orang masih terus menginginkan pakaian jadi dari India. "Dunia kini 'kan sedang keranjingan mode katun," kata seorang pengusaha India lainnya. "Dan masyarakat yang canggih itu tidak mau katun sintetis. Mereka mau katun yang asli. Jadi, selama kami dapat melahirkan warna dan corak katun baru, industri pakaian jadi India tak punya istilah surut." Boleh juga keyakinan itu. India telah memanfaatkan buruh murahnya dengan cara yang kreatif. Pakistan dan Bangladesh sudah pasti mengikuti jejak itu. Lantas, kita? Mau tetap low tech. Atau siap ke otomasi untuk merebut bisnis ini dari Korea dan Taiwan? Bondan Winarno * judul "Low Tech" pernah dipakai Kiat dua tahun yang lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini